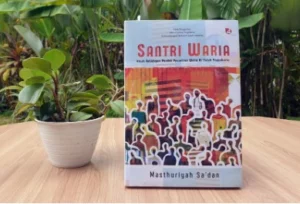Saya menolak upacara kematian yang harus ‘dirayakan’ secara meriah, karena bagi saya perpisahan bukanlah sebuah ‘pesta’ duka.
*Ika Ariyani- www.Konde.co
Tulisan ini saya tulis untuk mengingat sejenak ketika ayah saya meninggal dunia pada usia 41 tahun dalam posisi ibu saya tidak bekerja.
Waktu itu umur saya 14 tahun, dan adik saya yang bungsu masih kelas 3 SD. Betapa bingungnya kami sekeluarga pada saat itu.
Kami berpikir panjang waktu itu: dengan cara apa harus mengubur ayah kami? Karena kami harus membeli tanah, menyelenggarakan upacara pemakaman sebagai tradisi keluarga yang tak sedikit dananya.
Lalu kemudian datanglah saudara yang membuat ibu saya merasa sedih. Mereka menawarkan catering, harga hewan yang akan dijadikan simbol tradisi, peti mati dari kayu jati yang cukup mahal bagi kami, meminta ongkos pesawat karena ada saudara yang ingin melayat dari Kalimantan, desain kuburan yang mahal, bahkan ada yang menawarkan menjadi agen untuk segera menjual mobil kami satu-satunya.
Situasi ini memang tak membuat nyaman, apalagi bagi kami yang sedang berduka dan patah hati. Kami bahkan harus memecah pikiran untuk memenuhi tradisi-tradisi ini.
Kami tahu, mereka datang dengan niat baik sebagai tanda peduli pada kejadian yang kami alami. Namun, jika bisa memilih, kami ingin agar ayah segera dimakamkan secara cepat dan sederhana, tidak usah menunggu sampai 3 hari baru dimakamkan seperti tradisi keluarga, dan ingin acara yang sederhana saja sehingga tidak harus menanggung semua prosedur yang mahal itu.
Tapi sepertinya kami tidak punya pilihan saat itu. Saudara-saudara mendesak kami melakukan acara yang menurut mereka sakral dan harus sempurna. Amatlah disesali ketika sedang berduka, kami juga harus mengeluarkan banyak uang, bahkan kami sampai berhutang untuk sebuah acara duka.
Padahal hidup kami harus terus berjalan. Tanpa ‘pesta dukapun’ hidup kami akan terus berjalan. Pasti tak banyak orang berpikir soal ini.
Kami sudah membayangkan, hari-hari kemudian rumah menjadi sepi kembali, tinggallah kami yang patah hati sangat dalam dan tidak bisa membayangkan bagaimana masa depan kami tanpa Ayah sebagai satu-satunya pencari uang untuk keluarga. Jikapun ada saudara yang berkunjung sesudah itu, mereka selalu mengulang pesan agar Ibu saya tidak ke Jawa (asal daerah Ibu saya) dan menikah lagi. Hanya itu pesannya. Mereka bahkan tidak tahu jika kami mengalami kesulitan ekonomi, hal-hal yang mungkin tidak terlintas dalam pikiran saudara-saudara kami.
Saya lalu berpikir, mengapa kedukaan harus ‘dirayakan’ dengan pesta? Karena menurut saya, sebuah perpisahan bukanlah pesta. Jika ada saudara yang bermaksud datang untuk menghibur kedukaan ini, setidaknya kami ingin menyambutnya secara sederhana. Ayah adalah orangtua yang selama ini memberikan support ekonomi banyak pada hidup kami. Ketika ia meninggal, saya dan ibu harus merancang ekonomi keluarga kami selanjutnya
Lalu, dengan pengalaman ini, apakah saya boleh memutuskan bagaimana bila saya meninggal nanti? Bolehkah saya meminta agar tidak ada acara duka yang memakan biaya? Bolehkah saya menyumbangkan organ tubuh saya? Karena ini menjadi bagian dari keputusan saya yang tidak suka menjadi beban bagi orang lain dan agar di hari kematian saya, saya masih berguna untuk orang lain.
Jika saat ini sudah banyak pernikahan yang digelar secara sederhana, bahkan hanya mengurus surat pernikahan saja tanpa acara, mengapa tidak untuk acara kematian?
Banyak teman-teman saya yang menikah secara sederhana, hanya mengundang 50 orang teman, setelah mengucapkan janji pernikahan, lalu makan secara sederhana dan pulang. Bahkan ada yang hanya mengundang 10 orang teman dekat saja. Karena ini hanyalah upacara, lebih penting lagi untuk melanjutkan hidup setelah itu.
Saya membayangkan ibu saya, seorang janda yang tidak bekerja, harus memenuhi tuntuan sosial untuk menyelenggarakan acara duka di luar kemampuan keuangannya. Bahkan harus berhutang untuk itu.
Bukankah lebih baik jika pengeluarannya dipakai untuk membiayai kehidupannya selanjutnya?
*Ika Ariyani, pengelola Instagram feminis “Masalah kita Semua”, aktivis perempuan, tinggal di Surabaya