Memang tidak semua masih memegang prinsip itu. Ketua Badan Permusyawatan Desa (BPD) Pengenjek, Herman kepada VOA menyebut hanya tinggal sedikit warganya yang fanatik pada aturan adat.
“Bisa kita kategorikan, masih ada yang masih memegang, ada yang tidak memegang adat lagi. Dalam kasus ini, orang tuanya bisa dikategorikan yang masih memegang adat, jadi yang bawa pulang enggak dikasih pulang kalau malam. Karena adat, jadinya mau tidak mau pihak laki-laki tidak bisa mengelak,” kata Herman.
Maksud pernyataan Herman, yang membawa pulang tidak dikasih pulang, adalah jika anak laki-laki mengantar pulang anak perempuan terlalu malam, maka dia akan dipaksa menikah oleh orang tua anak. Ada kesempatan untuk menolak tuntutan itu, tetapi keluarga laki-laki biasanya menerima karena enggan disebut tidak bertanggung jawab.
Menikah Demi Nama Baik
Kisah dua remaja ini menurut pengakuan NH, kedekatan mereka baru berjalan empat hari.
Mereka bertemu pada Rabu (9/9) dan pergi bersama ke salah satu tempat wisata di Lombok Tengah. Sekitar pukul 19.30 WITA, keduanya pulang dan tentu saja S mengantar NH ke rumahnya.
Ayah NH memandang kepulangan itu terlalu malam, dan karena itu pernikahan harus segera dilakukan. Bagi warga yang kuat memegang adat, jika tidak segera menikah, nama baik anak perempuan dan keluarganya akan tercoreng.
Tarik ulur terjadi, karena keluarga S meminta pernikahan tidak dilakukan secepat itu. Namun adat mengalahkan semua alasan.
Pernikahan keduanya tetap digelar pada Sabtu (12/9). Dalam rekaman video yang tersebar di media sosial, S yang memakai jas hitam duduk disamping NH dengan gaun pengantin warna karamel. Mereka dinikahkan seorang pemuka agama.
Seingat Herman, pernikahan anak di lingkungan desanya baru ini terjadi. Biasanya, mereka menunggu hingga lulus SLTA. Kasus ini, lanjut Herman, akan menjadi bahan pembicaraan di tingkat desa. Dia ingin ada peraturan desa yang mampu menekan angka pernikahan anak.
“Sejauh ini kami masih dalam rancangan. Kemarin baru kami bahas soal pembelian ambulans desa, sampah, dan pengembangan wisata. Tapi isu ini sebelumnya sudah kami sering bahas juga dengan tokoh dan pemerhati pendidikan. Jadi, ini sebenarnya sudah mengarah kesana,” tambah Herman.
Pengenjek adalah pedesaan di Lombok Tengah yang bertumpu pada sektor pertanian. Pengolahan ijuk, industri kerupuk, pandai besi, dan perikanan menjadi usaha sampingan. Karena faktor ekonomi dan kesadaran, pendidikan tinggi masih ada di luar jangkauan anak muda disana.
Namun, kata Herman, dalam lima tahun terakhir sudah ada generasi muda Pengenjek yang menjadi sarjana. Mereka yang fanatik pada adat terkait pemaksaan perkawinan ini, kata Herman setidaknya ada dua kelompok, yaitu warga lanjut usia atau yang tidak berpendidikan.
Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat jumlah perkawinan anak hingga saat ini setidaknya 148 kasus.
Kabupaten Lombok Tengah memiliki angka tertinggi, dalam sebuah penelitian yang dilakukan terhadap 131 sekolah di NTB dengan 48 perkawinan anak. Disusul kemudian Lombok Timur dengan 33 perkawinan, Lombok Barat 20 perkawinan, 17 di Kabupaten Bima, 11 kasus di Sumbawa, 9 kasus di Mataram, dua di Kota Bima dan Dompu, dan satu di Sumbawa Barat.
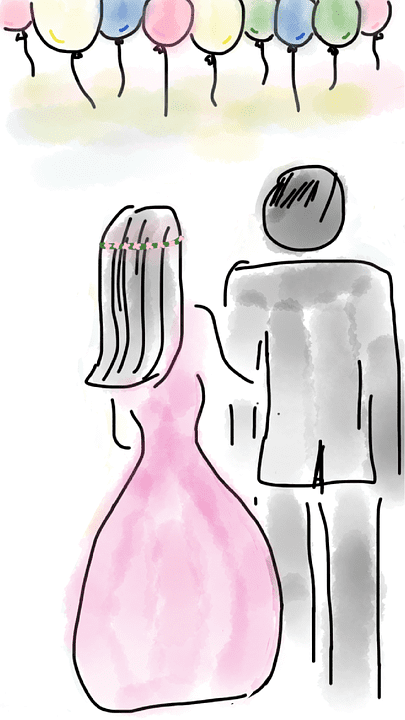
Kawin Tangkap di Sumba
Pemaksaan perkawinan atas dasar aturan adat sampai saat ini masih kerap terjadi, tidak hanya di Lombok tetapi juga di gugusan pulau Nusa Tenggara yang lain hingga ke Sumba di Nusa Tenggara Timur.
Ada istilah kawin culik di Lombok Timur, sedangkan di Sumba dikenal sebagai kawin tangkap. Semua ini berinti pada pernikahan paksa yang digelar atas tuntutan adat.
Di Sumba, tradisi pemaksaan perkawinan juga ada dalam bentuk yang berbeda. Unsur kekerasan dari laki-laki hadir dalam adat yang populer sebagai kawin tangkap.
Dalam sejumlah praktiknya, menurut Pendeta Aprissa L. Taranau, kawin tangkap terjadi ketika seorang laki-laki menangkap, dan bahkan bisa bermakna menculik perempuan untuk dijadikan istrinya secara paksa.
Aprissa adalah Ketua Persekutuan Perempuan Berpendidikan Teologi dan tinggal di Sumba. Setiap hari, dia mengambil pendekatan keagamaan untuk mengikis praktik kawin tangkap ini.
“Sangat berlapis perjuangan kami disini, karena bukan saja berhadapan dengan kekerasan seksual itu sendiri, tetapi karena diatasnamakan sebagai tradisi, adat atau budaya sehingga sangat sulit dihilangkan,” kata Aprissa.
Secara budaya, kata Aprissa, konteks kawin tangkap adalah pernikahan yang dilakukan tanpa proses melamar. Dari berbagai sumber tertulis, lanjutnya, budaya ini memang ada di Sumba. Sayangnya, tradisi ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai kawin tangkap.
Di masyarakat, khususnya anak muda, kemudian muncul pemahaman bahwa tradisi ini dilakukan dengan seenaknya menangkap seorang perempuan, dan kemudian memaksanya menikah.
“Kekerasan yang dialami perempuan berlapis, ditarik, dipaksa, dipukul kalau melawan. Kekerasan seksual juga karena ada pelecehan seksual, ada permaksaan perkawinan. Ada kekerasan psikis,” tambah Aprissa.
Di Sumba, Aprissa berjuang mengubah paradigma masyarakat yang mempertahankan praktik adat tersebut. Dia mengaku, gereja memiliki pekerjaan rumah untuk memberi pemahaman masyarakat mengenai nilai kesetaraan. Mereka juga terus bersuara, dengan harapan pemerintah mendengarkan suara korban, sehingga tergerak untuk membuat payung hukum yang mampu menghentikan tradisi ini.
Sampai saat ini, kata Aprissa, jika kasus sejenis terjadi, penegak hukum cenderung melihatnya persoalan adat.
“Selalu dibenturkan dengan pernyataan, bahwa ini adat dan dikembalikan ke keluarga, biar nanti mereka yang mengurus,” pungkasnya. [ns/ab]
(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)
(Sumber: Voice of America/ VOA)












