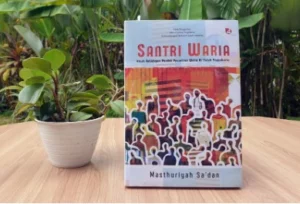Banyak peristiwa pelanggaran HAM yang mengendap begitu saja. Lihat saja, pelanggaran ini terjadi menimpa para pekerja seni, komunitas, korban HAM, perempuan, hingga di media.
Pidato Presiden Jokowi soal HAM dan dalam dokumen Nawacita hanya janji belaka. Hal ini terpapar dalam diskusi “Women’s Rights Are Human Rights” yang diadakan Institut Ungu untuk memperingati Hari Hak Asasi Manusia/ HAM 2020, 10 Desember 2020 melalui daring
Mutiara Ika Pratiwi dari Perempuan Mahardhika menyatakan bahwa agenda stop kekerasan seksual sebenarnya sudah ada dalam konvensi-konvensi internasional dimana Indonesia sudah meratifikasi ini, seperti dalam Konvensi CEDAW/ anti diskriminasi terhadap perempuan, namun hingga sekarang ternyata ini tidak kunjung jadi prioritas negara.
“Stigma tehadap perempuan di masa lalu juga masih terjadi, Marsinah yang dibunuh, masih dianggap peristiwa kriminal biasa pembunuhannya, hingga kasus kadaluarsa. Walaupun Jokowi dalam pidatonya selalu berkomitmen pada penuntasan kasus HAM, namun kasus Marsinah tetap tidak tersentuh. Kasus perkosaan Mei 1998 juga selalu dianggap tidak valid dan dianggap kasusnya tidak ada. Jelas ini menjadi medan pertempuran isu perempuan.”
Naomi Srikandi, seorang aktivis dan pekerja seni menyatakan bahwa di Indonesia, sejumlah pekerja seni pernah membuat gerakan bersama stop kekerasan seksual, ini juga karena banyak kekerasan seksual yang tersembunyi di kalangan pekerja seni
“Ada kasus pelaku kekerasan seksual Sitok Srengenge misalnya, ini sangat melelahkan untuk diadvokasi. Kita harus membuat ruang aman sebanyak banyaknya, kerja kolektif yang lintas batas, karena jika tidak dari kita yang melakukan dan berusaha menyelesaikannya, banyak pelanggaran HAM yang tak akan selesai juga.”
Bhena Geerusthia, peneliti Remotivi menyatakan bahwa di mediapun kondisinya tak jauh beda, banyak bias gender terjadi di media, dalam pemberitaan kekerasan berbasis gender sangat lemah etikanya.
“Logika bisnisnya payah dan kekerasan seksual hanya sekedar komoditas, logika ini juga sensasional, melangengkan mitos kekerasan seksual dalam diksi atau kata-katanya. Tubuh perempuan diobyektifikasi atau male gaze. Tubuh perempuan dilihat sebagai masalah moral, justru dicari kesalahannya,” kata Bhena
Sadika Hamid, manager komunikasi Amnesty Internasional Indonesia mengkritik konvensi atau aturan HAM internasional yang tidak diterapkan di Indonesia, ini menjadi catatan penting dalam penegakan HAM dari perspektif aturan internasional dimana Indonesia sebenarnya ada di dalamnya dan menyetujui atau meratifikasi aturan-aturan ini
Kania Mamonto, dari Asia Justice and Right atau AJAR menyatakan bahwa situasi ketidakpastian penyelesaian kasus HAM ini kemudian membuat AJAR membangun pendekatan ke komunitas untuk menguatkan para korban
“Walau kenyatannya, rasa sakit yang dirasakan para korban HAM ini tidak ada di data-data ini ya. Maka kita mendekatkan pada komunitas, komunitas Aceh, komunitas korban pelanggaran HAM 65. Korban pelanggaran HAM berat ini tidak pernah berhenti berharap karena setiap Pemilu selalu pemerintah dan berpidato memberikan harapan, tapi ternyata tidak pernah jadi. Posisi politik pemerintah selalu menjadi harapan, namun tidak pernah terwujud. Akhirnya mereka berorganisasi sendiri. Komunitas inilah yang kemudian memberikan penguatan sistem dan impunitas bagi para korban, komunitas inilah yang penting memberikan penguatan karena merupakan corak utama perjuangan, mereka bisa saling support dan solidaritas datangnya dari sini.”
Diskusi ini dengan sendirinya menyimpulkan bahwa negara memang tak bisa diharapkan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM, masyarakat harus bergerak sendiri untuk mengubah keadaan
(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)