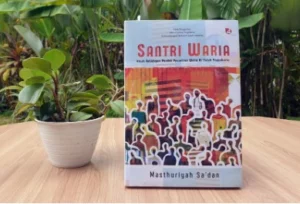Film berjudul ‘Selesai’ yang dirilis 13 Agustus 2021 ramai diperbincangkan minggu lalu. Bermacam-macam ulasan, termasuk kritikan pedas warganet, mondar-mandir di berbagai timeline sosial media. Tagar #Selesai #Tompi #Arieltatum juga berturut-turut sempat nangkring jadi topik terpopuler di Twitter.
Bermula dari paparan ‘perghibahan di dunia maya’ saya pun mulai menonton film ‘Selesai’ yang durasinya sekitar dua jam.
Menit demi menit adegan saya coba pelototi dengan seksama, akhirnya saya sepaham: film ini boleh saja dianggap berhasil memotret realita, tapi gagal atas pembelaan beragam persoalan diskriminasi yang ada. Termasuk, dengan sendirinya melanggengkan diskriminasi terhadap perempuan.
Kenapa saya bilang begitu? Mari kita mulai lihat isi film besutan Tompi dan Imam Darto yang diproduksi Beyoutiful Pictures ini. Dalam sebuah diskusi online yang diadakan Cinemalinea , Tompi dan Darto memaparkan isu yang akan diangkat dalam film ini. Diskusi ini ditayangkan secara online pada 19 Agustus 2021
Podcast berdurasi 2 jam 55 menit itu membedah proses kreatif pembuatan film yang kemudian akan kita kaitkan dengan hasil film, yang tak sedikit bikin publik gundah-gulana.
Jalan cerita film ‘Selesai’ sebenarnya tak terlalu rumit. Tompi-Darto mengklaim ide ceritanya begitu dekat dengan realita yang terjadi di sekitar mereka: perselingkuhan dalam rumah tangga, yang kali ini terjadi di situasi pandemi.
Dalam film diceritakan sosok Ayu (Ariel Tatum) dan Broto (Gading Marten) yang bertengkar akan cerai kala hubungan gelap Broto dan Anya (Anya Geraldine) mencuat. Namun, sang ibu Mertua Ayu kemudian tampil untuk berusaha menahan keduanya dari perceraian.
Sebagai cameo, film itu juga menampilkan kehidupan sepasang kekasih pekerja rumah tangga (PRT)-supir, Yani-Bambang, yang diperankan Tika Panggabean dan Imam Darto. Keduanya menjalin kasih yang tak kalah problematik: Bambang yang seorang laki-laki beristri memanipulasi Yani agar mau melayani secara seksual hingga sampai urusan ekonomi.
Sederhana tampaknya, namun jika ditilik satu persatu, kritikan publik atas film ini memang layak dilayangkan. Sebab, film ini terbilang problematik, utamanya terkait perspektif perempuan hingga mental health issue.
Memotret Realita Tanpa Adil Gender
Berkali-kali dalam diskusi di balik layar film, Tompi-Darto bilang bahwa film ini hanya bermaksud memotret realita. Tanpa menghakimi apapun. Sehingga, dalam film ini realita-realita yang ada di tengah masyarakat berusaha dimunculkan begitu saja.
Tompi mengaku ide cerita hingga penulisan skrip film ‘Selesai’ memang tidak melibatkan perempuan alias hanya mereka berdua. Kisahnya juga terinspirasi dari pengetahuan dan realitas pengalaman mereka, namun sayangnya film ini hanya dibuat dari sudut pandang laki-laki (male gaze).
“Benar-benar kita berdua. Dan memang gak harus juga (ada perempuan),” ujar Tompi dalam diskusi Cinemalinea audio-virtual (19/8/2021).
“Gak membutuhkan (sudut pandang perempuan), gak necessary harus, (cukup) observing,” imbuh Darto.
Imbasnya, alih-alih melawan berbagai diskriminasi gender utamanya bagi perempuan, film ini justru menampilkan berbagai realitas dengan sembrono dan mentah. Berbagai realitas yang hendak dipotret misalnya, maskulinitas rapuh berupa ego laki-laki (diperankan Broto) yang ingin menjadi sosok dominan dalam relasi.
Kaitannya ini, seorang laki-laki bakal memaksakan diri untuk memenuhi stereotip-stereotip maskulin dan tidak ingin terlihat feminin terlebih di depan publik. Maka, untuk memuaskan ego maskulinnya, dia bisa mencari pelampiasan agar bisa kembali menjadi ‘merasa dominan’.
“Si Broto (berselingkuh karena) tak menjadi pimpinan keluarga. Makanya dia keluar mencari yang bego (karakter Anya– yang menyebut virus corona seperti zombie). Gue laki-laki, gue dibutuhin. Perempuan ini benar-benar membutuhkan gue,” ujar Darto.
Di sisi lain, laki-laki dalam film ini, juga seolah dimaklumi saat bertindak abusive dan toksik. Ini tampak pada porsi berkata-kata kasar dan kekerasan, cenderung ditampilkan dominasi pada sosok Broto. Dia juga menampilkan perilaku gaslighting yaitu tindakan yang terlihat berkuasa dan dapat mengontrol orang lain dengan cara membuat korbannya tidak yakin akan dirinya sendiri.
Ini ditujukan misalnya saja pada adegan ketika Ayu yang mendapati suaminya berselingkuh dan melakukan konfrontasi, justru Broto membalikkan dengan perilaku yang kasar.
“Mau cerai? Mau harta, kan?,” kata Broto.
Realitas lainnya yang coba dihadirkan dalam film itu adalah “naluri lelaki” yang menormalisasi objektifikasi perempuan, kala Bambang menjadikan sosok Ayu sebagai bacol (bahan coli). Dalam perannya, dia juga melakukan manipulasi untuk mengajak kekasihnya, Yani, sebagai objek seksual.
“Secara harafiah biologisnya oranglah. Kalau ngeliat cewek seksi kira-kira laki-laki yang mungkin nggak punya pelampiasan, tergoda gak buat berbuat yang gak-gak? Iya kan? Faktanya kan,” kata Tompi.
Selain jalan cerita yang menggantung dan seolah membiarkan berbagai diskriminasi begitu saja, film ini juga menyinggung soal isu kesehatan mental. Ayu yang digambarkan mengalami depresi dan delusi, serta-merta ditampilkan sebagai sosok yang prihatin dan dibawa ke rumah sakit jiwa.
Deretan problem perselingkuhan Broto dan Ayu, diakhiri dengan laki-laki yang tetap bisa melenggang kekerasan tanpa adanya konsekuensi. Sementara, perempuannya dibiarkan begitu saja menjadi korban.
Bagian yang cukup disayangkan terkait ini, juga soal depresi yang seolah-olah langsung distigmakan gila. Ini ironi di kala isu kesehatan mental digaungkan untuk tidak tabu dibicarakan dan bisa mendapatkan pertolongan profesional seperti psikolog atau psikiater.
(Foto: Kompas.com)