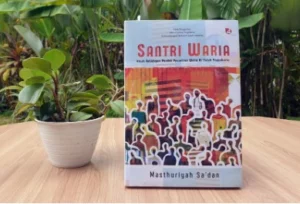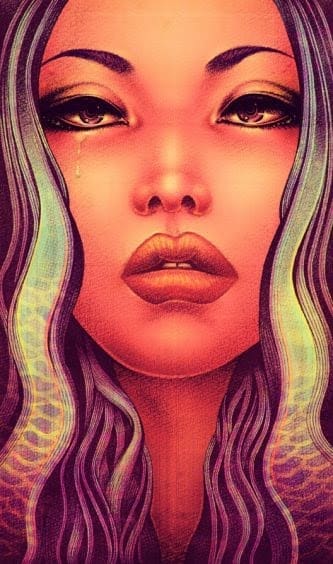“Kapan nikah?.”
Pertanyaan basa-basi itu selalu menjadi momok bagi perempuan. Berbeda dengan laki-laki, perempuan lajang memiliki beban sosial yang lebih besar. Bagaimana tidak? Jika tak kunjung mendapat pasangan, perempuan akan dilabeli sebagai barang tak laku, perawan tua, dan sederet julukan negatif lainnya.
Menyematkan status sebagai barang tak laku ini menyakitkan banget, karena perempuan diidentifikasi sebagai barang. Bahkan, status lajang perempuan kerap dikaitkan dengan kepribadian yang tertutup dan pemilih.
Emma Septiana dalam penelitian Fenomenologi Perempuan Lajang di Surabaya menulis, status lajang pada perempuan rentan mendatangkan stigma. Hal ini lantaran menikah seolah sudah dijadikan sebagai standar ideal masyarakat.
Depresi atas Label Negatif
Meski lumrah dilontarkan, pertanyaan “kapan nikah?” memberikan dampak negatif bagi psikologi perempuan. Dikutip dari laman Barisan.co, desakan orang sekitar untuk menikah dapat mengganggu mental dan memicu depresi, khususnya orang pada siklus the thirties antara 30 sampai 40 tahun. Situasi tersebut seolah menciptakan stereotip di masyarakat bahwa perempuan yang sudah mapan secara usia harus segera menikah. Desakan menikah pada perempuan disebabkan faktor kultural dan tuntutan sosial. Tidak bisa memungkiri, pernikahan seolah menjadi hal yang dinormalisasi masyarakat.
Menurut Septina (2013), masyarakat Indonesia memiliki struktur kolektivitas yang lebih kental. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia—khususnya perempuan—memiliki tekanan lebih kuat untuk memelihara budayanya, termasuk menikah. Pernikahan sudah dianggap sebagai ritus budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Sebagai konsekuensinya, perempuan yang masih lajang akan mendapat tekanan untuk menikah, baik oleh keluarga, teman, maupun lingkungan.
Dengan begitu, perempuan yang tidak menikah akan dianggap ‘tidak normal’. Perempuan lajang cenderung dikategorikan sebagai inferior karena tidak sesuai dengan norma kewajaran. Hal itu pula yang menyebabkan perempuan lajang mendapat stigma. Berdasarkan penelitian dari Greitemeyer pada 2009, masyarakat menilai perempuan lajang memiliki sikap yang tidak pandai bergaul, kurang dewasa, dan tidak bisa mengemban tanggung jawab.
Kesenjangan dalam Pernikahan
Penulis feminis Mesir, Nawal El-Saadawi menuturkan bahwa perempuan lajang dengan pendidikan dan karier tinggipun akan tetap didesak untuk menikah. Hal itu karena kuatnya budaya patriarki yang mengakar di masyarakat. Desakan itu ditujukan agar perempuan kembali ke ranah domestiknya.
Perempuan selalu didorong untuk menjadi ibu dan istri dalam sebuah keluarga agar ia tetap dihargai sebagai anggota masyarakat sepenuhnya. Karena budaya tersebut, setiap keluarga akan tetap menyarankan anak perempuannya untuk menikah.
Berbanding terbalik dengan perempuan, laki-laki lajang lebih memiliki keleluasaan. Masyarakat seolah tidak mempermasalahkan ketika laki-laki tak kunjung menikah. Dalam budaya patriarki, kaum laki-laki dianggap memiliki hak untuk memilih. Tak seperti perempuan yang harus menunggu untuk dipinang. Untuk itu, laki-laki yang melajang akan dianggap sebagai sebuah prinsip, sedangkan perempuan akan dianggap sebagai barang tak laku.
Dalam perkawinan pun, perempuan mendapat ketimpangan pada payung hukumnya. Sebagai contoh, UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana suami diperbolehkan memiliki istri lebih dari satu apabila istri tidak menjalankan kewajiban, cacat badan, dan penyakit yang tak bisa disembuhkan. Sedangkan di sisi lain, tak ada UU yang mengatur apabila kondisi tersebut dialami oleh suami. Mungkin sebagian orang menganggap hal ini biasa saja.
Dengan payung hukum yang patriarkis, tak menutup kemungkinan akan melahirkan pernikahan yang patriarkis pula. Hal yang demikian berpotensi melanggengkan dominasi laki-laki dalam lingkungan sosial.
Tidak Menikah, Tidak Masalah
Pada dasarnya, menikah merupakan hak setiap individu. Ketika seseorang memilih untuk melajang, itu juga merupakan hak individu.
Nadya Pramesrani, seorang psikolog mengatakan bahwa perempuan lajang di usia yang sudah matang tidak perlu khawatir dengan statusnya. “Menikah seharusnya bukan sebatas waktu atau tuntutan lingkungan,” ucanya yang dikutip dari Kompas.com. Dalam memahami pernikahan, kesadaran sosial perlu dibangun ketimbang sekadar mandat budaya. Alih-alih mempersoalkan pada angka pernikahan, masyarakat mesti lebih fokus pada terciptanya lingkungan yang optimal untuk berkembang.
Dengan demikian, bukan berarti bahwa pernikahan adalah hal yang salah dan sia-sia. Namun, menetapkan pernikahan sebagai suatu kewajiban juga bukan sikap yang tepat. Pernikahan menjadi ranah privasi setiap individu. Lagi-lagi, pernikahan bukanlah harga mati kehidupan. Saat perempuan memutuskan tidak menikah, bukan berarti hidupnya tak akan bahagia. Toh, ketika sudah menikah sekalipun, tak lantas membuat perempuan terlepas dari beban “kewajiban” lainnya, seperti mengurus rumah dan memiliki momongan. Menikah adalah hal yang baik, tapi tidak menikah juga bukan sebuah masalah.