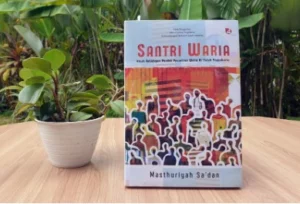“Kalau wartawan perempuannya genit-genit, ya narasumbernya, pasti akan tergoda kan!.”
Kalimat seksis ini terlontar dari salah satu narasumber kami, seorang jurnalis senior di stasiun televisi swasta ketika mengetahui data tentang sejumlah jurnalis perempuan yang dilecehkan oleh narasumbernya
Argumen senada ternyata masih banyak ditemui dalam lingkungan pekerja media. Kondisi ini membuktikan bahwa tak semua jurnalis memahami betul tentang apa itu pelecehan dan kekerasan seksual. Sistem kerja yang keras menjadikan ruang-ruang redaksi jadi kental dengan persepsi yang maskulin dan tak ramah bagi jurnalis perempuan.
Dalam ruang redaksi yang patriarki, pekerja perempuan kerap mendapatkan stigma buruk seperti dianggap lemah, tidak kompeten, emosional, padahal inilah yang menghambat perempuan jurnalis perempuan selama ini.
Mengutip Jaring.id, dalam riset Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN), 57,4 % responden yang terdiri dari jurnalis perempuan memandang bahwa budaya patriarki merupakan hambatan utama mereka.
Hal ini membuat jurnalis perempuan tidak dapat bergerak bebas. Pandangan mengenai fisik yang lemah, kerap menjadikan mereka jarang diberikan tempat dalam peliputan-peliputan khusus, seperti dalam peliputan-peliputan di arena yang berisiko, di wilayah konflik ataupun bencana.
Stigma terhadap jurnalis perempuan yang meliput di wilayah konflik juga pernah dialami oleh Desi Fitriani, jurnalis senior Metro TV. Ditemui secara daring melalui Zoom pada Senin (29/11/2021), eksekutif produser Metro TV ini membeberkan diskriminasi yang sempat ia terima ketika dalam penugasan pertamanya di wilayah konflik.
Kepada kami, Desi bercerita pernah mendapatkan perlakuan yang merendahkan, ketika meliput bersama dengan pasukan batalyon saat konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Di awal keberangkatan, beberapa personil pasukan melontarkan pertanyaan ‘Kamu yakin perempuan bisa? Kita jalan jauh lho, susah lho’. Disitu, Desi merasa dilecehkan, dianggap tidak mampu.
Hal serupa juga pernah dilihat oleh Daspriani Yayan Zamzami, jurnalis perempuan anggota Majelis Etik AJI Banda Aceh. Ia menuturkan bahwa selama peliputan konflik GAM, beberapa televisi nasional mengobjektifikasi jurnalis perempuan dengan menerjunkannya sebagai reporter lapangan sebagai pengumpan atau menarik perhatian.
“Jadi, mereka (stasiun televisi nasional) tuh, menempatkan jurnalis perempuannya sebagai reporter di lapangan, (agar) bisa masuk ke lini pemerintahan, dalam hal ini polisi dan militer,” tambahnya.
Tantangan menjadi seorang jurnalis perempuan di wilayah konflik tidak berhenti pada stigma yang selama ini berlaku. Kerentanan yang sesungguhnya terjadi ketika melakukan peliputan di medan bersenjata. Ancaman dan teror yang kerap menghampiri, kekerasan fisik, seksual, hingga menjadi korban salah sasaran merupakan konsekuensi yang harus dihadapi.
Melansir unilubis.com, jurnalis perempuan dianggap lebih rentan ketika terjun melakukan peliputan konflik. Selain rentan mendapatkan stigma separatis oleh pihak yang bertikai seperti halnya jurnalis laki-laki, objektifikasi dan eksploitasi seksual, infrastruktur transportasi serta sanitasi yang masih belum tercukupi kerap menjadi permasalahan tersendiri bagi jurnalis perempuan.
Akses yang Sulit dalam Peliputan
Padahal tak jarang, akses peliputan juga sulit sering dialami perempuan jurnalis. Sejalan dengan hal tersebut, Tika Adriana, pengurus divisi gender Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mengungkap, bahwa akses air bersih untuk jurnalis perempuan yang sedang menstruasi ketika meliput konflik misalnya, masih jauh dari layak.
Ini juga dibenarkan oleh Desi, menurut perempuan yang sudah meliput di 33 negara ini, untuk meliput di wilayah konflik salah satu perlengkapan yang harus dibawa yaitu tisu basah.
“Ya tinggal dibuang (pembalut), kita gali lubang, kita tanem di situ (pembalut),” tutur Desi ketika kami tanya mengenai pembuangan dan pembersihan diri ketika menstruasi.
Ironisnya, tantangan yang mereka alami selama masa bekerja, tidak begitu saja selesai pasca-peliputan. Ada luka-luka lain yang harus mereka bawa pulang bersama ke rumah, yang tidak dapat disembuhkan dalam waktu singkat.
Danika Nurkalista, selaku Koordinator Kasus di Yayasan Pulih, menyebut hal ini sebagai secondary trauma. Ia menjelaskan dampak psikologis pasca peliputan di daerah berkonflik kerap menimbulkan stres berkelanjutan. “Itu adalah jenis kasus yang membutuhkan pendampingan dan pengawasan lebih lanjut.” tambahnya.
Perempuan yang telah bekerja sama dengan para jurnalis dalam penanganan trauma pasca-peliputan sejak 2002 ini juga mempertegas mengenai akses layanan bantuan. Menurutnya, layanan bantuan dana hingga kesepakatan pendampingan dengan klinik maupun biro psikologis, haruslah menjadi tanggung jawab langsung dari para perusahaan media dan serikat pekerja.
“Advokasi mengenai batas waktu pekerja kemanusiaan, apabila seorang jurnalis ditugaskan di daerah berkonflik, hendaknya menerima grasi dua sampai tiga minggu waktu istirahat, dan digantikan dengan pekerja lain,” imbuh Danika.
Senada dengan yang diucapkan Danika, Tika menyebut bahwa di beberapa negara dengan sistem media yang sudah baik, jurnalis akan diberikan waktu dua pekan peliputan di wilayah konflik. “Dan mereka (jurnalis dari negara dengan sistem media yang baik), dikasih trauma healing,” tambah Tika.
Tika Adriana, bercerita kepada kami pada 23/11/2021 mengenai kondisi jurnalis perempuan di ruang redaksi. Ia menuturkan rata-rata, setidaknya hanya ada 3 perempuan dalam 10 jabatan manajerial di dapur redaksi. Menurut jurnalis Konde.co ini, meski menduduki jabatan manajerial, jurnalis perempuan tetap tidak diberikan kekuatan untuk mengemukakan ide-ide atau mengatur jabatan tertentu, karena dianggap tidak mempunyai pengalaman.
Tika juga menunjukkan bahwa jumlah jurnalis perempuan di Indonesia saat ini kurang dari 30% dari total jurnalis keseluruhan. Angka ini diperoleh dari survei yang dilakukan oleh AJI pada keseluruhan anggotanya. Melansir dari Konde.co, penelitian terbaru yang dilakukan oleh Nurul Hasfi, bersama rekannya sesama dosen, Sunarto, Luz Rimban, dan Amida Y pada tahun 2020, menyebut bahwa keseluruhan jurnalis perempuan di Indonesia tidak lebih dari 25%, dengan 20% di antaranya tergabung dalam AJI.
Ini menunjukkan bahwa jurnalis masih menjadi profesi yang dipenuhi dengan laki-laki. Lebih lanjut, temuan tersebut juga memperkuat adanya anggapan di media bahwa perempuan masih tidak mampu melakukan peliputan. Padahal, menurut penuturan Tika, perempuan hanya tidak diberikan kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuannya.
Berbicara mengenai peliputan, jurnalis perempuan yang mendapatkan kesempatan untuk meliput di wilayah berisiko ternyata jauh lebih sedikit jumlahnya. Hal ini tidak lepas dari berbagai macam stereotip mengenai perempuan yang masih kuat mengakar. Selain karena bahaya yang cukup besar, persepsi mengenai perempuan yang akan merepotkan, ketika diikutsertakan dalam peliputan konflik merupakan salah satu bentuk diskriminasi gender yang sering ditemukan.
“Masalahnya itu kan bukan nggak mampu, tapi mereka tidak diberikan kesempatan (meliput).” Ungkap Tika.
UU Pers dan Upaya Perlindungan Jurnalis dari Instansi Terkait
Kerentanan yang dihadapi oleh jurnalis, utamanya perempuan, menjadikan payung perlindungan terhadap keselamatan jurnalis harus segera diresmikan. Hal ini sejalan dengan narasi dalam Standar Perlindungan Profesi Wartawan yang berbunyi ‘dalam menjalankan tugas profesinya wartawan mutlak mendapat perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers.’
Berangkat dari kebutuhan inilah, pada 28 April 2008 lalu, Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA mengesahkan Peraturan Dewan Pers Nomor: 5/Peraturan-DP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan. Menyangkut topik jurnalis di wilayah berkonflik, peraturan keselamatan juga ditambahkan sebagai tujuan pembuatan payung hukum tersebut. Keselamatan dan keamanan jurnalis di wilayah berkonflik menjadi bagian penting atas peraturan perihal kepentingan pers.
Regulasi yang telah disahkan wajarnya dapat dijadikan acuan dalam aktivitas jurnalistik baik dari dewan pers maupun perusahaan media. Sayangnya, hal ini bertolak belakang dengan penjabaran Tika. Perempuan yang aktif menulis tentang kesetaraan gender ini menuturkan bahwa perusahaan media cenderung lalai terhadap penerapan Standard Operating Procedure (SOP) jurnalis di daerah berkonflik. “Jangankan SOP, jurnalis baru masuk ke perusahaan aja, kadang gak dikasih training dulu.” Tutur Tika mengomentari regulasi keselamatan kerja jurnalis yang memprihatinkan.
Tidak terbatas pada topik itu saja, Tika mengaku, perihal jam kerja dan kesehatan mental jurnalis, media-media di Indonesia masih tertinggal jauh dari media luar negeri. Menurut penggambarannya, media Indonesia kerap berlindung di bawah ayat ‘kesehatan mental adalah bagian dari risiko kerja’ yang harus ditanggung oleh jurnalis itu sendiri.
Kecenderungan perusahaan media Indonesia yang abai terhadap keselamatan jurnalis seperti yang diungkapkan Tika, merepresentasikan apa yang dialami oleh Desi. Perihal pengalamannya ketika meliput berita konflik demonstrasi 212 di dalam negeri, yang meninggalkan cerita pahit ketika mendapatkan kekerasan verbal dari pihak yang berkonflik. Desi yang diketahui bekerja sebagai reporter stasiun televisi yang diasosiasikan sebagai kubu oposisi dari massa demo, harus menerima teriakan-teriakan yang menghakimi identitasnya.
“Gue kena pukul. Makanya gue bilang, di dalam negeri malah kayak gitu (mendapat kekerasan). Di luar negeri, Alhamdulillah selamat,” pungkas Desi.
Penulis: Kamila El Sabilla, Maya Amelia, Aulia Maulani, Solehatun Marfuah, Sela Septi Dwi Arista, Mellia Arya Firanur Sukma, Dewi Avivah, Litalia Putri Cahyani, Manda Eka Azaria
(Artikel ini merupakan kerjasama Konde.co, The Asian Muslim Action Network (AMAN) dan Girl Ambassadors for Peace yang didukung UN Women dalam program Girl’s Camp 2021)