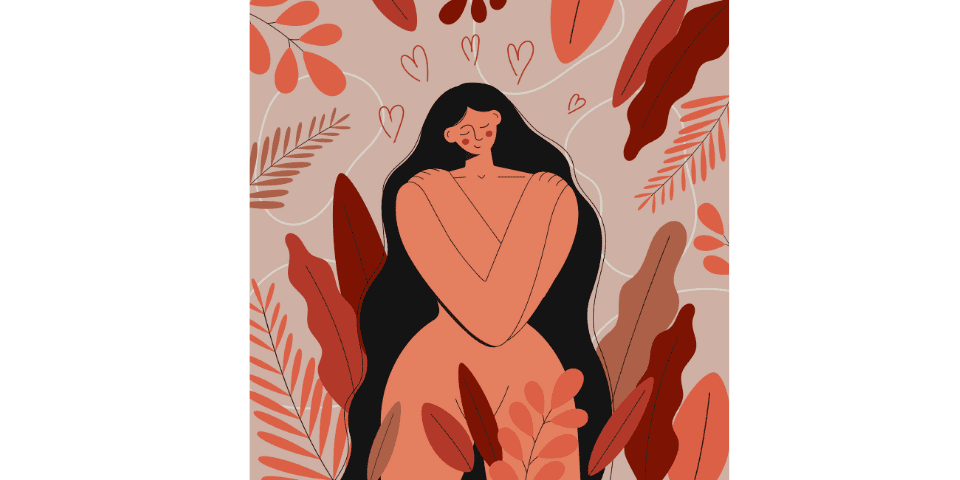Ingatanku dengan cepat terlempar pada sebuah esai abadi “Can the Subualtern Speak?” Gayatri Spivak menuliskannya berpuluh tahun lalu, aku mempelajarinya.
Namun dentumannya begitu nyata setelah mendengar berita kematian NWR, perempuan setelah diperkosa pacarnya yang seorang polisi dan memutuskan bunuh diri, malam itu.
Betapa pilu dan sesak hatiku setelah mendengar berita kematianmu. Penyesalan begitu menusuk, karena begitulah dunia misogini hanya menyediakan kematian sebagai satu-satunya bahasa bagi seorang perempuan sekaligus korban kejahatan seksual.
NWR buat saya tak ada tandingannya. Hanya dengan membaca surat dan tulisannya, kita akan tahu bahwa ia memiliki banyak mimpi. Ia cerdas, karena turut mengimaji suatu tata kehidupan yang adil dan setara. Tidak seorang pun bisa mengira, bahwa semua cita-cita itu harus ia tutup di penghujung tahun 2021 dengan lonceng nyaring kematiannya.
Sore hari, 2 Desember 2021. Tubuh NWR ditemukan tergeletak di samping makam ayahnya. Ia bunuh diri. Kematian ia pilih, sebab laki-laki yang menjadi kekasihnya tidak bertanggung jawab. Ia diperkosa, dipaksa menelan pil aborsi, ditipu serta dikhianati. Sebagaimana masyarakat patriarki umumnya, Novia menjadi seorang korban dengan berbagai stigma.
Ia depresi, pengakuannya ia tuliskan dalam catatan rapi, berbagai pertanyaan untuk mendapat solusi telah ia lempar. Namun, lagi-lagi, kelambanan dan keacuhan dari orang-orang di sekitarlah yang menjawab.
Tentu tulisan ini tidak akan mengulang persis kronologi yang beredar di sosial media. Uraian ini adalah sebuah opini mengenai kematian dari perempuan sebagai korban kejahatan seksual. Cerita NWR menjadi bukti, bahwa perempuan sebagai subaltern dalam masyarakat patriarki tidak memiliki pilihan.
Ia menjadi objek, didefinisikan, dan tidak memiliki bahasa. Sehingga, cerita ini tampak persis pada perempuan Sati di India yang diamati oleh Gayatri Chakravorty Spivak.
Jika Sati atau tradisi pembakaran pada janda (perempuan) adalah satu-satunya cara berbicara dan berbahasa perempuan di India, maka pilihan bunuh diri Novia memiliki artikulasi serupa.
Perempuan dalam tradisi Sati memilih kematian (dengan cara membakar tubuhnya) setelah kematian suaminya. Menjadi janda bermakna kehilangan eksistensinya; jika memilih bertahan ia akan distigma buruk. Tidak ada tafsir dan pilihan hidup lain. Maka kematian dipilih menjadi satu-satunya cara artikulasi subjek perempuan. Kebisuan itulah yang akhirnya berbicara.
“Something Cannot Say”
Sudah niscaya, subaltern selalu terhubung dengan sesuatu yang tidak dapat terungkapkan “something cannot say”. Begitulah duduk perkara awal yang ditulis oleh Gayatri.
Dalam esai yang dipublikasi pada tahun 1985 itu, Gayatri memang tidak spesifik menyebutkan bahwa “sesuatu yang tidak dapat terungkapkan” adalah situasi perempuan sebagai korban kekerasan seksual. Namun terdapat situasi yang ditangkap oleh Gayatri memiliki kesepadaan. Kesepadanan itu adalah posisi perempuan di tengah konstruksi ideologi malesentrisme.
Ia menuliskan: If, in the context of colonial production, the subaltern has no history and cannot speak, the subaltern as female is even more deeply in shadow.
Perempuan subaltern mendapati diri yang berlapis-lapis. Dalam konstruksi ideologi malesentrisme, perempuan tidak memiliki sejarah, bahasa, bahkan artikulasinya diciptakan. Situasi tak terkatakan ini atau situasi tak terketahui (unacknowledged) bagi Gayatri adalah suatu langkah penting.
Gayatri menyepakati ide Pierre Macherey bahwa suatu formula ideologi paling ampuh adalah ‘apa yang tidak dikatakan’. Salah satu contoh bagaimana prinsip itu bekerja adalah apa yang dilakukan perempuan (janda) Hindu pada saat itu.
Saat suami perempuan Hindu meninggal, ia menaiki onggokan kayu api untuk mengorbankan dirinya. Perempuan menginginkan kematian karena tak bisa melarikan diri dari status buruk janda.
Sama seperti Sati, kekerasan seksual pada mulanya berupa pengalaman tak terartikulasi. Pengalaman perempuan diceritakan begitu acak sebelum tahun 1970. Dalam buku Thinking about Sexual Harassment, Margaret A. Crouch menyebut bahwa terma “sexual harassment” atau apa yang kita pahami saat ini sebagai pelecehan seksual baru dipergunakan sejak dekade 1970-an.
Sebelum terdefinisi, kekerasan seksual hanya ada dalam pengalaman bisu, protes pekerja perempuan, cerita pilu di surat kabar, tanpa dipahami bahwa situasi yang merendahkan kehormatannya sebagai manusia adalah suatu tindak kejahatan.
Bahkan setelah terma itu bekerja dengan baik saat ini, kita masih sering mendengar kabar menyedihkan dari para korban dan penyintas kekerasan seksual. Betapa kekerasan seksual masih sulit terartikulasikan, betapa lembaga aduan dan pemerintah masih lamban.
Cerita NWR adalah Lonceng Kematian Abadi
Hanya ada sesal dan sesak, karena pengalaman dan aduan NWR baru kita dengar setelah pesan kematiannya datang.
Terlebih, saat dunia tengah ramai dengan berbagai kampanye: #16HAKTP, #GerakBersama, #SahkanRUUPKS, dan lain sebagainya. Tepat, di saat dunia memperingati 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, NWR, perempuan itu memilih kematian. Ia menjadi korban bertubi-tubi oleh kekasihnya, keluarga kekasihnya, bahkan keluarganya sendiri.
Mungkin setiap korban kekerasan seksual akan bertanya, bagaimana cara menceritakan ini (pengalaman) kepada dunia? Bagaimana cara mengobati martabat diri? Namun dunia masih tidak mau disibukkan dengan urusan yang mereka anggap remeh ini. Masyarakat dan keluarga bukan malah mengobati, namun menstigma sehingga bertambah berat beban yang harus dipikul korban. Itulah dunia yang kita hadapi saat ini.
Cerita NWR adalah lonceng abadi. Kematian seharusnya menjadi pesan tamparan untuk semua orang. Kematiannya adalah kepedihan yang tidak lagi dapat dibahasakan-dikatakan. Lonceng ini menjadi pukulan keras untuk patriarkisme yang masih bercokol dalam pengaturan hukum dan pemerintah di Indonesia.
Engkau telah damai dipeluk ibu Bumi, NWR.