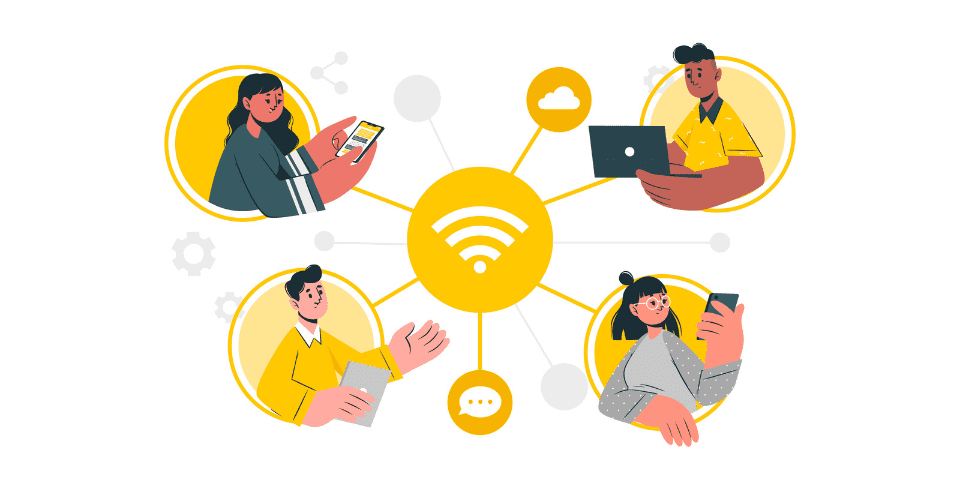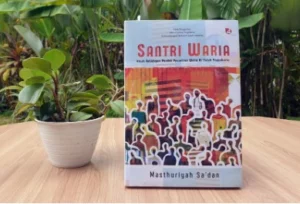Dalam feminisme, internet disebut-sebut sebagai kajian terkini, ia memberikan peluang ekspresi, namun juga membelenggu. Perjuangan dalam teknologi ini kemudian masuk dalam gelombang keempat feminisme.
Gelombang keempat feminisme ini mulai muncul sekitar tahun 2010. Asmi Ayuni dalam artikelnya di dfunstation.com menulis, dibandingkan zaman dulu, feminisme zaman dulu menghadapi berbagai kendala seperti struktur sosial politik yang kaku dan kurangnya saluran komunikasi.
Sementara feminisme di zaman sekarang sangat didukung oleh pemanfaatan media digital sebagai platform yang menjangkau jauh setiap orangnya untuk saling terhubung, berbagi perspektif, menciptakan pandangan yang lebih luas tentang pengalaman penindasan, serta kritik gelombang feminis di masa lalu.
Berdasarkan identifikasi laman Bustle mengenai apa saja yang diperjuangkan di gelombang feminisme zaman sekarang, muncul beberapa hal yang diperjuangkan di antaranya; queer, sex positive, penerimaan transgender, anti-misandry (anti membenci laki-laki), body positivity atau penerimaan bentuk tubuh apapun secara positif; dan penggunaan teknologi digital seperti internet yang mendukung pergerakan feminisme. Namun zaman sekarang, juga banyak sekali tantangannya, salah satunya tantangan kebijakan teknologi
Internet, selain berfungsi memberikan ruang untuk bersuara dan ekspresi, perempuan di internet juga menjadi objek beragam dalam bentuk kejahatan seperti cybercrime, seperti kekerasan secara verbal dan visual dalam wujud pornografi (cyberporn), pelecehan seksual, penculikan, perilaku narsistik, juga jadi sasaran budaya konsumtif.
Sebagai orang yang selalu bersuara, perempuan pembela Hak Asasi Manusia (HAM) mengalami kerentanan di dunia digital. Sejumlah aturan yang janji-janji awalnya memberikan payung hukum, justru tak sedikit yang membelenggu kebebasan berpendapat. Implementasinya pun, masih acapkali ‘tebang pilih’.
Aturan ranah digital yang jadi sorotan karena ada pasal karetnya ialah Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, Permenkominfo 5/2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat yang mengatur hampir seluruh aspek PSE mulai dari pendaftaran, moderasi konten, pemutusan akses, akses data untuk kepentingan pengawasan dan penegakan hukum, hingga sanksi terhadap PSE.
Peraturan menteri yang efektif berlaku 24 Mei 2021 itu, menyebutkan seluruh PSE di Indonesia harus sudah mendaftar dan mendapatkan tanda pengenal dari Kominfo. Bila tidak mendaftar sesuai dengan kebijakan dan jangka waktu yang telah ditetapkan, menurut Pasal 7, PSE tersebut berpotensi menerima sanksi administratif berupa teguran hingga pemutusan akses (blokir ataupun take down).
Hasil kajian hukum Perkumpulan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFENET) misalnya, menyebut pada aturan yang terdiri dari 49 pasal di Permendikbud 5/2020 ini, ada setidaknya tujuh pasal bermasalah, baik dari sisi perspektif hukum, juga HAM.
Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Era Purnamasari mengatakan seperti halnya pasal karet UU ITE yang bisa mengancam aktivis pembela HAM dengan penangkapan dan diskriminasi akses data pribadi, Perkominfo 5/2020 ini juga sama punya potensi bahayanya. Bukan saja identitas data pribadi, bahkan orientasi seksual pun bisa diakses oleh lembaga penegak hukum.
“Itu mengancam kebebasan pribadi seseorang,” ujar Era dalam diskusi daring Feminist Festival bertajuk Internet Safety for Women Human Rights Defender pada (28/11/21).
Tak hanya keleluasaan akses data pribadi, menurut Era, Permenkominfo itu juga bisa jadi ancaman kala dimanfaatkan begitu saja dalam melakukan pemblokiran atas informasi-informasi yang dianggap ‘meresahkan’. Padahal, tidak ada mekanisme verifikasi dan pengujian informasi yang “meresahkan”.
“Kalau di negara demokrasi, harus ada check and balances; Yudikatif, Eksekutif. Pemerintah pun punya kepentingan.. ketika ada tafsir itu multitafsir, mestinya lembaga itu menyediakan akses untuk keadilan. Logika yang dibangun Kominfo ini tidak mengarah ke situ. Kecenderungan sekarang, semacam pengadilan atau Yudikatif itu tunduk pada eksekutif,” terang dia.
Era juga menyayangkan bahwa saat ini, ada kecenderungan pemberian kewenangan seluas-luasnya pada kepolisian untuk mengakses data pribadi ketika penangkapan aktivis pembela HAM seolah semakin mudah. Sejak adanya perubahan UU ITE tahun 2016, penggeledahan dan penyitaan tidak mesti ada izin dari Ketua Pengadilan.
“Akhirnya polisi menangkap dulu baru dicari bukti kemudian, akses perangkat elektronik dicari ke situ buktinya. Tak ada jaminan aktivis ketika diretas,” katanya.
Asfinawati dari YLBHI menambahkan, akuntabilitas hukum dalam aturan yang berpotensi mengancam kebebasan berekspresi di internet bagi aktivis pembela HAM itu, juga dipertanyakan. Dia mencontohkan, selama ini ada ‘tebang pilih’ dalam penanganan peretasan di dunia digital.
“Kalau dia influencer yang sering bela pemerintah kalau dia di doxing, cepat (penanganan). Tapi peretasan dan doxing dari (aktivis pembela HAM) yang kritis tak pernah diungkap,” ucap Asfin di kesempatan sama.
Dia juga menyoroti, bahwa masih banyak aktivis pembela HAM kritis yang mendapatkan ancaman secara digital dari warganet ataupun pendengung (influencer), yang ironisnya ada dugaan juga “dipelihara” oleh lembaga negara dan kepolisian.
“Di laporan ICW tertulis, di situ influencer, dan sebenarnya kita tidak tahu betul untuk apa influencer itu,” ujarnya.
Ancaman bagi Jurnalis
Jurnalis perempuan sebagai pembela HAM juga tak luput dari ancaman di dunia digital. Kerja-kerja jurnalis memang telah dilindungi dan diatur dalam UU Pers No 40/1999. Pada pasal 4 ayat 1 disebutkan, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Artinya, pers harus bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin.
Namun nyatanya, masih ada saja hambatan aturan yang justru berpotensi mengkriminalisasi jurnalis. Seperti, pasal 27 ayat 3 UU ITE tentang pencemaran nama baik dan pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian.
Data Aliansi Jurnalis Independen (AJI), bahkan mengungkap, adanya kasus pembungkaman pers mencapai 3 kasus jurnalis yang ditahan (dikriminalisasi) dalam setahun. Paling banyak memang jurnalis yang meliput isu sensitif seperti korupsi, dampak lingkungan hingga kekerasan seksual.
“Terjadi peningkatan intensitas yang cukup serius UU ITE pada 2018, dijadikan untuk membungkam dan menekan pers,” ujar Sekretaris Jenderal AJI Indonesia, Ika Ningtyas.
Di sisi lain, Ika menyebut, jurnalis ini juga masih banyak mengalami serangan digital dalam menjalankan tugasnya. Seperti doxing, peretasan, harassment, serangan Ddos, hingga KBGO.
“14 kasus dalam setahun,” lanjutnya.
Ironisnya lagi, kata dia, pelabelan hoaks oleh institusi negara juga masih banyak ditemukan. Di antaranya yang menimpa Reuters dan Jubi (2019), majalah Tempo (2020), Harian Kompas (2021) dan terbaru Project Multatuli (2021).
“Padahal kerja-kerja jurnalisme ini sudah melalui verifikasi yang panjang,” ujar Ika.
Untuk membekali para jurnalis agar terhindar dari serangan digital tersebut, Ika mengatakan AJI terus menyelenggarakan edukasi Holistic Safety termasuk bagi jurnalis perempuan. Meliputi, keamanan fisik, psikososial hingga digital.
Selain itu, dia juga mengajak untuk para aktivis pembela HAM bisa memperkuat advokasi litigasi, menggalang dukungan publik, kolaborasi stakeholders, hingga meningkatkan profesionalisme dan etik serta independensi newsroom.
Berkenaan dengan aturan di ranah digital, Era (YLBHI) pun berharap, selain adanya revisi UU ITE, juga perlu segera disahkannya UU Perlindungan Data Pribadi.