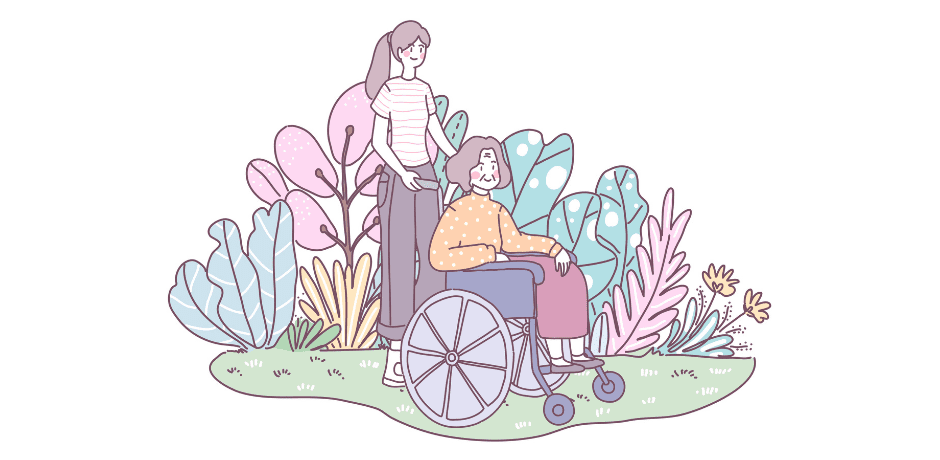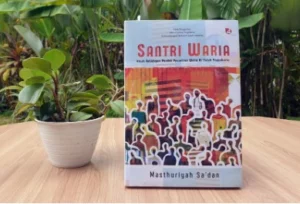Sebut saja Amel, ia adalah penderita tuna rungu berusia 19 tahun. Perempuan muda asal Binjai ini menyatakan tak pernah mendapatkan pendidikan hak kesehatan seksual dan reproduksi (HKSR).
Hambatan yang muncul dari pendidikan HKSR bagi penyandang tuna rungu seperti Amel, salah satunya karena lingkungan terdekatnya tidak bisa menggunakan bahasa isyarat dalam berkomunikasi.
Selain itu, masih banyak istilah HKSR yang belum ada terjemahannya dalam bahasa isyarat, sehingga menyulitkan anak-anak disable untuk mudah mengerti seperti Amel, untuk mendapatkan pendidikan HKSR yang sangat penting.
Amel tidak sendiri, dari riset terbaru Perkumpulan Pamflet Generasi (PAMFLET) pada 2021 mengungkap, akses informasi seputar HKSR masih nihil bagi penyandang disabilitas dan anak muda yang berasal di luar kota besar (urban).
Penelitian ini melibatkan 31 anak muda berusia 18-24 tahun di tiga wilayah yaitu Bandung (Jawa Barat), Surabaya (Jawa Timur), dan Medan (Sumatera Utara) dan dilaksanakan pada periode Juni hingga Oktober 2021.
Periset dari Pamflet, Coory Yohana mengatakan riset yang bertujuan melihat pengetahuan orang muda terkait HKSR ini, menunjukkan disabilitas dan masyarakat wilayah rural masuk dalam kategori ‘tidak ada’.
Kondisi tersebut, mewakili pengalaman orang muda yang memandang informasi atau pengetahuan tentang seksualitas dan reproduksi tidak pernah atau tidak bisa mereka dapatkan.
Para disabel ini, banyak dari mereka yang mengalami berbagai hambatan utamanya terkait ketiadaan akses informasi yang memadai. Pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB) juga belum bisa optimal mengedukasi soal HKSR.
Mereka juga belum banyak yang ‘tersentuh’ pendidikan HKSR akibat minimnya sumber daya. Ini disebabkan, tiap bentuk disabilitas mesti mendapatkan penanganan (treatment) yang berbeda dan khas.
“Ada keterbatasan menyampaikan informasi,” ujar Coory dalam paparan riset di Luminor Pecenongan, Jakarta Pusat, Senin (13/12/2021) lalu.
Dalam riset itu disebutkan, ada seorang perempuan disabel asal Surabaya, AYY berusia 23 tahun, mengatakan HKSR ditiadakan dari pembelajaran setelah dia naik ke kelas 2 SMP. Alasannya, pelajaran seperti itu dianggap bersifat multi interpretasi sehingga memiliki kecenderungan untuk multitafsir.
“Pada akhirnya, pendidikan seks ditiadakan dan menjadi tabu bagi teman-teman difabel,” ujar AYY.
Perempuan disabel lainnya, ARS berusia 19 tahun asal Binjai mengatakan, hambatan yang muncul dari pendidikan HKSR juga berasal dari lingkup keluarga atau lingkungan terdekat yang tidak mendukung. Misalnya saja, tidak bisa menggunakan bahasa isyarat dalam berkomunikasi.
Terlebih, hambatan lainnya juga disebabkan karena masih banyaknya istilah HKSR yang belum ada terjemahannya dalam bahasa isyarat.
“Teman-teman yang punya masalah tentang seksual juga kesulitan dalam mengakses, gitu. Dan ketika kita berkomunikasi, justru orang yang kita tanyakan, itu kan berverbal kan, beroral, kita nggak ngerti. Jadi sama aja ketika kita dikasih tahu, juga kita nggak paham,” kata ARS.
Tak hanya difabel, Coory melanjutkan, hambatan yang dialami oleh kalangan orang muda di luar kota besar, umumnya berkenaan dengan keterbatasan infrastruktur informasi seperti internet yang dipandang sebagai salah satu sumber utama orang muda untuk mengenal HKSR.
“Di wilayah rural, anak muda mencari sendiri. Mereka susah juga, ketika mengakses internet tapi belum stabil,” imbuh Coory.
Kondisi tersebut terjadi pada seorang responden riset, perempuan asal Sumedang, HM (21 tahun), mengungkapkan susahnya dirinya yang tinggal di pinggiran kota dalam mengakses informasi HKSR. Internet di sana masih mengalami banyak kendala. Sementara, pertemuan-pertemuan seperti FGD (Focus Group Discussion) di pedesaan juga masih minim jika dibandingkan di kota.
Selain juga akibat norma di tengah masyarakat yang banyak menganggap HKSR itu tabu.
Di wilayah rural, adat dan budaya yang berlaku juga dipandang belum mendukung sikap terbuka dalam membahas HKSR. Terlebih lagi, kondisi sosial dan ekonomi membuat kondisi rural masih rentan terhadap pelanggaran hak seperti perkawinan anak atau kawin paksa.
“Isu ini sangat masih dianggap tabu bagi masyarakat tradisional di daerah pinggiran, para orang tua, sesepuh adat. Apalagi kalau dikaitkan dengan masalah kultur,” jelas HM.
Lalu bagaimana kondisi orang muda lainnya dalam mengakses HKSR?
Coory menyebut, ada dua kategori lainnya yang menggambarkan kondisi edukasi HKSR di kalangan orang muda dalam risetnya. Yaitu, kategori terbatas yang mewakili pengalaman orang muda yang mampu mengakses informasi HKSR, namun tidak menyeluruh dan cenderung terbatas.
Kaitannya ini, dia mencontohkan, pengetahuan HKSR yang institusi pendidikan berikan cenderung hanya menyentuh isu permukaan reproduksi. Pengetahuan seputar HKSR peserta biasanya diperkaya dengan ajaran keluarga di rumah yang juga masih sangat terbatas. Misalnya, pembahasan di rumah sekadar memberikan pemahaman seputar perbedaan laki-laki dan perempuan. Alhasil, orang muda mendapatkan pemahaman yang tidak lengkap.
Sementara kategori ketiga yaitu mewakili pengalaman orang muda yang memiliki level aksesibilitas cukup tinggi terhadap informasi HKSR.
Ini terjadi, pada orang muda yang memandang bahwa informasi sudah ada dan dapat diakses adalah mereka yang sudah terlibat dalam komunitas atau organisasi HKSR seperti Palang Merah Indonesia (PMI).
Lalu, ada pula orang muda yang telah mendapatkan pendidikan khusus yang berkaitan mengenai HKSR di perguruan tinggi seperti mata kuliah gender dan seksualitas atau jurusan Kesehatan Masyarakat. Hingga mereka yang terlibat dalam gerakan memperjuangkan HKSR, seperti SeBAYA Jawa Timur dan Hope Helps.
“Paling tinggi HKSR diakses anak muda yang sudah terlibat komunitas memang,” tegas Coory.
Riset itu juga menggarisbawahi soal layanan kespro dan seksual di Indonesia yang sampai kini memang masih jadi sebuah kemewahan. Dikarenakan cenderung tidak terjangkau. Terlebih, minimnya alokasi sumber daya memadai sampai angka kemiskinan tinggi memperparah situasi.
“Kondisi layanan kespro dan seksual bagi orang muda bisa dimengerti melalui 3 kategori akses, tidak ada atau tidak tahu, terbatas, serta ada dan bisa diakses,” katanya.
Tantangan dan Rekomendasi Menyuarakan HKSR
Dari 31 partisipan FGD di tiga wilayah, 22 orang atau setara 70% menyatakan bahwa mereka sudah pernah terlibat dalam upaya menyuarakan HKSR. Sedangkan, tujuh orang lainnya, sudah membahas isu HKSR dengan cara peer to peer atau belajar dari sesama teman muda.
Ada pula, tujuh orang responden menyuarakan edukasi HKSR lewat media sosial, sementara delapan lainnya terlibat melalui kegiatan komunitas atau organisasi yang fokus di isu HKSR.
Sementara itu, sembilan orang menyatakan bahwa mereka belum pernah terlibat dalam upaya menyuarakan HKSR. Mereka yang belum menyuarakan mengatakan bahwa ada rasa takut akan stigma negatif terhadap isu HKSR dan keraguan akan pengetahuan yang sudah mereka miliki sebagai orang muda.
Ini senada dengan studi dasar yang dilakukan oleh Puskagenseks UI untuk RHRN 2, dimana sebanyak 30,33% responden survei menyatakan bahwa mereka merasa ‘malu’ ketika mencari informasi terkait HKSR, apalagi untuk terlibat dalam gerakan HKSR.
“Dalam FGD riset ini, kami menemukan bahwa orang muda, baik yang belum atau sudah terlibat menyuarakan HKSR, menghadapi banyak tantangan. Faktor yang menjadi penghalang orang muda menyuarakan HKSR ada dalam beberapa wujud dan datang dari beberapa lapisan, yaitu personal, privat, publik, dan institusional,” kata Coory.
Maka dari itu, pihaknya memberikan rekomendasi untuk mendukung orang muda menyuarakan HKSR. Di antaranya, di lingkup personal, mitra dapat membantu orang muda meningkatkan kemampuan intrapersonal seperti membangun kepercayaan diri, pengetahuan, dan penguatan potensi diri.
Selanjutnya, perlu didorong adanya pemahaman level kedua (mendalami HKSR), namun dengan pemantik seputar pemahaman level pertama (membongkar stigma dan tabu) dan diselesaikan dengan level ketiga (menyuarakan HKSR).
Menyesuaikan perancangan pelibatan orang muda dengan ketertarikan orang muda. Mulai dari kurikulum, proses belajar hingga mentor. Hingga memastikan aksesibilitas dan inklusivitas dalam setiap kegiatan pelibatan orang muda.
“Perlu pula mendorong agensi orang muda secara penuh untuk menyuarakan HKSR yang kontekstual di lingkungan masing-masing. Sehingga leluasa dalam memilih apa yang disuarakan dan cara menyuarakan,” pungkasnya.