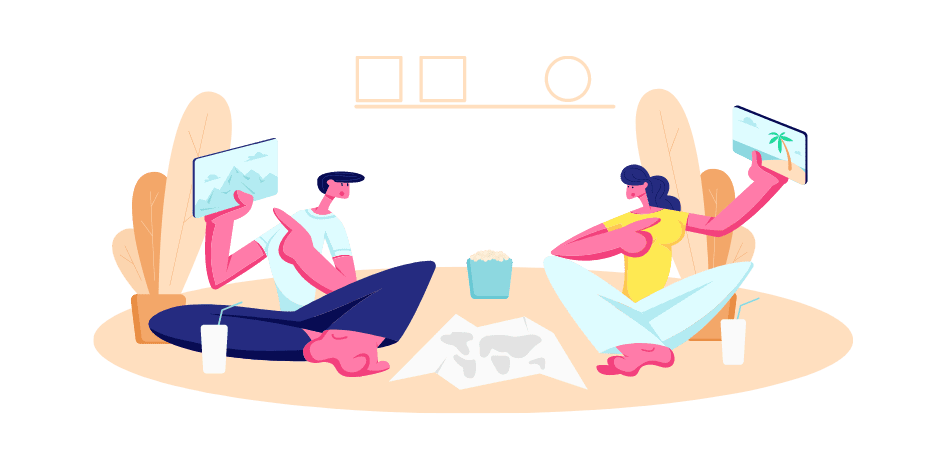“Pada saat dipecat aku sudah habis-habisan kerja. Tiba-tiba down sekali, depresi berbulan-bulan. Dan berbarengan ada masalah personal juga. Aku sampai nggak keluar kosan, nggak makan dan nggak ngapa-ngapain. Salah satu alasan keluar dari asosiasi karena marah, kecewa malu. Karena sudah tidak berstatus apa-apa dan tidak tahu mau ke mana”
Demikian pengakuan seorang perempuan pekerja seni yang menjadi responden dalam riset “Kerja Emosional Perempuan” yang dilakukan Koalisi Seni. Pengakuan ini menggambarkan bagaimana para perempuan pekerja seni harus bekerja dalam ketidakpastian, meski telah mencurahkan semua energi dan waktunya.
Dari riset itu terungkap, bagaimana perempuan pekerja seni lebih terbebani kerja emosional karena ada ekspektasi yang berbeda terhadap mereka ketimbang pada pekerja seni laki-laki.
Kalau kamu nanya apa sih kondisi kerja emosional itu? Itu meliputi segala bentuk pengelolaan emosi pribadi di tempat kerja untuk ditampilin ke orang lain, gimana menangani emosi orang lain, dan mengubah emosi orang lain.
Bentuk kerja emosional itu bisa berupa nampilin maskulinitas, ciptain suasana kondusif, jaga reputasi, ngadepin perundungan, kudu terus-terusan melakukan interaksi sosial, nangani keluhan, kasih bimbingan psikologis, dan jaga citra di media sosial.
Berat ya? Makanya kerja emosional ini sering memicu kelelahan fisik, depresi, paranoia, kelelahan mental, dan sakit kepala. Apalagi banyak responden bekerja tanpa pelindungan yang memadai terhadap semua implikasi kerja itu. Dukungan hanya bisa diharapkan dari keluarga atau komunitas mereka.
Kondisi ini diperburuk oleh gak adanya dukungan kesehatan seperti asuransi kesehatan maupun penggantian biaya berobat. Perlindungan di tempat kerja dalam bentuk forum diskusi atau serikat pekerja pun belum dimiliki secara rata di banyak tempat kerja.
“Perempuan dianggap punya sifat feminin seperti kooperatif, perhatian, merawat, dan ramah. Sifat itu dianggap terberi dan alamiah untuk perempuan, padahal kenyataannya tidak. Dampaknya, perempuan yang jadi pekerja seni harus menanggung beban kerja emosional,” ujar Koordinator Peneliti Kebijakan Koalisi Seni, Ratri Ninditya, pada saat peluncuran survei pada Kamis, (16/12/2021) lalu.
Riset dilakukan pada 2021 dengan survei daring yang melibatkan 202 responden. Ada juga analisis wawancara mendalam dengan 9 narasumber yang berasal dari perempuan (cisgender maupun transgender) yang bekerja di sektor seni dengan peran di balik layar dan menangani interaksi publik secara intensif.
Secara umum, hasil survei ini nunjukin kalau perempuan pekerja seni cenderung bekerja dengan intensitas kerja tinggi dan beban emosional besar, tidak dibekali keterampilan kerja yang cukup, kurang punya pengaruh dalam pengambilan keputusan, dan bekerja dengan durasi panjang. Selain itu, banyak responden yang diupah sangat rendah.
Dari 8 responden dengan skor kondisi kerja terburuk, separuhnya bekerja sebagai manager. Lebih dari separuh (5 orang) bekerja pada individu dan separuh dari mereka juga bekerja di lembaga nirlaba. Hampir separuh responden, tepatnya 93 responden, mengaku kalau mereka bekerja tanpa kontrak tertulis.
Perempuan pekerja seni juga dihadapkan pada intensitas kerja tinggi yang mencakup: kecepatan kerja tinggi, tenggat waktu pendek, keharusan mengelola banyak pekerjaan sekaligus, dan beban kerja emosional yang besar.
Para perempuan ini kudu gawe dalam kondisi kerja yang gak sepenuhnya aman. Hampir separuh responden (46%) mengaku bekerja tanpa kontrak tertulis. Terus lebih dari 25% pernah mengalami kekerasan di tempat kerja setidaknya sekali dalam setahun terakhir. Bentuk kekerasan bisa kekerasan fisik, pelecehan seksual, atau perundungan. Perundungan yang paling sering terjadi, disusul kekerasan seksual dan kekerasan fisik.
Kondisi penghasilannya mengkhawatirkan, dengan 41% mengaku upah kerjanya belum memenuhi standar UMR. Udah gitu, mayoritas atau 82% responden belum ikut sebagai anggota serikat atau organisasi yang sejenis.
“Kondisi kerja buruk ini berbanding terbalik dengan tingginya motivasi kerja responden. Tingginya motivasi di tengah buruknya kondisi kerja bisa berdampak pemakluman dan pelanggengan eksploitasi, serta pensiunnya pekerja dari sektor seni budaya,” kata Harits Paramasatya pada kesempatan yang sama.
Luput dari perhatian pemerintah
Kerja seni emang masih jadi blankspot bagi para pembuat kebijakan. Sektor kerja seni dapat dikatakan sama sekali luput dari kebijakan public mengenai ketenagakerjaan yang mengandung bias manufaktur dan bias kerja formal.
Meski telah lahir Undang-undang (UU) Pemajuan Kebudayaan dan UU Ekonomi Kreatif, keduanya belum secara spesifik mengatur hak-hak pegiat seni dan pelaku kreatif sebagai pekerja.
Kaburnya relasi kerja dan sikap-sikap bias gender yang berlaku luas dalam sektor seni yang patriarkis, membuat kondisi kerja pekerja seni perempuan masih buruk. Imbasnya, beban kerja emosional yang sangat besar dengan implikasi yang sangat dirasakan adalah akses terbatas pada sistem pendukung.
Kerja emosional, sebagai salah satu aspek kerja yang paling intens, dilakukan di tengah kondisi ketidaksetaraan, atau ketimpangan yang dilanggengkan. Hasil wawancara yang fokus pada aspek kerja emosional menunjukkan, pekerja seni perempuan menghadapi berbagai bentuk ketimpangan yang dilanggengkan melalui seksisme, misogini, dan transfobia; kaburnya relasi kerja; dan gak adanya kebijakan yang berpihak pada hak pekerja seni perempuan.
Ketiga hal ini membuat pekerja seni perempuan harus melakukan kerja emosional ekstra dan menanggulangi risiko kerjanya sendiri.
Praktik seksis dan patriarkis terwujud dengan kurang dilibatkannya pekerja perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Tujuh responden melapor langsung ke pimpinan atau pendiri laki-laki. Beberapa di antaranya memimpin dalam jangka waktu yang panjang, bahkan sepanjang organisasi tersebut berdiri.
Pada lembaga dan perusahaan yang berpusat pada satu figur laki-laki, keputusan pimpinan seringkali diambil tanpa mendiskusikannya terlebih dulu dengan anggota lain dan tidak bisa digugat.
Beberapa responden menyebut, pemimpin lelaki menentukan visi dan target, tapi tanggung jawab pencapaiannya dibebankan ke pekerja perempuan. Pada sebagian besar kasus, narasumber tidak memiliki suara dalam pengambilan keputusan di tempat kerja mereka.
Sikap misoginis tampak ketika perempuan harus bekerja lebih keras dari kolega mereka yang lelaki untuk mencapai pengakuan yang setara. Selain itu, isu perempuan dianggap sebagai hal yang tidak penting atau bahkan dianggap tidak ada oleh kolega laki-laki.
Narasumber juga menyebutkan kalau kolega lelaki kerap menganggap mereka tidak kompeten dalam pekerjaan karena mereka adalah perempuan. Panggilan meremehkan juga ditujukan pada perempuan, seperti “ibu-ibu arisan” atau “cewek-cewek rumpi” kerap dilontarkan kepada pekerja perempuan.
Survei juga menemukan hanya sebagian kecil yang diberikan pembekalan khusus dalam meningkatkan kapasitas oleh tempat kerja mereka. Sebagian besar responden mengembangkan sendiri kapasitas dirinya dengan terjun langsung ke pekerjaan.
Sebagian besar responden juga gak punya wadah khusus untuk menyampaikan aspirasi mereka di tempat kerja.
Kemapanan dan prospek kerja menjadi salah satu isu yang menonjol bagi para perempuan pekerja seni, di mana 41 responden sangat yakin mereka bisa kehilangan gaweannya dalam waktu 6 bulan. Sementara 15 responden sangat setuju kalau pekerjaannya sekarang tidak memberikan prospek karir yang baik.
“Kondisi penghasilan juga bisa dibilang mengkhawatirkan, dengan 41% responden mengaku kalau upah kerja mereka belum memenuhi standar UMR,” terang Ratri.
Kondisi kerja buruk ini berbanding terbalik dengan tingginya motivasi kerja perempuan pekerja seni. Tingginya motivasi di tengah buruknya kondisi kerja bisa berdampak pada pemakluman dan pelanggengan eksploitasi serta pensiunnya pekerja dari sektor seni budaya.
Kesepenuhhatian pekerja pada sektor seni perlu diakui dan dihargai melalui mekanisme pelindungan risiko kerja yang memadai, baik di tingkat peraturan dan perundangan, maupun kebijakan khusus di tempat kerja.
Hadapi Transfobia
Selain seksisme dan misogini, pekerja transpuan juga harus menghadapi transfobia saat bekerja. Mereka seringkali dilarang untuk mengekspresikan gender mereka di tempat kerja. Para transpuan harus mengingkari identitas asli mereka dan berpenampilan sebagai lelaki agar bisa mendapatkan pekerjaan.
Aturan yang dibuat Komisi Penyiaran Indonesia melalui Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) tahun 2012 melanggengkan transfobia ini. P3SPS diterbitkan bersama artikel di situs KPI yang menyatakan larangan penyiaran konten yang memiliki unsur LGBT, yang mencakup transpuan.
“Hal ini membuat wadah berkarya transpuan yang berkegiatan di bidang akting makin terbatas,” imbuh Ratri.
Di tengah rezim ketidaksetaraan ini, para pekerja perempuan bertahan karena rasa cinta pada seni dan cita-cita untuk mengembangkan tempat kerja menjadi lebih baik. Mereka memandang kerja seni sebagai panggilan hidup dan “kerja untuk kebaikan”.
Hal ini juga sejalan dengan hasil survei yang menunjukkan tingginya motivasi kerja. Sayangnya Motivasi yang begitu kuat ini dihadapkan pada budaya kerja bias gender dan relasi-relasi kerja yang kabur. Pekerja seni perempuan pun menjadi lebih rentan saat tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, hingga mengakibatkan beban dan risiko kerja makin tak tampak dan minim pelindungan.
Kerja emosional yang dilakukan, ujar Ratri, tidak diakui sebagai jenis pekerjaan tersendiri di tempat kerja dan tidak disebutkan secara eksplisit di deskripsi pekerjaan. Lebih buruk, definisi pekerjaan emosional belum dipahami.
Keseluruhan pekerjaan, termasuk kerja emosional di dalamnya, dilakukan tanpa pelatihan atau bahkan penjelasan singkat tentang hal ini. Dukungan untuk melakukan kerja emosional juga sangat minim. Pelatihan, anggaran, ataupun jenis-jenis bantuan lainnya hampir gak ada.
Pada beberapa kasus, responden harus membiayai perlengkapan yang dibutuhkan untuk mengerjakan kerja emosional dari dana pribadi mereka. Ini karena kerja pemberi kerja belum menganggap kerja emosional sebagai satu bentuk kerja, tapi dianggap sebagai bagian pekerjaan sehingga tidak dihargai di lingkungan profesional.
“Hal ini membuat narasumber kerap kurang dihargai oleh pemberi kerja karena sebagian pekerjaannya dianggap bukan kerja profesional,” tulis laporan survei.
Rendahnya penghargaan akan kerja emosional memicu beban berlipat: mereka dituntut untuk bisa mengidentifikasi kerja emosional, menjalankannya, dan mengembangkan kapasitas mereka secara mandiri tanpa dukungan yang memadai.
Gak semua pekerjaan emosional ini dilakukan untuk mencapai target kerja, tapi demi bisa bertahan di tempat mereka bekerja. Dilihat dari kondisi kerja seni yang kerap tak memiliki batas jelas antara hubungan personal dan profesional, batasan antara kerja emosional dan regulasi emosi pun melebur.
Secara garis besar, jenis kerja emosional yang dialami oleh responden dapat dibagi dua: kerja emosional yang dilakukan untuk menjalankan deskripsi kerja, dan kerja emosional sebagai efek samping dari kondisi lingkungan kerja yang patriarkis. Pada hakikatnya, kedua jenis kerja emosional ini dapat muncul dalam bentuk sama.
(Tulisan Ini Merupakan Bagian dari Program “Suara Pekerja: Stop Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja” yang Mendapat Dukungan dari “VOICE”)