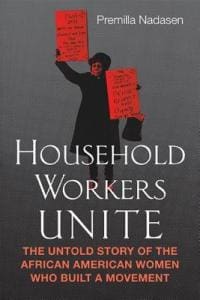Video ceramah seorang artis yang berprofesi sebagai mubalig perempuan berdurasi tak kurang dari dua menit, beberapa waktu lalu viral dan menjadi perbincangan. Versi lebih lengkap video itu berjudul “Jangan Ceritakan Aib Pasangan di Sosmed” yang berasal dari sesi pengajian di Masjid Al-Muhajirin, Magelang.
Terlepas dari fakta bahwa video tersebut telah dipotong dan adanya klarifikasi susulan dari artis yang mubalig tersebut, namun narasi soal KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) yang dikatakan mubaliq itu justru banyak menjadi perhatian. Banyak publik menganggap, mubalig itu seolah menormalisasi adanya KDRT yang dialami istri, sebagai upaya menutupi aib suami.
Di video itu, KDRT menjadi contoh untuk penekanan tema utamanya soal perihal rahasia (aib) rumah tangga yang dianjurkan agar tak dibocorkan kepada orang lain, termasuk orang lain ataupun teman. Disayangkan pula, perempuan dianggap sebagai orang yang banyak melebih-lebihkan cerita kaitannya dengan peristiwa yang ia alami di rumah tangga.
Padahal KDRT, apapun alasannya, hal itu tetaplah perilaku yang tidak diperbolehkan. Termasuk dari sisi hukum di Indonesia dengan adanya Pasal 44 KUHP dan UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT yang bahkan telah ditetapkan sejak tahun 2004 lalu.
Relasi Kuasa KDRT: Suami Merasa Berwenang terhadap Istri
Kekerasan tetaplah kekerasan. Ada relasi kuasa yang sangat mungkin menjadi sebab sekaligus alasan di baliknya.
Jika cerita tersebut menggambarkan suami sebagai pelaku pemukulan, ini sangat mungkin terjadi karena ia memiliki posisi dominan sehingga merasa berhak atau sah-sah saja melakukan KDRT.
Posisi demikian bisa terjadi karena suami acapkali menjadi pencari nafkah tunggal keluarga, sehingga istri—dan terutama anak-anak—memiliki ketergantungan penuh. Jika tidak demikian, kondisi kultur sosial yang seolah menormalisasi atau bahkan mendukung tindakan tersebut.
Di beberapa masyarakat, termasuk di Madura, narasi perihal KDRT seolah masih menjadi hal yang mengawang-awang, jauh dari lingkungan kita. KDRT seperti jauh dari kehidupan kita, seolah-olah hanya terjadi di konten infotainment, di pemberitaan media ataupun di kisah perceraian di pengadilan. Sementara di akar rumput, KDRT dianggap nyaris dianggap tidak terlihat
Ironisnya, pada konteks suami sebagai pelaku KDRT seperti cerita yang dikutip dalam video tersebut, KDRT seringkali justru dianggap sebagai instrumen “pendidikan”, privilege, bahkan konsekuensi transaksional. Mengapa bisa begitu?
Pertama, sebagai instrumen “pendidikan”, KDRT dalam arti kekerasan fisik seperti memukul, menampar, dan lain sebagainya sering dianggap sebagai cara mendidik. Padahal relasi kuasa jelas sangat bermain di sini ketika suami diposisikan sebagai pihak yang mendidik istri dan karenanya ia bisa memilih metode pendidikan sesukanya, termasuk melakukan KDRT dengan dalih melakukannya karena sayang.
Narasi pertama ini, lantas dilegitimasi oleh beberapa asumsi yang cenderung menyederhanakan persoalan dan lagi-lagi menjadikan perempuan (istri) sebagai korban. Bukannya tidak disadari kesalahannya, kondisi ini bahkan dipertahankan dari waktu ke waktu.
Asumsi-asumsi lain juga menjadi mitos terhadap KDRT semakin kental, misalnya adanya kalimat seperti: perempuan adalah “tercipta dari tulang rusuk” sehingga harus diluruskan oleh sang suami. Suami dalam hal ini, juga seolah memegang kuasa: suami mendapatkan “peralihan tanggung jawab” dari ayah mertuanya, dan mitos superioritas laki-laki lainnya.
Penafsiran teks keagamaan secara bias (utamanya pada QS 4: 34) , yang disokong pola pikir dan lingkungan masyarakat yang patriarki juga berkontribusi melanggengkan asumsi-asumsi tersebut.
Kedua, privilege atau hak istimewa laki-laki selaku pihak yang disebut-sebut “menentukan” nasib istrinya kelak di akhirat. Ini juga yang juga bisa jadi potensi perempuan seolah harus tetap menurut dan bersabar pada suami.
Narasi perihal ridho atau kerelaan suami terhadap istri, yang hingga kini belum diimbangi pola pikir yang resiprokal (saling berbalasan), misalnya, belum banyaknya wacana timbal balik bahwa kerelaan istri terhadap suami juga sangat penting. Hal inilah yang acap kali digunakan untuk menormalisasi tindak KDRT.
Ketiga, konsekuensi transaksional. Sampai hari ini, masih ada yang berpandangan bahwa mas kawin dan/ nafkah yang diberikan suami mengharuskan perempuan untuk bisa menurut dan mensyukuri segala kondisi rumah tangga. Termasuk, jika berhadapan dengan suami yang “ringan main tangan” atau KDRT.
Ibarat buah simalakama, istri mencoba speak up (berbicara) atas apa yang dialaminya, namun ia dianggap lebay bahkan mendapatkan berbagai perundungan dan tuduhan yang semakin memojokkan. Sementara jika diam, ia berpotensi semakin menderita secara fisik maupun mental.
Sayangnya lagi, ancaman fisik dan psikis semacam itu tak sedikit pula yang tak disadari oleh korban KDRT. Ada pula mereka yang cenderung diam dan justru “harus bersabar” serta nrimo dengan situasi yang dihadapi. Bahkan ada yang menyamakan sikap itu dengan “bukti bakti” pada suami yang selama ini digaungkan sebagai kewajiban istri.
Sementara, label “pembangkang”, “pemberontak”, dan semacamnya pun disematkan bagi perempuan (istri) yang berani speak up atas kekerasan yang dialami. Tak jarang, bahkan mereka dikuliti sebagai biang masalah hingga mengakibatkan laki-lakinya melakukan KDRT.
Kekhawatiran atas video ceramah mubalig itu, juga terhadap para korban KDRT. Selama ini sudah mendapatkan kekerasan berlapis dan traumatis, juga semakin tak mudah untuk mengumpulkan keberanian speak up karena malah dianggap berlebihan.
Mendorong Perspektif HAM dan Kesetaraan
Pembacaan teks keagamaan secara kontekstual yang berperspektif HAM dan kesetaraan tentu diperlukan. Jangan sampai ada bias-bias yang justru melanggengkan kekerasan dalam bentuk apapun, termasuk KDRT terhadap perempuan.
Seperti dalam cerita yang disitir dalam potongan video tersebut, sosok istri solehah justru digambarkan sebagai mereka yang berkomitmen kepada suami dalam keadaan apapun dan bagaimanapun karakter moral suaminya.
Ini tampak sejalan dengan riwayat yang diketahui dha’if (lemah dan karenanya tidak bisa dijadikan hujjah) tentang seorang istri pada zaman Rasulullah yang bahkan tidak mau keluar rumah untuk menjumpai ayahnya yang sakit, lalu meninggal dunia karena mempertahankan janji pada sang suami untuk tidak ke mana-mana.
Dalam suasana di Jazirah Arab 14 abad yang lalu, konteks demikian barangkali cukup beralasan. Namun dalam konteks Indonesia di hari gini, janji demikian menjadi tidak relevan dan terkesan ngawur.
Prinsip yang dipegang teguh, seharusnya bukanlah pada person atau dalam hal ini suami, tetapi spirit atau nilai yang mendasarinya. Jika spirit-nya adalah melindungi istri, maka nilai untuk birru al-walidayn bisa menjadi pembanding untuk lebih bijak mengambil keputusan.
Dalam konteks memutus rantai KDRT, kita juga perlu menciptakan support system yang menjadi ruang aman bagi korban untuk berani speak up.
Bagaimana, perilaku KDRT dan pendiaman atas perilaku tersebut di lingkungan kita yang masih patriarki ini, sangatlah mungkin diwariskan kepada orang terdekat dari keluarga yang mengalami KDRT. Baik sebagai pelaku atau korban.
Maka, keberanian untuk bersuara dan melaporkan kasus KDRT pada pihak yang tepat tidak hanya akan memberi efek jera pada pelaku, tetapi juga mental support yang berarti bagi korban dalam proses kesembuhannya.