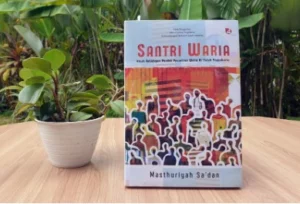Yuni tinggal di daerah pesisir Banten. Dalam sebuah rumah mungil yang sesak dan sempit, sesesak realitas yang mesti ia hadapi, dan sesempit pilihan- pilihan yang tersedia atas hidupnya di masa depan. Yuni punya impian mendapat beasiswa kuliah.
Sebagaimana anak-anak yang berangkat dari keluarga menengah ke bawah lain, dengan segala keterbatasan ekonomi dan akses terhadap pendidikan, beasiswa adalah salah satu, bila bukan satu-satunya, untuk memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Konsekuensi selanjutnya adalah meniti tangga sosial dan membawa diri keluar dari lingkaran setan bernama kemiskinan struktural.
Yuni siswi yang pandai, berprestasi, nilai-nilai akademiknya membukakan baginya kesempatan untuk mendapatkan beasiswa yang ia angan-angankan (kecuali untuk pelajaran bahasa Indonesia). Tanpa beasiswa tersebut, yang tersisa dari masa depan setelah lulus SMA adalah menjadi pekerja migran sebagaimana jalan hidup yang diambil tetangga-tetangganya.
Pilihan lain yang paling mudah dan lazim terjadi di lingkungan pedesaan adalah menerima salah satu dari sekian lamaran laki-laki yang datang ke rumahnya. Pilihan terakhirlah yang menjalin rentetan konflik dalam film garapan Kamila Andini ini yakni kenyataan yang harus dihadapi Yuni, serta upayanya untuk keluar dari realitas tersebut.
Fim Yuni dibuka dengan adegan Yuni yang sedang berkemas berangkat sekolah: mengenakan daleman, memakai seragam sekolah, mengikat rambut, memakai jilbab, mengendarai motor. Semua pernik yang dikenakan Yuni, hingga kendaraan yang dipakainya berwarna ungu. Penekanan ungu yang melekat dalam diri dan keseharian Yuni, hingga semesta cerita dalam film ini disinyalir merupakan alusi-simbolis atas kesetaraan dan keadilan gender.
Warna ini digunakan dalam peringatan Hari Perempuan Sedunia, serta menjadi simbol solidaritas publik untuk mendorong pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia.
Dalam periodisasi gerakan feminisme, ungu merupakan simbol dari gerakan feminisme kontemporer. Berangkat dari pemahaman ini, impulsivitas dan fanatisme Yuni terhadap ungu sekaligus menjadi alegori bagi kegelisahan Yuni dalam meraih otonomi atas dirinya yang selama ini dibungkam oleh aparatus-aparatus represi keluarga dan norma-norma tradisional setempat.
Di lingkungan sekitar Yuni berlaku pemahaman bahwa perempuan yang menerima lamaran adalah perempuan yang beruntung, dan lamaran tersebut tabu untuk ditolak. Norma tersebut ia ketahui dari gosip-gosip di sekolah juga nasihat tetangga kepadanya.
Oleh karena masyarakat mengidealkan hal demikian, Yuni dituntut untuk patuh. Namun bila ia mengikuti ekspektasi tentang menjadi perempuan baik yang dikonstruksi oleh masyarakat di lingkungannya, itu berarti impiannya untuk mendapatkan beasiswa harus ia kubur dalam-dalam, karena salah satu syarat untuk mendapatkannya adalah si penerima berstatus lajang/belum menikah.
Situasi lain yang membebani dan membuat eksistensi Yuni sebagai perempuan tersubordinasi adalah lamaran-lamaran yang datang kepadanya diikuti dengan iming-iming material. Ringkasnya, dalam konstruksi relasional itu, Yuni adalah barang dagang yang ditukar dengan nominal, dan bila terbukti Yuni masih perawan, nominal yang diberikan bisa lebih tinggi lagi. Hal ini secara tidak langsung menegaskan kedudukannya sebagai barang dagang dengan kondisi masih prima, tersegel, praktis akan mendapat nilai tukar yang lebih mahal.
Lantas, bagaimana upaya Yuni dalam melawan lapis-lapis kenyataan pahit yang dihadapi, dilihat, dan didengarnya tersebut?
Awalnya perlawanan yang dilakukan Yuni yaitu dengan melakukan penolakan atas lamaran-lamaran yang datang padanya, dan kerisihannya atas nilai-nilai tradisional yang dibebankan masyarakat kepadanya.
Resistensi Yuni bergolak di dalam dirinya, dan ia menghadapi semuanya sendirian. Belum ada solidaritas dari teman-teman Yuni yang pada dasarnya sama galaunya atas masa depan yang hendak mereka hadapi.
Pesisir Serang yang menjadi latar cerita ini dengan segenap budaya dan adat istiadat tradisionalnya dibingkai dalam logika sebagai kolot, terbelakang, primitif yang mewujud dalam pernikahan usia anak, kedudukan perempuan dalam masyarakat, himpitan ekonomi. Tak ada suaka sedikitpun di sana bagi Yuni. Tidak dari keluarga, juga dari guru sekolahnya, apalagi teman-temannya.
Sang penulis cerita seakan-akan berkata kepada penonton, bila tidak ingin bernasib sama dengan Yuni satu-satunya cara adalah, pergilah ke kota dan hiduplah seperti orang-orang di sana!
Kembali ke pertanyaan sebelumnya, bagaimana Yuni melawan itu semua, dengan keterbatasannya sebagai remaja dan akses berpikir yang terbatas? Dalam kondisi yang semakin menghimpitnya, dengan datangnya lamaran dari gurunya, dengan pola transaksional yang serupa dan tak bisa ia tolak, ia melakukan seks. Ya, ia melakukan hubungan seksual dengan Yoga, laki-laki yang ia sukai tetapi tak dapat dimilikinya.
Lalu kemenangan kecil apa yang Yuni peroleh setelah berhasil melakukan hubungan seksual, yang sang sutradara anggap sebagai momen empowerment tokohnya? Pada hari pernikahan dengan gurunya, Yuni menghilang. Ia pergi ke suatu danau dan menenggelamkan diri.
Setelah menonton film tersebut saya hanya bisa berkata, ”hah?” Awalnya saya sangsi atas dugaan bahwa perlawanan yang Yuni lakukan atas amarahnya terhadap masyarakat dan keluarga yang merepresinya adalah dengan melakukan hubungan seksual. Jangan-jangan saya kurang cermat atau salah mengerti konstruksi yang dibangun dalam cerita tersebut, dan paling parah, saya tidak bersimpati atas kondisi Yuni sebagai perempuan yang serba tersubrodinasi. Kemudian dugaan saya terbukti.
Dalam wawancara dengan Detik, sang sutradara Kamila Andini, mengonfirmasi bahwa adegan seks tersebut merupakan adegan yang paling penting, satu-satunya tindakan yang Yuni pilih atas keinginannya sendiri.
Sebelum beranjak lebih jauh, analisis ini bukan dalam rangka kritik terhadap adegan seks dalam kacamata moral normatif, apalagi menganggap adegan seks dalam film Indonesia adalah sesuatu yang tidak perlu dan tabu, tetapi kritik terhadap gagasan bahwa hubungan seksual adalah sarana pembebasan diri segala nilai represif yang menderanya.
Karena, berangkat dari asumsi bahwa sarana perlawanan terhadap tabu seksual adalah dengan melakukannya, rentan terjerumus dalam wacana kolonial, atau norma seksual ala Barat. Apalagi bila keputusan tersebut adalah satu-satunya upaya yang dilakukan dari sekian kemungkinan yang tersedia.
Pertanyaan selanjutnya, benarkah adegan seks tersebut kontekstual dengan logika dalam semesta cerita film, dan mengandung urgensi sebagai laku pembebasan diri? Apakah adegan demikian bertautan dengan pendapat bahwa, kekuatan yang dianggap merepresi seksualitas manusia adalah adat, tradisi, dan agamanya sendiri, sedangkan pembebasan dicari dengan memandang ke Barat? Seperti gagasan Katrin Bandel dalam Kajian Gender dalam Konteks Pascakolonial.
Mengingat tidak digambarkan proses kesadaran yang menggiring Yuni hingga mencapai keputusan tersebut, semuanya seakan terjadi secara begitu saja. Tak adakah solusi empowerment yang bisa didapatkan dari kultur sosial yang membuat Yuni terhimpit, sebagaimana yang Kartini lakukan ketika menerima lamaran seorang bupati Rembang, dengan syarat ia tidak mau melakukan prosesi adat dengan berjalan jongkok, mencium kaki suami, kesempatan untuk tetap dapat mengejar cita-cita, hingga meminta dibuatkan sekolah khusus perempuan?
Sebelum menjawabnya, terlebih dahulu saya ingin beranjak dari Serang ke Jombang, tempat film Perempuan Berkalung Sorban (selanjutnya ditulis PBS), mengambil latar. Pemilihan PBS sebagai pembanding dalam analisis ini didasarkan pada kemiripan konflik, setting tempat berupa pedesaan, dan penulis cerita yang mempunyai latar belakang yang sama. Yuni ditulis oleh sang sutradara sendiri, Kamila Andini, dan PBS ditulis oleh Gina S. Noer dengan sutradara Hanung Bramantyo.
Dalam PBS, Annisa (Revalina S. Temat), lahir dari seorang kiai pendiri pesantren tradisional di pesisir kabupaten Jombang. Annisa mempunyai angan-angan untuk kuliah, memberdayakan santri-santri di sana untuk mendapat akses pengetahuan yang luas dengan membangun perpustakaan di pesantren ayahnya. Semua impian itu runtuh karena ia dijodohkan dengan seorang santri, Samsudin (Reza Rahadian) yang ayahnya punya sumbangsih material ketika pondok tersebut baru berdiri dengan kondisi ekonomi yang sulit. Konsekuensi dari menolak lamaran tersebut bisa diduga.
Sepanjang film kita disuguhi dengan posisi perempuan dalam sistem sosial, budaya, dan norma agama setempat yang disampaikan secara eksplisit melalui tokoh-tokohnya maupun yang dibangun secara implisit dalam bangunan cerita.
Namun yang membedakan PBS dengan Yuni adalah bagaimana subjek perempuan tampil, mengelola diri, dan berdialektika dengan kenyataan yang mereka hadapi serta hadirnya sistem dukungan yang bersimpati bagi situasi pahit sang tokoh.
PBS menampilkan perempuan sebagai individu yang mempunyai kesadaran untuk bertindak di tengah segala keterbatasan diri dan situasi yang mengimpitnya. Di samping masyarakat yang represif, dukungan hadir dari tokoh sang ibu, yang menyertai anaknya dalam menanggung beban sosialnya. Memberi kehangatan ketika pernikahannya dengan Samsudin kandas akibat KDRT, membelanya secara terbuka di hadapan masyarakat yang hendak merajamnya atas tuduhan zina dengan Khudori (Oka Antara).
Tuduhan zina tersebut bermula dari rasa frustasi Annisa atas konstruksi sosial yang menekannya. Supaya ia bisa keluar dari lingkungannya, Annisa memaksa Khudori untuk memperkosanya, dengan begitu ia akan dikeluarkan dari pesantren dan memulai kehidupan yang baru dengan Khudori yang kemudian menjadi suaminya. Khudori mengerti trauma rumah tangga yang dialami Annisa dan mau membersamainya.
Singkatnya, Khudori adalah tempat aman bagi Annisa selain ibunya sendiri. Karena dengan dihadirkannya sosok yang sama-sama berkesadaran dan menentang budaya patriarki yang menindas, perjuangan lebih mungkin terwujud. Terbukti, Annisa berhasil kuliah dan meraih cita-citanya membangun perpustakaan bagi santri-santri pesantrennya.
Dalam Yuni, sebagaimana telah dijelaskan di atas, tidak hadir satu pun agensi tokoh yang bersimpati dan membantu Yuni menghadapi kenyataannya. Sementara Bu Lies, guru sekolah Yuni, yang turut mendukung Yuni meraih beasiswa mempunyai potensi untuk membersamai Yuni dalam kondisi-kondisi kritisnya, mengingat semesta latar ceritanya yang sempit, nyaris tidak mungkin Bu Lies tidak tahu situasi pahit yang menimpa Yuni, yang akan menghalanginya mendapatkan beasiswa.
Namun potensi tersebut seakan-akan tidak dilihat oleh penulis skenario, dan semakin menegaskan ide tentang hubungan seksual sebagai momen empowerment perempuan mendahului bangunan dan logika cerita film. Menurut saya, persis di situlah wacana kolonial beroperasi.
Penulis cerita dan sutradara Yuni hanya menempelkan adegan seks tersebut sebagai riasan yang seolah-olah feminis, tindakan paling emansipatif, paling wajar, dan alamiah. Atas dasar itu, saya berani mengatakan bahwa Kamila Andini tidak simpatik terhadap tokoh bikinannya sendiri.
Yuni, dan film-film yang mengusung wacana seksualitas lain pada dekade kedua abad ini, hadir pada saat ketika ledakan wacana tentang feminisme dan seksualitas muncul.
Kini seksualitas, terutama feminisme, menjadi wacana populer dalam percakapan di media sosial, baik itu dalam aspek praktik, medis, ketubuhan, maupun wacana. Istilah seperti konsensual, kesetaraan gender, berbagi peran, edukasi seks, maskulinitas rapuh, body shaming, patriarkis, bertebaran ketika membicarakan topik terkait, dan itu perlahan-lahan diterima bukan sebagai tabu lagi.
Inilah barangkali yang membuat film Yuni diterima dan kemudian dibingkai sebagai film feminis, bahkan dijadikan rekomendasi tontonan oleh sejumlah media daring dalam menyambut Hari Kartini. Film Yuni sukses, sebagaimana film-film yang mengangkat wacana serupa, karena menghadapkan adat istiadat bersama norma-norma tradisionalnya dengan ide-ide modern ala kelas menengah perkotaan, atau lebih jauh, dengan Barat.
Fenomena tentang ledakan wacana yang telah disinggung di atas pun ramai diperbincangkan dan kemudian diterima oleh kalangan kelas menengah berpendidikan, hidup di kota, mengikuti arus perkembangan global dengan segala tawaran-tawaran perilaku konsumtifnya. Ini tentu bermasalah ketika segala yang datang dari luar, terutama Barat, dipersepsi sebagai kemajuan, modern, dan paling sah sebagai norma anutan, dan pada saat yang sama menganggap segala yang tradisional harus ditinggalkan.
Tentu saja kritik terhadap tradisionalitas itu sah dan memang perlu. Yang berbahaya adalah ketika kritik itu malah terjerumus ke dalam wacana kolonial sendiri, atau yang bermasalah lagi, bila kritik itu justru berpotensi terjebak struktur kolonial. Kita yang menjadi agen kolonialnya.