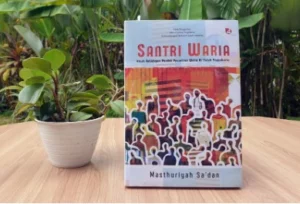Frasa “kesetaraan gender” barangkali sudah sering kita dengar belakangan ini baik dalam percakapan sehari-hari, guyonan, maupun acara diskusi publik yang serius. Hal ini, di satu sisi merupakan sinyal bagus dalam upaya mewujudkan lingkungan yang ramah gender.
Asumsinya, makin sering isu kesetaraan gender dibicarakan, orang tidak akan malu-malu lagi untuk sekadar mencari tahu, syukur-syukur menjadi simpatisan dan terlibat aktif di dalamnya. Di sisi lain, isu kesetaraan gender yang dibicarakan, diserap, dan dikampanyekan secara serampangan tanpa pemahaman komprehensif tentangnya justru berpotensi menciptakan polarisasi tersendiri.
Secara sederhana, pemahaman saya terhadap istilah kesetaraan gender adalah sebatas konsep dan praktik, bahwasanya laki-laki dan perempuan mendapat perlakuan yang adil dalam berekspresi (dengan segala bentuknya), berpolitik (memilih dan dipilih), berekonomi (akses terhadap pekerjaan dan pendapatan layak), hingga hal-hal semacam gaya berpakaian, tanpa perlu dihakimi.
Saya yakin bahwa pengertian ini sejatinya mudah dipahami. Akan tetapi, yang tak boleh dilupakan adalah kita tak hidup di ruang hampa. Gagasan-gagasan yang bertemu dan berdialektika bakal menyulut respons yang unik dan bermacam-macam. Tak terkecuali, yang menentang atau berseberangan.
Lalu, mengapa konsep yang sejatinya hanya mendambakan perlakuan yang adil berubah menjadi sikap saling membenci? Mengapa diskursus kesetaraan gender kerap kali berujung pada masalah toxic “perempuan melawan laki-laki”?
Menurut saya ada dua penjelasan. Pertama, fakta bahwa perempuan sering kali sudah berada dalam posisi dilemahkan. Mulai dari representasi kaum perempuan dalam budaya populer yang problematik, diskusi publik, hingga komposisi jumlah tenaga kerja perempuan yang timpang (terhadap laki-laki).
Sudah terlampau sering kita melihat setiap perilaku dan gagasan yang dianggap wajar (ketika) dilakukan laki-laki, jadi terasa berbeda bila dilakukan oleh perempuan, bahkan untuk sesuatu yang sesungguhnya tidak ada hubungannya dengan gender.
Banyak hal yang dilakukan perempuan dinilai, dikoreksi, dan dievaluasi dengan standar yang dipasang oleh laki-laki. Imajinasi atas perempuan yang “baik” dan “ideal” dibuat sekehendak hati laki-laki. Kita menyebut kondisi ini dengan lingkungan patriarkis.
Lelaki punya keuntungan karena secara kultur “diperbolehkan” untuk menilai dan menghakimi bagaimana sebaiknya perempuan berperilaku. Pada titik ini, kita seharusnya sudah mulai memahami logika atas kejengkelan perempuan.
Di sinilah tepatnya mengapa perempuan sudah berada dalam posisi dilemahkan dalam perjuangannya memperoleh hak-hak yang setara dengan laki-laki. Singkatnya, bagi mereka yang sudah dilemahkan, sulit untuk tak paranoid.
Kemungkinan beberapa orang akan jengkel dan berhenti membaca setelah akhir kalimat ini, tetapi saya harus bilang ini wajar belaka. Laki-laki pun mengalami hal yang sama. Perbedaan mendasarnya adalah bahwa laki-laki tidak menyadari atau bahkan tidak mau melihatnya sebagai masalah lantaran terlalu lama hidup dalam kultur yang memakluminya.
Kondisi ini diperparah dengan laki-laki yang kerap kali melakukan objektifikasi (baik yang disadari ataupun tidak) tanpa mendapatkan konsekuensinya. Beberapa bahkan kadung menikmati kondisi ini dan mungkin tidak sepakat dengan arah perubahan yang dituntut perempuan. Kondisi inilah yang menurut saya menjadi semacam lingkaran setan dan memunculkan sentimen-sentimen yang kontraproduktif dengan upaya kesetaraan gender.
Kedua, adalah sulitnya menundukkan arogansi masing-masing pihak dan menerima kenyataan bahwa sesekali, lelaki dan perempuan memang bertindak kurang bijak. Bagian inilah yang menurut saya paling sulit dan pahit untuk disampaikan, tetapi juga sangat penting.
Setelah poin pertama, melihat pernyataan ini keluar dari laki-laki akan terdengar aneh, tetapi apa boleh buat? Mau disukai atau tidak, ini memang terjadi.
Hak-hak yang dengan susah payah diperjuangkan, bukannya kemudian dapat dinikmati tanpa konsekuensi ataupun tanggung jawab, juga tidak membuat kita tercerabut dari konteks dan dimensi-dimensi lain di luar diri kita sendiri. Jika pada suatu masa, misalnya, kita sudah tak dilarang untuk merasa nyaman dengan bentuk tubuh dan diizinkan menunjukkannya di muka umum, bukan berarti kita bisa mencemooh sebagian lain yang memilih untuk menutupinya karena taat pada nilai yang berbeda. Merasa sudah merdeka ketika meniti jalan karier, bukan berarti secara bebas menghakimi mereka yang memilih peran domestik secara sukarela.
Pilihan-pilihan yang disebutkan di atas pun tak lepas dari dimensi hak dan tanggung jawabnya masing-masing. Menurut saya, kuncinya adalah tidak menyangkal bahwa mau sebebas apapun kita, hak-hak kita akan menemui wilayah batasnya di hadapan hak-hak orang lain.
Sependek pemahaman saya, kebebasan yang didambakan adalah kebebasan kolektif, bukan kebebasan yang hanya dimiliki sebagian (orang) saja. Sepakat dengan ide kebebasan berpendapat, misalnya, tidak membuat kita menjadi imun terhadap kritik balik dari yang “bukan kita.”
Melawan Stigma Perempuan dan Laki-laki
Perempuan tidak lemah, dan laki-laki boleh menye. Kedua hal ini tidak perlu ditandingkan atau dijadikan alat untuk mengukur tingkat kejantanan atau keperempuanan seseorang.
Menurut saya pribadi, stigmatisasi sedikit banyak menghambat kita menjadi manusia yang lebih utuh, mencegah kita menjadi ekspresif tentang perasaan masing-masing, bahkan memaksa kita memiliki mentalitas merendahkan karena merasa harus menjadi yang paling tinggi.
Oleh karena itu, pidato Emma Watson dalam peluncuran kampanye #heforshe di UN pada 2014 lalu saya rasa masih sangat relevan dan patut dijadikan pengingat bahwa problem kesetaraan gender bukanlah hal yang eksklusif menimpa perempuan, melainkan juga laki-laki. “Bagaimana mungkin mengharapkan perubahan,” kata Emma, “bila hanya separuh dari komunitas (masyarakat) yang dilibatkan?”
Pesannya perlu ditanamkan dalam benak kita, bahwa sudah saatnya laki-laki dan perempuan diperlakukan dengan asumsi bahwa keduanya berada di pihak yang sama dan punya daya untuk berubah. Meski pada kenyataannya masih ada sejumlah masalah, tetapi lebih baik daripada tidak melakukannya sama sekali. Hal ini tentu saja masih jauh lebih baik ketimbang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai musuh bebuyutan.