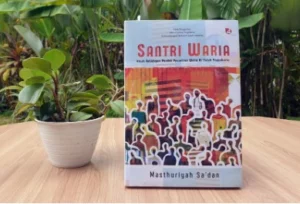Baru-baru ini, ketika ibu dari seorang teman meninggal, dalam pengumuman kematiannya, ia menggunakan foto dimana ibunya mengenakan syal di kepalanya. Teman saya bilang soal jilbab dan dia memilih foto itu karena dia percaya foto tersebut akan membantu membersihkan roh ibunya dari dosa-dosanya di akhirat. Betulkah? Kata siapa? Al-Qur’an? Hadits? Apakah sebegitu mudahnya untuk membersihkan dosa?
Lucunya, seumur hidup ibunya tidak pernah memakai jilbab. Bahkan, ia sering mencibir dan mengungkapkan ketidaksukaan terhadap perempuan berjilbab yang berupaya menutupi perbuatan buruk mereka, tidak Islami (korupsi misalnya), kemunafikan, memamerkan busana muslim terkini atau “jilbab politik” yang dikenakan politisi perempuan untuk memamerkan “kredensial Islam” mereka kepada para pemilih. Ibunya mengenakan syal pada pagi hari foto itu diambil hanya karena dia merasa kedinginan, dan dia menutup kepala dan bahunya untuk menghangatkan dirinya. Jadi mengapa putranya memaksakan “jilbab religius” padanya setelah dia meninggal, ketika dia menolaknya saat dia masih hidup?
Kasus teman saya di atas mungkin hanya membuat kita tersenyum kuning mengasihani pemahaman Islamnya yang tidak ada dasarnya. Tetapi ketika interpretasi yang menyimpang dari pemakaian jilbab menyebabkan seorang perempuan meninggal, itu jelas bukan bahan tertawaan. Inilah yang terjadi pada Mahsa Amini, seorang perempuan Kurdi berusia 22 tahun di Iran, yang ditangkap oleh apa yang disebut “polisi moral”, pada 13 September karena mengenakan jilbabnya secara tidak benar – dengan memperlihatkan sedikit rambut – dan meninggal tiga hari kemudian. Kematiannya memicu protes massal di seluruh negeri dan bahkan di berbagai penjuru dunia – di antaranya Athena, Berlin, Brussel, Istanbul, Madrid, New York, Paris dan Perth.
Jilbab menjadi wajib di Iran sejak Revolusi Islam 1979, dan peraturannya ditegakkan oleh Patroli Bimbingan yang sangat dibenci, juga dikenal sebagai polisi moral, yang mensurvei penduduk perempuan untuk “pelanggaran” kode pakaian publik. Mereka yang dinyatakan bersalah mengenakan jilbab secara “tidak pantas” didenda atau dipenjara – dan seringkali dilecehkan bahkan dianiaya ketika mereka sedang “direhabilitasi”.
Selama 43 tahun berdirinya negara Islam, sering terjadi protes terhadap aturan wajib jilbab, bahkan sejak awal, pada tahun 1979. Dalam beberapa tahun terakhir, protes semakin keras, tetapi pemerintah merespons dengan tindakan yang semakin keras, termasuk penggunaan teknologi pengenalan wajah (facial recognition).
Menurut aktivis Iran Masih Alinejad, “Bagi Republik Islam, jilbab adalah alat untuk mengontrol perempuan, dan melalui perempuan, mengontrol seluruh masyarakat. Bagi mereka, ini seperti Tembok Berlin. Jika kita meruntuhkan tembok ini, Republik Islam tidak akan ada. Perempuan melawan hukum hijab wajib dan semua hukum anti-perempuan di Iran, tapi inilah saatnya gerakan mendapatkan momentum. Ini adalah revolusi perempuan”.
Revolusi perempuan? Dalam teokrasi otokratis?
Ya! Menurut sejarawan dan penulis Iran-Amerika Abbas Milani pada tahun 2015, Iran adalah rezim paradoks: “Iran merupakan negara otoriter yang kejam […] di mana undang-undang misoginis menyangkal hak dan status yang setara bagi perempuan. Namun di balik wajah rezim yang kejam, berdenyut warga muda yang terhubung secara global dan gerakan perempuan yang mengesankan dalam jangkauannya, kewaspadaan dan kesabaran mereka”. Dan pengamatan Milani ternyata benar, terbukti dengan keberanian dan kekuatan yang ditampilkan oleh para perempuan penentang rezim.
Jadi bagaimana kematian Amini memicu ledakan kemarahan dan kemurkaan sehingga para perempuan sampai membakar jilbab dan memotong pendek rambut mereka, tindakan menantang luar biasa berani yang dapat merenggut nyawa mereka?
Kematian Amini adalah percikan yang meledakkan tong mesiu, seperti halnya pembunuhan archduke (gelar bangsawan setingkat pangeran) Frans Ferdinand dari Austria memicu Perang Dunia I. Rakyat Iran, terutama perempuan, sudah cukup merasakan ketertertindasan. Sina Toossi, mantan analis riset senior di Dewan Nasional Iran Amerika dan saat ini rekan non-residen senior di Pusat Kebijakan Internasional, menulis kolom berjudul “Protes jilbab Iran telah menyalakan api yang tidak dapat dipadamkan rezim” (World Politics Review, 26 September).
Jelas, bagi saya di Indonesia, yang memiliki mayoritas Muslim 88 persen dan merupakan tempat tinggal 13 persen Muslim dunia, perkembangan di Iran sangat menarik. Terlebih lagi karena isu di Iran berpusat pada jilbab, yang juga menjadi isu kontroversial di Indonesia (lihat: “Muslim headcover conundrum: when cover up really exposes”, The Jakarta Post, 4 Agustus).
Meski Indonesia negara semi-sekuler dan tidak ada hukum jilbab wajib, jilbabisasi paksa marak terjadi, menyebabkan banyak keresahan di kalangan perempuan muda, terutama siswi di beberapa sekolah yang tidak diberi pilihan. Jilbabisasi paksa ini merupakan indikasi bahwa Indonesia menjadi lebih konservatif, lebih otoriter, dan kurang demokratis.
Aturan jilbab wajib didorong ketidaktahuan. Memperbodoh dan membungkam massa selalu menjadi siasat penguasa yang ingin mengontrol rakyat, baik melalui cara agama maupun secara sekuler, biasanya ancaman atau kekerasan.
Ada kesenjangan besar di Indonesia, tidak hanya soal kekayaan, tetapi juga pengetahuan, termasuk pengetahuan agama. Indonesia memiliki banyak cendekiawan dan aktivis Muslim yang sangat baik, berpendidikan universitas, yang percaya pada demokrasi dan hak asasi manusia, yang tentu saja termasuk hak-hak perempuan. Tapi bagaimana mendidik massa yang mengandalkan ustadz yang konservatif, bahkan seringkali fanatik, dan mengandalkan media sosial yang tidak bisa diandalkan sebenarnya?
Cendekiawan feminis Muslim berlimpah di Indonesia, dan banyak dari mereka adalah laki-laki. Meskipun mereka mungkin tidak secara terbuka menyebut diri mereka feminis seperti Kyai Muhammad Husein, ulama terkenal dari Cirebon, mereka jelas percaya pada kesetaraan gender.
Bahkan, Azyumardi Azra, seorang cendekiawan Muslim yang sangat dihormati yang meninggal pada 18 September, mengatakan dalam ceramah untuk masyarakat Nurcholish Madjid pada tahun 2017 bahwa “semakin banyak masyarakat yang didominasi laki-laki, semakin kecil kemungkinannya untuk kebangkitan Islam. Semakin perempuan didomestikasi dan dibatasi, masyarakat akan semakin kurang egaliter”.
Banyak Muslim yang mendambakan kebangkitan Islam, tetapi mereka melakukannya dengan cara yang salah: dengan menindas dan mengontrol, yang sebenarnya sangat anti-Islami.
Cendekiawan Muslim yang sangat dihormati, Quraish Shihab, menulis sebuah buku tentang jilbab (2018). Intinya: jilbab tidak wajib bagi perempuan Muslim. Siapapun yang mempelajari Quran dengan benar mengetahuinya. Putrinya sendiri, Najwa Shihab, pembawa acara talk show populer, tidak mengenakan jilbab, dan tidak seperti istri banyak politisi terkemuka di Indonesia, ia tidak membiarkan dirinya ditekan untuk memakainya.
Baru-baru ini, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan pemerintah sedang menggalakkan paham Islam Wasathiyah, atau Islam moderat, untuk menjamin keharmonisan masyarakat kita yang majemuk. Indonesia telah lama terkenal sebagai negara Muslim moderat, tetapi entah bagaimana pemerintah membiarkan paham dogmatis Wahabi menyusup ke masyarakat kita. Hijabisasi paksa adalah salah satu indikator gejala ini.
Jadi, mari kita berharap bahwa ke depan, Iran menjadi lebih seperti Indonesia, dan Indonesia belajar menjadi lebih Indonesia lagi, dalam cara kita mengamalkan Islam, yang toleran dan moderat seperti yang kita lakukan di masa lalu!
(Artikel ini dipublikasikan di The Jakarta Post 28 September 2022 dan dipublikasikan kembali berbahasa Indonesia dengan seizin penulis)
(Sumber Gambar: Wikipedia)