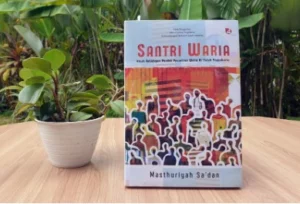“10 Bulan Menikah, perempuan di Jambi Baru Sadar Kalau Suaminya Perempuan”
Seorang perempuan di Jambi, N selama 10 bulan tidak sadar jika ia menikahi seorang perempuan bernama Ahnaf Arrafif.
Kurang lebih begitulah berita yang beredar pada Juni 2022 lalu. Kalau kamu masih ingat, pemberitaan tentang kisah N dan Ahnaf Arrafif ini kemudian ramai di media sosial. Cerita ini ramai ketika diungkap sendiri oleh N di media sosial Twitter.
Suara.com menulis, kepada N, sebelum menikah, Ahnaf mengaku berprofesi sebagai dokter Spesialis Bedah Saraf dan pengusaha batu bara dengan gelar akademis panjang. Keduanya lalu menikah secara siri. Mereka tidak bisa menikah secara negara karena Ahnaf waktu itu tidak membawa KTP. Ahnaf mengatakan karena waktu itu ia sedang dalam proses pergantian nama setelah dirinya menjadi seorang mualaf.
N baru sadar jika Afnaf adalah seorang perempuan ketika 10 bulan pernikahan mereka. Beredar juga foto-foto Ahnaf dengan ekspresi gender feminin setelah itu.
Kasus tersebut kemudian berlanjut di pengadilan, Ahnaf kemudian didakwa dengan pasal pemalsuan gelar akademis yang berujung terungkapnya identitas jenis kelamin resmi yang dia miliki. Ahnaf adalah seorang translaki.
Sejumlah kalangan kemudian mencari keuntungan dari kasus ini, mereka seperti menggoreng isu Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender/ LGBT dengan ekspresi ujaran kebencian yang mereka sebarkan
Berbagai konten dan pemberitaan di media online juga ramai oleh ujaran kebencian yang bertebaran terhadap LGBT di kolom komentar. Sebuah kondisi yang menimbulkan tekanan, terutama bagi translaki.
Sejak itu, semua translaki selalu diasosiasikan sebagai orang seperti Ahnaf. Namun dari kasus Ahnaf kita juga menjadi tahu sulitnya menjadi translaki
Sulitnya Menjadi Translaki
Menjadi translaki seolah adalah sesuatu yang tak boleh dilakukan, mereka ditentukan untuk jadi orang lain. Maka, kasus tersebut memiliki dampak sosial bagi translaki, yaitu menjadikan mereka rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi jika mereka mengakui bahwa mereka adalah laki-laki. Ironisnya, kasus seperti Ahnaf bukan yang pertama kali terjadi di Indonesia.
1.Tahun 2010, publik digemparkan oleh kasus Alter Hofan yang dilaporkan oleh mertuanya dengan pasal pemalsuan identitas.
2.Tahun 2015, Ichal Saser di Polewali Mandar dilaporkan oleh istrinya karena dianggap melakukan penipuan identitas.
3.Tahun 2016, Efendi di Boyolali dilaporkan atas pemalsuan identitas.
4.Tahun 2017, Farel di Tanjung Balai berjuang memperoleh keadilan setelah dilaporkan dengan tuduhan penipuan identitas dan penelantaran anak.
5.Tahun 2018, Ryan di Bandar Lampung dilaporkan atas pemalsuan identitas oleh keluarga istrinya. Ryan menggunakan dokumen palsu untuk menikah dan mengontrak rumah.
Banyaknya kasus gugatan pidana dan dianggap melakukan pemalsuan identitas ini seharusnya membuat komunitas translaki lebih berhati-hati dalam mengubah identitas. Ini jelas bukan sesuatu yang mudah.
Kasus Ahnaf tidak hanya sebagai bahan belajar dan berefleksi, tetapi juga sebagai pengingat bahwa kebutuhan akan identitas legal yang sesuai dengan identitas gender adalah salah satu kebutuhan krusial bagi seorang translaki.
Jalan Panjang Menuju Pengakuan Negara
Itu juga yang terjadi pada diri saya. Sejak memutuskan untuk bertransisi secara medis dan legal untuk mengubah identitas, saya membekali diri dengan berbagai informasi dan pengetahuan terkait translaki di Indonesia. Salah satu tujuan saya adalah perubahan identitas legal.
Sayangnya, di komunitas translaki, tidak ada informasi kredibel yang bisa saya akses. Karena sebagian besar translaki yang sudah melakukan perubahan identitas enggan membagi pengalamannya. Hal ini menjadi jalan buntu bagi kolektif-kolektif translaki yang diharapkan menjadi sumber informasi komunitas.
Yang bisa saya lakukan adalah banyak membaca dan mempelajari putusan-putusan sidang seputar perubahan identitas jenis kelamin dari perempuan menjadi laki-laki. Dari riset sederhana tersebut, saya mendapatkan 3 kesimpulan:
1. Seseorang bisa mengubah identitas jenis kelamin dari perempuan ke laki-laki, jika terbukti memiliki kondisi interseks atau kelainan organ seksual tertentu. Misalnya, kasus Aprilio Perkasa Manganang yang diketahui mengidap hipospadia.
2. Translaki yang sudah melakukan seluruh tindakan operasi penyesuaian gender dapat dikabulkan permohonannya untuk mengubah identitasnya.
3.Translaki bisa dikabulkan permohonannya jika ada justifikasi pendukung yang kuat dari psikiater. Terlepas dari apa saja tindakan medis yang sudah dilakukannya.
Ketiga kesimpulan tersebut berlaku jika seorang translaki ingin merubah identitasnya dengan mekanisme persidangan permohonan perdata, sesuai dengan UU Adminduk.
Dalam aturan acara perdata, dibutuhkan 3 alat bukti yang menguatkan permohonan perubahan identitas jenis kelamin. Pertama, bukti saksi fakta yang bisa dilakukan oleh keluarga atau rekan-rekan terdekat.
Di Indonesia terdapat sebuah norma yang tidak tertulis, yaitu seseorang baru dianggap dewasa setelah ia menikah. Jika belum dewasa, maka dibutuhkan “izin” dari pihak keluarga. Namun, apakah semua keluarga translaki mau menerima keadaan anaknya dan mau bersaksi di pengadilan? Inilah salah satu tantangan yang kerap terjadi pada translaki yang ingin melakukan perubahan nama dan/atau jenis kelamin di pengadilan.
Kedua, bukti dokumen yang menjelaskan seluruh proses medis yang telah dilakukan oleh pemohon. Menurut standar resmi yang berlaku, transisi medis dilakukan dengan serangkaian tahapan, yaitu: konseling dan assessment dari psikiater, rujukan ke androlog atau obgyn untuk terapi hormon, rujukan ke dokter bedah plastik untuk operasi rekonstruksi dada, rujukan ke obgyn untuk pengangkatan rahim dan ovarium, serta rujukan ke dokter bedah plastik untuk operasi rekonstruksi genital. Seluruh dokumentasi dari tahapan-tahapan inilah yang menjadi bukti dokumen. Untuk seorang translaki, transisi medis sendiri membutuhkan biaya puluhan hingga ratusan juta rupiah.
Dengan stigma dan diskriminasi sistemik yang dialami, apakah mungkin setiap translaki di Indonesia memiliki kemampuan finansial untuk menjalani proses tersebut? Transisi medis juga berkaitan dengan hak personal dan ketubuhan. Terlebih jika seseorang memiliki kondisi kesehatan tertentu yang tidak memungkinkan untuk melakukan transisi medis.
Ketiga, bukti ahli. Secara umum, ahli yang dibutuhkan adalah dokter yang menangani langsung transisi medis tersebut. Bisa psikiater, dokter bedah, dan obgyn.
Lantas, bagaimana caranya kita mendapatkan bukti ahli jika tidak melalui proses transisi medis yang resmi? Akses transisi medis pun hanya tersedia di kota-kota besar. Karena mencari tenaga kesehatan yang ramah trans di Indonesia bagai mencari jarum emas di tumpukan jerami. Tidak menutup kemungkinan juga diperlukan ahli agama yang ramah trans sesuai dengan agama masing-masing pemohon, sebagai antisipasi jika hakim menginginkan ahli agama dihadirkan. Inipun bak mencari jarum emas di tumpukan jerami.
Mengingat bahwa isu trans sangat sensitif dan erat hubungannya dengan privasi, bantuan hukum menjadi krusial. Terutama bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum.
Saya pernah mencoba menghubungi 2 lembaga bantuan hukum yang diketahui bekerja sama dengan organisasi dan komunitas LGBT, namun sayangnya, keduanya tidak bersedia memberikan pendampingan yang saya butuhkan. Lembaga pertama tidak menyediakan pendampingan, tetapi hanya dapat memberikan saran strategis.
Mereka hanya akan memberikan pendampingan jika di kemudian hari ditemukan adanya tindakan diskriminatif. Lembaga kedua bahkan menolak memberikan bantuan jika seluruh proses transisi medis belum selesai. Apakah masalah ini dianggap bukan kebutuhan penting bagi komunitas transpria? Apa karena ini permohonan perdata dengan hakim tunggal dan tidak ada penggugatnya?
Maka satu-satunya jalan adalah menggunakan jasa pengacara swasta, tentunya yang ramah trans dan memahami isu SOGIESC (Sexual Orientation, Gender Identity, Gender Expression, and Sex Characteristics).
Meskipun harus merogoh kocek puluhan juta rupiah, hal ini sepadan dengan layanan yang sesuai dengan yang ekspektasi. Mulai dari merencanakan strategi bersama, membuat dan mendiskusikan legal letter, mempersiapkan para saksi, pendampingan di ruang sidang, hingga proses registrasi di Catatan Sipil.
Lagi-lagi, saya beruntung tidak mendapatkan hakim yang transfobik. Proses persidangan berlangsung tertutup untuk umum sebanyak 4 kali. Sidang pertama untuk memberikan bukti dokumen dan pemeriksaan saksi fakta. Sidang kedua untuk pemeriksaan ahli. Sidang ketiga untuk pembacaan kesimpulan yang disusun oleh kuasa hukum. Hingga sidang keempat untuk pembacaan penetapan.
Tok tok tok! Ketukan palu hakim menandakan bahwa negara telah mengakui identitas gender saya sebagai seorang laki-laki. Selanjutnya yang harus saya lakukan adalah melaporkan penetapan tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maksimal 30 hari setelah turunan penetapan diterima. Maka, resmilah perubahan identitas saya.
Panjangnya Pengurusan Identitas: Rentan Jeratan Pidana Hingga Tindak Pemerasan
Transisi medis yang membutuhkan biaya besar, ditambah aksesnya yang sangat terbatas membuat hanya transpria kalangan menengah ke atas yang mampu mengakses perubahan identitas legal. Bagaimana dengan mereka yang tidak memiliki kemampuan finansial? Bagaimana dengan mereka yang tidak memiliki akses pada informasi mengenai mekanisme perubahan identitas? Gap inilah yang membuat kasus-kasus pidana pemalsuan identitas sering terjadi pada transpria.
Di dalam komunitas translaki sendiri terdapat oknum-oknum yang mengajak teman-teman translaki lainnya untuk membuat KTP dengan jalur ilegal. Caranya dengan bekerja sama dengan oknum catatan sipil untuk mencari Nomor Induk Kependudukan/ NIK orang lain yang sudah meninggal atau belum terdaftar di e-KTP. Kemudian, NIK tersebut diganti isinya dengan data pemesan. Biayanya mencapai jutaan rupiah untuk hasil yang diragukan legalitas dan keamanannya.
Ada juga yang membuat KTP palsu dengan menggunakan aplikasi edit gambar dan dicetak sedemikian rupa agar mirip dengan yang asli. Beberapa orang mengaku menempuh jalan ini karena menginginkan proses instan dan lebih terjangkau. Sama saja dengan melakukan pemalsuan identitas.
Menurut Pasal 378 KUHP mengenai penipuan ancaman hukuman pemalsuan identitas bisa dikenakan hukuman maksimal 4 tahun penjara. Sedangkan dengan Pasal 93 UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan diancam dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp 50.000.000,00. Ancaman inilah yang menjerat orang-orang yang memilih jalan seperti Ahnaf dan kasus-kasus serupa.
Lain ceritanya dengan mereka yang menempuh proses persidangan. Joko, salah satu translaki, harus merogoh kocek ratusan juta rupiah untuk biaya pengacara. Pengacara tersebut memberikan jaminan keberhasilan 100% dengan cara “bekerja sama” dengan hakim tertentu untuk memuluskan permohonan Joko. Karena merasa tidak memiliki opsi lain, Joko menyanggupinya.
“Gue nggak tahu mau minta tolong ke mana lagi. Kalau sama organisasi, pasti diarahin ke LBH. Sempat minta tolong sama temen FTM (Female-to-Male), tapi dia malah nipu gue. Gue tanya ke salah satu senior, baru deh dikasih akses ke psikiater di Jakarta. Psikiater itu yang ngasih kontak lawyer. Katanya sih itu lawyer biasa ngurusin FTM,” ujar Joko.
Ia juga menyadari bahwa dirinya tidak memiliki bukti medis yang cukup kuat sebagai alat bukti. Proses yang sudah dilalui Joko adalah konseling psikiater dan terapi hormon. Anggaplah biaya pengacara yang dikeluarkan sebagai penutup kekurangan bukti.
“Gue ngobrol sama nyokap. Mau gue operasi dulu atau ngurus (perubahan identitas) dulu? Nyokap nggak setuju gue operasi. Dia lebih setuju gue ngurus legal. Tapi, kalau mau begitu biayanya nggak kecil dan gue nggak sanggup. Untung nyokap mau bayarin semuanya sampai ID gue beres,” jelasnya.
Joko menginginkan proses persidangan tertutup dan tidak tercium media. Persidangan dilakukan secara online. Tetapi, beberapa bulan setelah sidang Joko menemukan berita tentang persidangannya di media lokal. Untungnya berita tersebut tidak viral seperti kasus Ahnaf saat ini. Selama persidangan hingga identitas barunya diterima, Joko juga kerap dimintai biaya-biaya tambahan di luar perjanjian yang sudah disepakati bersama.
“Di surat perjanjian 100 juta. Di luar itu gue masih dimintain yang lain-lain lagi. Kalau ditotal, hampir 200 juta aja ada,” kata Joko.
Setelah proses persidangan selesai dan seluruh dokumen kependudukan barunya diterima, Joko takut dan enggan berurusan lagi dengan pengacara tersebut. Ia juga bukan orang pertama yang mengalami hal serupa dari pengacara yang sama. Dari kasus Joko kita belajar bahwa tidak semua narasi yang tertulis di turunan penetapan seindah itu kenyataannya. Ketika seorang hakim mengabulkan permohonan transpria, lihat dulu apa yang terjadi di balik layar.
Pengalaman Joko berbeda dengan Bambang. Bambang memiliki bukti dokumen medis yang sangat lengkap beserta ahlinya. Bambang sudah melalui proses konseling, terapi hormon, rekonstruksi dada, dan pengangkatan rahim dan ovarium. Selama persidangan, hakim tidak melontarkan pertanyaan yang menstigma dan cenderung ramah trans. Tapi, sidang penetapan Bambang ditunda selama 3 minggu dengan alasan pandemi.
“Pas gue sampai di PN (Pengadilan Negeri), gue liat lawyer gue keluar dari ruang panitera. Katanya, hakim ada ‘minta’ segini,” ujar Bambang sambil menunjukkan 5 jarinya. “Kalau nggak gue kasih, sidangnya nggak dimulai. Mau gimana lagi? Daripada gue ngulang sidang lagi dari awal. Biaya dan waktunya lebih banyak lagi. Mending gue bayar 5 juta di situ. Uang segitu buat gue nggak banyak, tapi dibilang sedikit juga nggak.”
Benar saja, setelah menyetorkan uang tunai melalui kuasa hukumnya, sidang penetapan Bambang dimulai dan permohonannya dikabulkan.
Sistem peradilan yang transfobik dan minimnya akses bantuan hukum menyebabkan transpria mengalami kekerasan finansial dalam proses perubahan identitasnya. Perlu kita sadari bahwa sosialisasi dan edukasi mengenai UU Adminduk masih sangat kurang. Jangankan untuk merubah identitas jenis kelamin, untuk merubah domisili saja masyarakat masih banyak yang belum memahami prosedurnya.
Perubahan identitas jenis kelamin pada UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diatur dalam Pasal 56 ayat (1) diatur bahwa pencatatan “peristiwa penting” lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan yang dimaksud dengan “peristiwa penting lainnya” dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU Adminduk sebagai berikut:
“Yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.”
Edukasi mengenai UU Adminduk, sanksi pidana, dan kaitannya dengan identitas translaki sangat minim. Informasi seperti ini seperti tak ada yang memberikan, harus mencaro-cari sendiri. Bantuan hukum yang terjangkau pun tidak tersedia. Seolah isu perubahan identitas legal ini belum menjadi prioritas. Padahal, fakta ini ada dan nyata di lapangan. Terlihat dari kasus-kasus yang menjerat translaki yang ada hampir setiap tahunnya.
Masalah ini tidak akan selesai jika masih ada anggapan bahwa isu perubahan identitas legal hanya dimiliki oleh transpria kelas menengah ke atas. Apakah kelas sosial mereka menyebabkan kerentanan identitas mereka berkurang?
“Jujur, gue kecewa. Dianggapnya orang-orang yang kelas menengah ke atas nggak layak dibantu. Kita nggak disupport orang tua tajir kayak Joko. Kalau buat mereka (baca: aktivis transpria) ini nggak penting, belum tentu buat yang lain juga nggak penting,” ujar Bambang.
Merekalah sasaran empuk pemerasan dan kekerasan finansial oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan. Tidak bisa dipungkiri bahwa kebutuhan akan pengakuan identitas legal ini dimiliki oleh setiap lapisan kelas translaki. Butuh kerja keras beberapa tahun bagi saya dan beberapa kawan untuk mewujudkan mimpi kami. Saya dan Bambang tidak terlahir dari keluarga kaya, bahkan kami juga ikut membantu perekonomian keluarga.
Jika gerakan translaki menuntut keadilan, apakah ini akan berhasil? Mereka yang sudah berhasil melakukan perubahan identitas juga membutuhkan ruang aman untuk berbagi. Karena setiap orang memiliki hak atas privasi dan kebutuhan untuk melanjutkan hidup.
Pertanyaannya, apakah ruang-ruang tersebut sudah tersedia dalam kolektif dan organisasi komunitas translaki? Masih banyak individu translaki di luar sana yang membutuhkan informasi terkait perubahan identitas. Mereka yang tidak tahu harus kemana mencari bantuan yang kredibel. Mereka yang tidak terjangkau oleh organisasi komunitas. Mereka yang berani mengambil risiko karena usahanya berujung di jalan buntu.
Lagi-Lagi: Nilai-Nilai Patriarki
Sistem patriarki yang berakar di masyarakat kita mengamini heteronormativitas. Menurut heteronormativitas, seorang yang bervagina sudah pasti perempuan, harus berekspresi feminin, dan tertarik kepada laki-laki berpenis. Begitu juga pada laki-laki. Mereka harus berpenis, maskulin, dan tertarik kepada perempuan bervagina. Mereka yang tidak memenuhi kriteria tersebut akan terpinggirkan.
Otomatis translaki berada di luar kriteria heteronormatif. Stigma, diskriminasi, kekerasan, dan peminggiran sudah menjadi bagian dari kehidupan ketika kami memutuskan untuk melela. Dengan konstruksi sosial seperti itu, translaki kerap kali mengalami kesulitan ketika mengakses layanan publik. Apalagi ketika harus berurusan dengan dokumen kependudukan. Kami harus menyiapkan mental yang prima untuk berhadapan dengan penyedia layanan publik.
“Masnya laki-laki, kok KTP-nya (tertulis) perempuan?”
“Padahal kalau rambutnya panjang cantik lho!”
Kalimat-kalimat semacam itu sudah menjadi makanan sehari-hari bagi translaki. Belum lagi jika harus menghadapi ceramah dadakan dari penyedia layanan. Tidak jarang pula kami dikira berbohong ketika menunjukkan KTP dengan jenis kelamin perempuan.
Tantangan selanjutnya ada pada hubungan romantis. Translaki yang berelasi dengan cis-perempuan kerap dituntut untuk menikahi pasangannya. Karena bagi masyarakat patriarki, seorang perempuan harus cepat-cepat menikah dengan pasangan laki-lakinya.
UU Perkawinan di Indonesia hanya mengakui pernikahan heteroseksual antara laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, identitas jenis kelamin secara hukum harus diubah agar bisa menikah. Pilihannya hanya menikahi pasangan atau mengakhiri hubungan. Desakan ini yang kemudian membuat translaki menempuh jalan berisiko untuk mengubah identitasnya. Di tengah masyarakat yang mengaggap pernikahan sebagai pencapaian hidup, kebutuhan menikah menjadi faktor bagi sebagian besar transpria untuk melakukan perubahan identitas.
“Pacar gue udah tanya melulu kapan kita nikah. Gue juga nggak mau dia nunggu lama-lama. Jadi, gue harus cepat-cepat ngurus (perubahan identitas),” kata Joko.
Setelah menikah, masalah belum selesai. Apa yang terjadi jika ada orang yang mengetahui dan membongkar identitasnya? Jeratan pidana yang akan datang jika ia melakukan pemalsuan identitas, seperti yang sering kita lihat dalam pemberitaan media. Belum lagi sanksi sosial yang diterimanya. Faktor inilah yang membuat sebagian translaki memilih untuk menutup masa lalunya rapat-rapat setelah transisinya selesai. Termasuk dengan cara menjauhi komunitas dan segala sesuatu yang berhubungan dengan translaki. Karena ada privasi diri dan keluarga yang harus dilindungi dari perundungan berbasis transfobia.
Sistem patriarki juga berimbas pada peradilan yang heteronormatif. Seorang trans dianggap melawan kodrat, sehingga tidak layak diberikan status hukum jenis kelamin yang sesuai dengan identitas gendernya. Putusan seperti ini pernah terjadi baik pada translaki maupun transpuan. Di persidangan juga kerap ditanyakan tentang orientasi seksual. Akan aman bagi transpria heteroseksual, karena ketertarikannya sama dengan laki-laki pada umumnya. Tetapi, bagaimana dengan translaki yang memiliki orientasi seksual selain heteroseksual? Ada kemungkinan permohonannya ditolak oleh hakim karena tidak sesuai dengan norma yang berlaku jika mereka berkata jujur.
Sekarang saya tidak perlu lagi ketakutan saat diminta untuk menunjukkan KTP dan identitas diri. Bagian nama dan jenis kelamin menjadi dua baris yang menuliskan perjalanan hidup saya. Sebuah perjalanan untuk menjadi diri sendiri. Tanpa melalui perjalanan itu, saya tidak akan bisa melihat ketidakadilan yang terjadi pada orang-orang seperti saya. Tidak hanya oleh negara dan oknum peradilan, tetapi juga oleh komunitas sendiri. Ketidakadilan ada untuk disadari dan dilawan.
Kasus Ahnaf juga diketahui oleh orang tua saya, “kok bisa terjadi kayak gitu? Emang nggak ada yang ngasih tahu dia kalau itu berbahaya? Kalau ada translaki yang ingin transisi datang ke kamu, ceritakan juga kalau jalan yang kamu ambil ini berisiko tinggi. Jangan hanya cerita manisnya aja!”
Pesan tersebut akan selalu terpatri di benak saya. Mungkin butuh perjuangan puluhan hingga ratusan tahun untuk mengubah negeri ini menjadi lebih inklusif terhadap translaki. Tapi, hidup terus berjalan. Perjuangan kita untuk melawan juga perlu terus dievaluasi.
Ada berbagai cara untuk melawan, baik di garis depan maupun di balik layar. Keduanya adalah pilihan masing-masing individu yang tetap harus dihargai. Mari belajar saling mendengarkan dan memahami agar kasus seperti Ahnaf tidak terjadi lagi di masa depan.