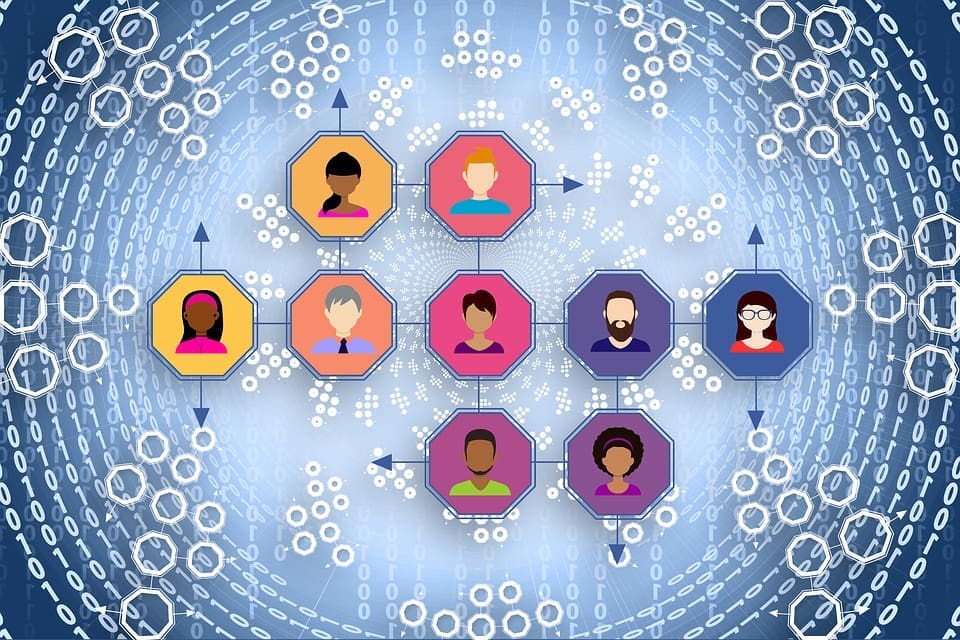Banyaknya kekerasan berbasis gender online yang terjadi di Indonesia mendorong PurpleCode Collective, sebuah kolektif yang berfokus pada isu kekerasan berbasis gender online (KBGO), untuk menggagas penelitian.
Peneliti PurpleCode, Idha Saraswati dalam acara peluncuran hasil penelitian berjudul Rekoleksi Persaudarian: Menamai Kekerasan, Merawat Pemulihan Kolektif, Cerita dari Sembilan Penyintas Kekerasan Berbasis Gender Online Oktober 2022 lalu menyatakan, PurpleCode melakukan penelitian ini yang digagas berdasarkan pengamatan mereka, karena belum adanya temuan yang memadai tentang kekerasan berbasis gender di ranah online di Indonesia dari perspektif para penyintas.
“Kami punya kegelisahan terkait bagaimana sih sebenarnya suara dari penyintas? Apakah para penyintas di Indonesia ini sudah mendapatkan support system yang memadai? Apakah pola dukungan yang ada selama ini sudah mencukupi? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang kemudian mendorong kami untuk melakukan penelitian ini. Jadi secara umum penelitian ini bertujuan untuk menggali apa itu KBGO dan dampaknya dari sudut pandang penyintas,” ujar Idha.
Merujuk pada Catatan Tahunan Komnas Perempuan pada 2020, terdapat 940 kasus kekerasan berbasis siber yang dilaporkan. Jumlah ini meningkat tiga kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Sementara pada 2021 angkanya kembali naik sebesar 83 persen. Jumlah ini bisa jadi jauh lebih besar karena data tersebut berdasarkan pada kasus yang dilaporkan.
Penelitian PurpleCode kemudian menemukan bahwa menyadari adanya kekerasan menjadi titik mula bagi penyintas dalam memahami situasi yang ia hadapi. Namun kesadaran penyintas akan kekerasan tidak muncul serta-merta, melainkan melalui proses panjang dan berliku dan masing-masing orang memiliki rutenya sendiri.
Hal ini tidak terlepas dari lapisan kekerasan yang mereka hadapi karena ada jenis-jenis kekerasan yang bisa langsung disadari. Akan tetapi ada juga kekerasan yang tidak langsung disadari sehingga membuat diri si penyintas makin terkungkung dan sulit keluar dari lingkaran kekerasan itu.
Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kesadaran akan adanya kekerasan itu bukan hanya sekali lalu selesai, tetapi prosesnya naik turun dan jatuh bangun
“Kami menjadi saksi selama penelitian bagaimana rekan-rekan penyintas juga masih berjuang untuk menghadapi trauma yang mereka hadapi.”
Idha menjelaskan, bagi para penyintas, mereka menyadari bahwa kekerasan adalah langkah awal untuk mengatasi persoalan atau dampak yang dialami.
“Kita biasa menyebutnya sebagai coping behaviour. Penelitian ini juga menemukan bahwa upaya mengatasi kekerasan itu bermacam-macam, baik di level personal maupun kolektif. Di level personal dimulai dengan berdialog dengan diri sendiri, menghubungi teman terdekat, mengakses dukungan psikologis maupun legal, dan sebagainya.”
Penyintas sebagai Subyek Penelitian
Untuk itu dalam penelitian ini, Purple Code menggunakan metodologi feminis yang diterjemahkan dalam sejumlah langkah penelitian diantaranya dengan menempatkan para penyintas sebagai rekan penelitian atau subjek penelitian.
“Di dalam praktiknya kami mencoba menerjemahkan prinsip-prinsip tersebut dalam sejumlah langkah antara lain menempatkan para penyintas sebagai rekan penelitian alih-alih sebagai objek penelitian. Dengan demikian rekan penelitian selalu kami mintai pertimbangan di dalam setiap tahap penelitian,” papar Idha.
Selain itu Idha menuturkan, kondisi rekan-rekan penelitian yang merupakan penyintas juga menjadi prioritas sehingga mereka menyediakan akses kepada pendamping bagi para rekan penelitian yang membutuhkan selama proses penelitian.
“Kami juga sejak awal mengingatkan diri kami sendiri bahwa penelitian ini melibatkan rekan-rekan yang mengalami kekerasan. Oleh karena itu kondisi rekan-rekan (penyintas) jauh lebih penting daripada kebutuhan untuk menggali data untuk kepentingan penelitian ini,” kata Idha.
“Selain itu kami juga berupaya menghubungkan rekan-rekan penelitian ini dengan pendamping apabila dibutuhkan selama penelitian,” tambahnya.
Menanggapi metodologi feminis yang digunakan dalam penelitian ini, Dewi Candraningrum, pengajar studi gender, ekofeminisme dan sastra di sejumlah perguruan tinggi mengatakan, riset ini menggunakan metode feminist participatory action research (FPAR) yang di kalangan akademisi belum banyak dipraktikkan.
“(Isu, red) ini ditulis dan diriset karena untuk merawat pemulihan, kan ini berarti ada tindakan atas perubahan sosial yang menjadi ciri utama dari feminist participatory action research. Jadi ada kehendak untuk mengubah persoalan. Yang ini bagi kita kalangan akademisi ‘menjadi sangat langka dan sangat jarang’ untuk kita lakukan,” ujar Dewi dalam acara peluncuran hasil penelitian.
Lebih lanjut Dewi mengungkapkan mempraktikkan feminist participatory action research bukan hal sederhana. Kenapa? Karena ada dua tanggung jawab yang harus kita lakukan. Pertama dokumentasi ilmu pengetahuan.
Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan pengalaman dari para penyintas yang ditulis sendiri oleh penyintas, sehingga ini menjadi poin penting dari penelitian.
Kedua, sebagai peneliti ingin melihat adanya perubahan sosial. Bagi kalangan akademisi riset biasanya dikumpulkan dan kemudian bisa dipakai untuk mempengaruhi kebijakan. Dalam penelitian ini PurpleCode dan para penyintas sudah melangkah lebih jauh karena mereka sadar bahwa ini harus ada perubahan sosial.
Penelitian ini melibatkan 9 penyintas yang berasal dari sejumlah wilayah seperti Jakarta, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Penelitian sebagian besar dilakukan secara daring karena berlangsung selama pandemi yakni mulai 2021 hingga awal 2022. Penelitian ini menggunakan metode dokumen personal dengan meminta para rekan penelitian untuk menulis buku harian dengan pertanyaan panduan. Penulisan buku harian tersebut dipadukan dengan wawancara semi terstruktur.
Sementara upaya kolektif, misalnya dilakukan dengan berbagi kisahnya di dalam forum-forum diskusi dengan tema-tema kekerasan terhadap perempuan serta ikut turun aksi ke jalan terkait dengan isu-isu perempuan. Begitu juga keterlibatan rekan-rekan penyintas di dalam penelitian ini sebenarnya adalah salah satu upaya untuk berbagi kisah dengan harapan agar perempuan yang lain tidak mengalami ataupun merasakan apa yang mereka alami.
“Jadi kekerasan yang mereka alami itu ternyata bisa mendorong munculnya rasa solidaritas kolektif sebagai sesama penyintas,” ujar Idha.
Penelitian ini juga menemukan bahwa, sebenarnya penyintas punya kekuatan yang luar biasa yang itu kerap kali tidak disadari oleh penyintas sendiri maupun oleh pendamping.
“Kita kerap luput bahwa penyintas itu punya kekuatan dan determinasi yang luar biasa untuk kemudian me-manage ataupun bersiasat dengan kekerasan yang dialaminya. Meski jalurnya naik turun dan berliku-liku. Bagi kami penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran tentang situasi yang dihadapi oleh penyintas, lebih dari itu dari penelitian ini kami mengerti bahwa dalam diri setiap penyintas ada semangat untuk bangkit dan bahkan bersolidaritas terhadap sesama perempuan,” pungkasnya.
Tantangan Dalam Proses Pendampingan
Literasi digital dipandang sebagai hal penting dalam upaya pencegahan maupun penanganan KBGO. Sayangnya hal ini belum banyak dilakukan. Pendapat ini disampaikan Tata Yunita, TaskForce KBGO NTT saat dimintai tanggapan terkait temuan penelitian dalam acara peluncuran hasil penelitian tersebut.
Menurut Tata, ketiadaan literasi digital dan upaya untuk menciptakan ruang aman di dunia maya membuat kita melupakan bahaya KBGO. Pengabaian ini pada akhirnya membuat kita ikut mengabaikan penyintas. Untuk itu dalam proses pendampingan penting untuk memberikan literasi terkait keamanan digital.
“Jadi teman-teman (penyintas, red) tidak hanya dikasih support terkait dengan konseling tapi juga ada kebutuhan lain terkait kekerasan yang terjadi secara fisik, juga bantuan hukum maupun bantuan teknologi. Walaupun ada beberapa penyintas yang kayak butuh bantuan teknologi tapi kadang-kadang masih ada rasa trauma untuk menggunakan teknologi tersebut,” jelas Tata.
Hal ini yang membuat Task Force KBGO melakukan kampanye lewat media sosial sebagai teman dari pendampingan. Menurut Tata kita juga perlu menyadarkan orang terkait mengapa kita harus melihat KBGO itu sebagai isu yang penting karena ketidaktahuan akan membuat seseorang atau masyarakat makin mengamini kekerasan yang ada. Dan keengganan untuk menganggap isu ini sebagai hal yang urgen akan membuat sunyi pengalaman penyintas.
Lebih lanjut Tata berpendapat, selain literasi digital, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang pendamping dalam proses pendampingan. Diantaranya seorang pendamping hendaknya menjauhkan diri dari keinginan menjadi hero.
“Kalau dari pengalaman aku pribadi teman-teman penyintas itu kadang-kadang kayak misalnya menghubungi pendamping itu mereka hanya ingin ditemani dan didengarkan tanpa penghakiman. Karena kalau baca hasil penelitian itu ada beberapa rekan peneliti yang bercerita kalau mereka harapannya keluarga itu bisa menjadi lingkaran pertama dalam melakukan support bagi mereka tetapi beberapa itukan malah diabaikan,” papar Tata.
Hal lain adalah menumbuhkan rasa percaya dari teman-teman penyintas terhadap komunitas atau organisasi pendamping. Tata bercerita dirinya pernah dihubungi seseorang dan ditanya soal task force KBGO. Ketika ia menyampaikan kesediaannya untuk membantu, si penelepon justru mengatakan bahwa dirinya hanya mengetes saja bahwa nomor yang dihubungi benar melakukan pendampingan.
“Jadi menurutku ini sebenarnya jadi PR nih bagaimana kemudian penyintas belum punya rasa percaya yang tinggi terhadap (lembaga, red) aduan yang sebenarnya sudah sering wara-wiri di media sosial,” kata Tata.
Tata juga menyoroti proses penyidikan kasus-kasus kekerasan seksual yang selama ini cenderung dilakukan terhadap kasus-kasus yang viral dan mendapat sorotan publik. Hingga kemudian muncul istilah delik viral.
Peran Media Dalam Mengangkat Isu KBGO
Media sesungguhnya punya peran dalam upaya penanganan maupun pencegahan KBGO. Namun tak jarang pemberitaan media belum memperhatikan etika pemberitaan dan perlindungan data pribadi korban.
Aulia adam, editor Magdalene, dalam kesempatan yang sama berpendapat bahwa hal ini tidak terlepas dari posisi jurnalisme di Indonesia sebagai sebuah industri karena pergerakannya didasari oleh kekuatan ekonomi, sosial dan politik. Poin ekonomi ini berperan besar hingga akhirnya berpengaruh terhadap bagaimana sebuah media memberitakan kasus kekerasan seksual.
“Banyak media di Indonesia sebenarnya masih sama seperti industri lainnya, sangat patriarki sangat mengutamakan keuntungan, profit buat medianya. Dan itu akhirnya membuat keputusan-keputusan di dapur redaksi juga bergantung pada dua hal itu,” ujar Adam,
Selain itu menurut Adam representasi perempuan, queer dan disabilitas di newsroom masih sangat minim sehingga berdampak pada produk yang dihasilkan.
“Nggak usah teman-teman queer atau teman-teman disabilitas gitu, representasi teman-teman perempuan sendiri sebenarnya juga masih sangat minim di newsroom-newsroom yang notabene misalnya medianya tercetak sebagai media mainstream gitu, mainstream ini yang followersnya lebih besar yang kekuatan ekonominya lebih besar, ternyata itu juga berdampak pada produk yang dikeluarkan,” papar Adam.
Untuk itu upaya yang perlu didorong agar pemberitaan media berpihak pada korban antara lain dengan memberikan training bagi jurnalis dan editor agar newsroom media memahami soal kekerasan seksual serta bagaimana memberitakannya. Selain itu keberadaan buku panduan liputan kekerasan seksual juga dipandang penting. Sayangnya sejauh ini masih minim.