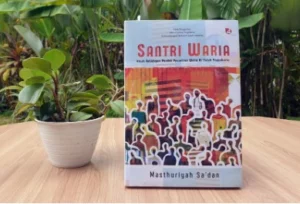Mereka yang melakukan kerja-kerja advokasi dan pembelaan terhadap hak-hak perempuan korban kekerasan ini, tak jarang pula jadi sasaran kekerasan berbasis gender.
Istilah pembela HAM (Human Rights Defender) mulai dikenal secara formal sejak 9 Desember 1998. Para pembela HAM adalah setiap orang mempunyai hak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan yang lain, untuk memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan HAM dan kebebasan dasar di tingkat nasional dan internasional.
Maka dari itu, perempuan pembela HAM ini semestinya juga terjamin perlindungannya. Namun selama ini, tak sedikit justru dari perempuan pembela HAM ini yang mendapatkan banyak serangan.
Ana dari Women Crisis Center (WCC) Jombang mengungkap, sebagai pendamping korban kekerasan dirinya kerap mendapatkan intimidasi baik langsung maupun tak langsung. Tujuannya supaya korban yang dia dampingi tak melanjutkan proses advokasi dan dirinya tak lagi mendampinginya.
“Serangan digital adalah hal yang kerap terjadi kepada kami, seperti penyebaran foto di sosial media, ujaran kebencian, untuk merusak nama baik institusi.” ujar Ana.
Sementara itu, Nona Duwila dari LBH APIK Jayapura menjelaskan, tantangannya saat menjadi pendamping korban kekerasan di Papua. Ia bukan saja harus menghadapi tantangan secara geografis yang sangat sulit dijangkau, namun juga situasi sosial masyarakat setempat. Yaitu, stigmatisasi terhadap petugas pendampingan yang datang karena dianggap bukan bagian dari NKRI. Petugas masih dianggap sebagai pendatang dan mendapat masalah rasial.
Paralegal yang mendampingi korban ini tidak hanya mendapatkan kesulitan akses pelaporan untuk korban, namun juga berbagai ancaman bahkan serangan. Terlebih, jika pelakunya adalah orang berpengaruh atau punya jabatan yang bisa mempunyai power untuk menekan para pendamping di lapangan.
“Sebanyak 4 korban yang pelakunya pejabat, maka kami diancam jika korban meneruskan proses hukum. Rumah saya difoto, syukurlah tetangga saya sangat peduli jadi saya mendiskusikan dengan warga di sekitar bahwa saya sedang menangani suatu kasus, mereka ikut melindungi saya dengan mengawasi orang tidak dikenal yang datang ke wilayah kami,” terangnya.
Mereka menyatakan ini dalam acara diskusi perlindungan para pembela HAM yang diadakan LBH APIK Jakarta pada 29 November 2022 bertepatan dengan Hari Pembela HAM.
Banyak Ancaman, Nihil Perlindungan
Perempuan pembela HAM lainnya, Nihayatul dari LRC KJHAM Semarang, mengaku dirinya pernah dilaporkan atas tuduhan penculikan terhadap korban yang Ia dampingi. Ada ancaman dari pelaku yang menggunakan preman, teman pendamping diikuti oleh preman tersebut sampai pulang ke kosnya.
Di situasi ini, mirisnya Nihayatul bilang, upaya pengamanan bagi pendamping saat ini masih nihil. Padahal, ancaman yang mereka terima itu tak sedikit termasuk di ranah digital.
“Di media sosial juga kami harus mengganti foto, yang tidak ada foto anak-anak dan keluarga kami,” katanya.
Senada, Raden Rara Ayu Hermawati Sasongko dari LBH Apik Semarang juga pernah mendapatkan ancaman di media sosial. Dia bahkan dipukul pelaku bahkan beberapa kali mendapatkan kiriman santet ke kantornya ataupun rumah pribadi.
“Pernah ketika mendampingi kasus KDRT, kendaraan saya ditaburi pasir dan bunga,” ungkap Rara.
Perjuangan para perempuan pembela HAM yang menghadapi tekanan sosial dan stigmatisasi juga dialami oleh aktivis perempuan Sapa Institut Jawa Barat. Di sana paling banyak kasus yang ditangani adalah persoalan buruh migran.
“Stigma buruk pada ibu-ibu desa di komunitas Balai Istri yang menjadi mitra kami. Ibu-ibu kok kerjanya melakukan pertemuan yang membuat perempuan menjadi pembangkang dan tidak nurut suami. Ibu-ibu yang menjadi pendamping ini juga menghadapi ancaman verbal sampai mistis dari pelaku yang tinggal di desa yang sama.” ujar Viny Zulva dari Sapa Institut.
Berkaitan itu, Viny mengatakan pihaknya menerapkan beberapa strategi. Sapa Institut biasanya akan bekerjasama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan Kepala Desa untuk mendapatkan dukungan. Selain itu, juga bermitra dengan lembaga layanan lain dan pemerintah.
Pendekatan seperti itu memang sangat diperlukan. Itu berguna untuk mengikis stigmatisasi dan diskriminasi yang terjadi terhadap pendamping.
Sebab jika tidak, ada pula kasus kehadiran pendamping yang seringkali dicap sebagai ‘provokator’. Perangkat desa pun bisa ikut campur dengan menghalang-halangi saksi untuk tak memberi kesaksian terhadap kasus KDRT. Demi “nama baik” pula, mereka ingin untuk kasusnya diselesaikan di tingkat desa saja tak perlu “orang luar”.
Mirisnya Kondisi Pendamping
Terbatasnya jumlah personil perempuan pembela HAM menghasilkan kondisi beban ganda di pekerjaan, seperti yang dihadapi WCC Jombang, selain tugas utama mendampingi korban kekerasan di semua tingkat proses hukum, mereka juga harus memfasilitasi diskusi, ditambah membuat pelatihan sehingga kerja overload bahkan waktu untuk keluarga dan diri sendiri tidak ada.
Situasi yang sama juga terjadi di LRC KJHAM Semarang, yang tahun ini menangani 70 kasus, jadi satu orang harus bisa mengerjakan sampai 15-20 kasus. Di LBH APIK Semarang, Raden Rara Ayu Hermawati Sasongko mengungkapkan hari Sabtu dan Minggu masih menerima konsultasi hukum, sampai malam melakukan pendampingan di kantor polisi, kami terpaksa menomorduakan kepentingan pribadi.
Husna Amin LBH APIK Jakarta juga menceritakan kewalahannya personil di LBH APIK yang tahun ini menangani lebih dari 1.321 kasus. Terlebih saat ini, LBH APIK juga makin padat dengan semakin besarnya peran: menjadi sumber informasi dan rujukan seluruh Indonesia dan luar negeri bagi para buruh migran.
“Wilayah kerja LBH APIK yang berada di Jakarta Timur namun petugas yang jumlahnya sedikit harus berbagi tugas bekerja mendampingi sampai ke Jakarta Utara yang macet dan cukup jauh. Jam kerja PPHAM bukan nine to five seperti pekerja kantoran, tapi harus siap setiap saat karena kasus kekerasan tidak mengenal waktu,” katanya.
Di situasi itu, perempuan pembela HAM juga masih harus menghadapi beban ganda di ranah domestik. Termasuk, saat beberapa pendamping ada yang memiliki anak balita.
“Saat harus membersamai korban, menghadapi sarana tidak memadai seperti ruang menyusui dan tidak bisa memompa ASI ketika sedang menunggu sidang,” lanjutnya.
Mendesakkan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Keamanan
Negara seharusnya menjamin pendamping memperoleh perlindungan hukum, namun faktanya tidak semua paham akan kebutuhan jaminan pendamping korban. PPHAM tidak bisa dituntut secara hukum, namun belum ada kepastian bahwa pendamping akan bebas dari kriminalisasi atau ancaman akan pidana.
“Belum semua orang peduli dengan keamanan PPHAM, karena tidak dianggap sebagai sebuah pekerjaan hanya kerja-kerja sosial sehingga belum menjadi prioritas,” ujar Nihayatul dari LRC KJHAM.
Ana dari WCC Jombang lantas menyuarakan kemendesakan, agar negara meninjau ulang aturan eksplisit tentang pelanggaran-pelanggaran terkait jaminan kerahasiaan identitas, bahkan kerap dilakukan oleh aparat penegak hukum pada saat pembacaan putusan atau penerbitan surat DPO identitas korban bebas di-share.
Padahal, UU TPKS Pasal 28 dan 29 dikatakan bahwa negara menjamin pendamping berhak mendapatkan perlindungan hukum selama mendampingi korban dan saksi di semua tingkat pemeriksaan.
“Namun sampai saat ini kami yang harus mengatasi sendiri intimidasi yang terjadi,” kata dia.
Tak hanya itu, hak EKOSOB sekarang juga masih memang belum ada jaminan dari pemerintah. Hak EKOSOB ini meliputi hak atas pendidikan, hak atas perumahan, hak atas standar hidup yang layak, hak kesehatan, hak atas lingkungan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya.
“Kami harus mitigasi resikonya, seperti mendaftar mandiri di BPJS ketenagakerjaan,” lanjutnya.
Begitu pula dengan kondisi di LBH APIK Semarang, Terkait gaji tidak dijamin oleh negara, PPHAM tidak dianggap sebagai pekerja sehingga tidak digaji hanya diberi uang pengganti transport. Selain tidak ada gaji, ketika kecelakaan pun harus membayar sendiri.
Yustina Fendrita Lambuina I Protect Now (Indonesia Protection For WHRD Human Rights) mendorong para pihak yaitu pemerintah, swasta, dan lembaga donor mengakui hak sipil dan hak EKOSOB. Ada situasi khusus bagi PPHAM bahwa pada perempuan yang bekerja pada kelompok minoritas agama dan kepercayaan, PPHAM dianggap mengajarkan hal yang sesat.
PPHAM atau paralegal secara profesi belum diakui oleh negara, padahal profesi ini harus dihargai serta dijamin kesejahteraan dan perlindungannya.
Pada PPHAM transpuan, mereka sering dibully saat bekerja mendampingi di kantor polisi. Bagi PPHAM dengan rentang usia muda 20-30 tahun juga sering tidak dipercaya bahwa perempuan tersebut mampu bekerja mendampingi dan masih dianggap anak kecil.
“Harapannya pemerintah, lembaga layanan dan swasta pihak terkait melindungi PPHAM bekerja sama membuat program EKOSOB. Memasukkan perlindungan PPHAM dalam Pergub tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu untuk Perempuan korban Kekerasan misalnya. Harapannya peran negara hadir dalam pemberian perlindungan dan tidak ada diskriminasi terhadap PPHAM,” pungkasnya.