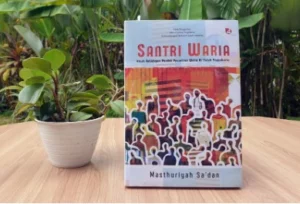Konde.co menghadirkan “The Voice”: Edisi khusus para aktivis perempuan menulis tentang refleksinya. Ini merupakan edisi akhir tahun Konde.co yang ditayangkan 28 Desember 2022- 8 Januari 2023
Izinkan saya membuat disclaimer sebelum kamu membaca tulisan ini. Disclaimer yang menekankan kalau perjuangan menjadi jurnalis–terutama jurnalis perempuan—itu tidak mudah.
Ini bukan soal kemampuan atau keahlian reportase. Bukan juga dalam soal menjaga narasumber, tetap dalam memperjuangkan profesionalisme dan independen. Bukan soal kepasrahan dengan gaji yang minim dan harus bekerja lebih dari 12 jam sehari. Bukan juga soal beban berlipat sebagai perempuan pekerja, istri dan ibu yang harus sesuai ekspektasi masyarakat dan norma.
Sama sekali bukan.
Ini berhubungan dengan upaya perempuan mengimitasi diri menjadi laki-laki demi bisa bertahan di salah satu industri yang cukup maskulin ini. Jadi saat membaca ini, saya menyarankan Anda memakai sepatu para jurnalis perempuan yang kekecilan dan tentu saja empati.
Saya masih ingat saat merintis menjadi jurnalis. Untuk bisa bertahan sebagai wartawan, saya harus melakukan hal yang sama seperti laki-laki. Kondisi diperparah dengan lokasi liputan saya yaitu Aceh dan saat itu konflik sedang parah-parahnya.
Tidur di bawah kolong meja, atau terpaksa pulang tengah malam menjadi santapan saya. Belum lagi kalau harus dicegat aparat bersenjata dan terpaksa tiarap mencium permukaan aspal jalan raya saat mereka memeriksa kartu identitas di dalam kegelapan malam.
Kalau sudah begitu salah satu aparat bersenjata akan bertanya, “Kenapa sih perempuan mau jadi jurnalis dan pulang larut malam? Kenapa tidak jadi ASN, guru atau mengurus anak saja?”
Buat banyak orang, pekerjaan perempuan sebagai jurnalis–terutama di Aceh dan saat konflik—memang bukan pekerjaan yang “normal” dan cenderung nyeleneh. Harusnya saya sudah berada di rumah, di mana dianggap tempat yang paling aman untuk perempuan seperti saya. Bukan kelayapan di jalan dan jadi sasaran razia aparat bersenjata.
Padahal rumah juga bukan jaminan menjadi tempat aman, terbukti kekerasan terhadap perempuan juga terjadi di rumah.
Pertanyaan kenapa menjadi jurnalis hanya karena gender itu juga jadi favorit orang-orang terdekat. Keluarga, tetangga, bahkan teman-teman saya juga mempertanyakan keputusan saya. Semula saya mencoba menjelaskan, namun belakangan saya lelah sendiri.
Saya berpendapat, kalau saya tidak pernah mengusik orang dengan pilihannya, jadi kenapa saya harus menjelaskan pilihan saya?
Banyak jurnalis perempuan yang tidak sadar kalau harus mengimitasi laki-laki demi bisa bertahan di newsroom yang kejam. Mereka menganggap adalah hal yang biasa dan “normal”. Jurnalis perempuan mungkin lebih suka menggunakan kata “adaptasi” dengan kondisi newsroom.
Belum lagi ada semacam candaan, “Katanya mau setara dengan laki-laki, ya tugas dan kewajibannya harus sama dong.”
Padahal jelas-jelas saja konsep kesetaraan bukan berarti sama rasa sama rata, melainkan ada pertimbangan lain seperti privilese dan kesempatan yang selama ini tidak masuk hitungan ketika membicarakan kesetaraan gender.
Anyway, saya memang jatuh cinta pada profesi ini. Sama seperti orang yang jatuh cinta, pendapat atau pandangan orang itu bukanlah hal yang penting. Dan cinta saya pada profesi ini abadi, terbukti saya bisa bertahan hingga 22 tahun tanpa terusik sedikit pun dengan stigma yang disangkutkan.
Diskriminasi di Newsroom Itu Bukan Mitos
Riset kecil-kecilan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan PR2Media pertengahan tahun 2022 ini memberi titik lebih terang kalau jurnalis perempuan bukan hanya harus “beradaptasi” tetapi juga mengalami diskriminasi di newsroom. Jadi adanya diskriminasi ini bukan mitos semata.
Riset itu melibatkan 405 jurnalis perempuan seluruh Indonesia selama satu bulan. Dari jumlah itu 16,8 persen jurnalis perempuan mengatakan mereka mengalami diskriminasi dalam hal remunerasi termasuk gaji pokok, tunjangan dan bonus dibanding rekan mereka yang lelaki.
Selain remunerasi lebih kecil, riset juga menemukan kalau 29,6 persen jurnalis perempuan mengalami diskriminasi dalam tugas peliputan. Jurnalis perempuan hanya ditugaskan di topik atau tugas-tugas peliputan yang secara tradisional itu dianggap wilayah perempuan misalnya isu domestik, hiburan dan keluarga.
Jurnalis perempuan juga menghadapi pekerjaan ekstra tanpa adanya insentif, dan adanya eksploitasi tubuh jurnalis perempuan oleh redaksi supaya mendapatkan wawancara dengan narasumber tertentu.
Masih ada newsroom yang “tega” menjadikan jurnalis perempuan sebagai umpan demi bisa mendapatkan narasumber penting, atau bahkan menempatkan jurnalis perempuan di lembaga yang kebanyakan narasumbernya adalah lelaki seperti kepolisian atau militer.
Jurnalis perempuan juga enggan mengambil cuti haid yang jadi hak mereka karena khawatir dianggap “lemah” dan tidak produktif.
Epiknya lagi, riset ini menemukan diskriminasi juga terjadi antara jurnalis perempuan itu sendiri yaitu antara jurnalis yang sudah berkeluarga dan yang masih lajang. Jurnalis perempuan yang lajang konon tidak mendapatkan akses untuk kesehatan reproduksi. Padahal jurnalis perempuan yang belum berkeluarga juga bisa mengalami masalah dengan organ reproduksi.
Sementara itu jurnalis perempuan kini juga sedang dihantui kekhawatiran untuk dirumahkan manajemen media. Riset menunjukkan masih ada stereotip peran perempuan yang bukan bread maker alias pencari nafkah. Hal ini menyebabkan jurnalis perempuan menjadi sasaran “empuk” untuk dirumahkan terlebih dahulu dibanding jurnalis laki-laki yang dianggap pencari nafkah utama keluarga. Belum lagi bila jurnalis perempuan itu sudah menikah karena dianggap memiliki suami yang bisa menafkahkan.
Temuan riset itu semakin menguatkan pendapat saya kalau belum ada perubahan signifikan terhadap jurnalis perempuan di newsroom, bahkan sejak saya memulai karier 22 tahun lalu.
Pelecehan dan Kekerasan Seksual Masih Masif
Saya pernah ditelepon oleh salah satu jurnalis perempuan yang curhat kalau dia menjadi korban kekerasan seksual. Ada narasumber yang menjamah payudaranya saat sesi wawancara one on one.
Narasumber ini bukan orang biasa melainkan cukup prominen. Wajahnya sering muncul di media dan pernyataannya cukup nge-lead.
Saya yang mendengarkan jelas jengkel dan ingin membawa kasus itu ke polisi. Namun sambil menangis jurnalis itu minta kasusnya tidak diperpanjang dan dijadikan “asal Mbak tahu saja”.
Dia memohon saya mendengarkan kesedihannya tanpa harus berpikir solusi, apalagi mencari keadilan untuk dia.
“Saya takut Mbak. Bagaimana kalau orang tahu? Suami saya pasti marah. Saya takut,” katanya.
Dia bahkan tidak berminat melaporkan narasumber itu ke editor atau pemimpin redaksi di newsroom.
“Tidak ada gunanya. Pasti laporan saya tidak ditanggapi,” katanya terisak.
Jurnalis perempuan itu hanya satu dari banyak jurnalis perempuan yang mengalami pelecehan ataupun kekerasan seksual saat menunaikan tugasnya.
Riset terakhir yang dilakukan AJI dan PR2Media pada akhir tahun 2022 menemukan kalau masih banyak jurnalis perempuan yang mengalami kekerasan seksual. Dari 852 jurnalis perempuan di 34 provinsi di Indonesia, sebanyak 82,6 persen (704 responden) pernah mengalami kekerasan seksual sepanjang karier jurnalistik mereka.
Pelaku juga sangat random dan bisa siapa saja. Temuan yang menurut saya pribadi sangat mengerikan dan menambah kerentanan jurnalis perempuan dalam melakukan tugas kejurnalistikannya.
Apalagi kenyataan kalau tidak semua media sudah punya kesadaran melindungi jurnalisnya dari kekerasan seksual. Alih-alih memberikan keadilan untuk para korban. Memang hingga saat ini banyak media yang belum mempunyai mekanisme atau Standard of Procedure (SOP) pencegahan dan penyelesaian kasus kekerasan seksual.
Tidak dipungkiri kalau ada media yang memiliki SOP penyelesaian kasus kekerasan pada jurnalisnya. Sayangnya kekerasan seksual dimasukkan dalam kekerasan biasa. Padahal kekerasan jenis ini harus dipisahkan dan mendapatkan perhatian khusus. Apalagi tidak memiliki cara penyelesaian yang sama, kadang lebih kompleks ketika melibatkan relasi kuasa.
Kendati demikian, saya meyakini kalau semua media punya keinginan sama yaitu mencegah dan menyelesaikan kekerasan seksual di tempat mereka. Saya bahkan yakin Dewan Pers, dan organisasi profesi jurnalis lainnya juga segendang penarian untuk hal ini.
AJI sendiri sudah memiliki SOP pencegahan dan penyelesaian kasus Kekerasan Seksual sejak awal tahun 2022. SOP itu melindungi 1.800 anggotanya dari kekerasan seksual, selain juga meningkatkan kesadaran lewat kampanye dan edukasi.
Diskriminasi dan kekerasan terhadap jurnalis perempuan memang masih terjadi dan akan menjadi pekerjaan rumah bukan saja untuk media, tetapi juga Dewan Pers, organisasi profesi, pemerintah dan organisasi masyarakat sipil.
Media merupakan pilar penting demokrasi yang mengutamakan hak asasi, kebebasan berekspresi dan tentu saja mendidik publik dengan konten media terpercaya dan bisa diandalkan.
Namun bagaimana jurnalis perempuan bisa melakukan tugasnya jika mereka masih dihantui ketidakadilan, stigma, diskriminasi dan kekerasan? Ibaratnya, mereka memakai sepatu yang kekecilan, sehingga sulit berjalan dalam melakukan peliputan. Sepatu juga terlalu kecil untuk menyimpan potensi yang bisa lebih besar.
Sebagai jurnalis perempuan, saya berharap bisa berganti sepatu yang kekecilan itu dengan sepatu yang cocok dan pas. Kami juga ingin bergerak lebih leluasa demi melayani kepentingan umum. Termasuk leluasa menjadi diri sendiri.
Semoga tahun 2023 adalah tahun yang lebih ramah untuk kami.