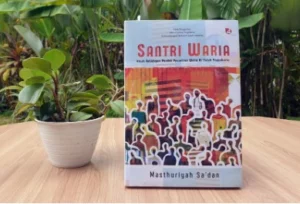Pelecehan seksual merupakan tindakan berupa pelayangan ungkapan atau ujaran yang mengandung seksisme dan sugestif serta tidak dikehendaki penerimanya.
Setidaknya ada tiga argumentatif suatu tingkah laku digolongkan sebagai tindak pelecehan seksual, yaitu legalitas, perilaku, dan situasional.
Konstruksi sosial patriarki yang memandang kedudukan perempuan inferior dibandingkan laki-laki, telah menempatkan perempuan sebagai pihak yang paling riskan untuk mendapat pelecehan seksual. Praktik-praktik tersebut digencarkan dalam balutan gurauan berkonotasi seksis dan semakin dinormalisasikan oleh masyarakat, terutama laki-laki.
Subordinasi Perempuan dalam Framing Media
Normalisasi pelecehan seksual terhadap perempuan di media-media daring banyak diakibatkan adanya dominasi perusahaan media untuk membingkai berita (framing) dengan menyudutkan posisi perempuan. Hal tersebut yang melatarbelakangi berkembangnya stigma negatif masyarakat pada perempuan yang mengalami pelecehan ataupun kekerasan seksual.
Berita di media massa yang saya catat sejak tahun 1993 kerap melanggengkan penulisan pemberitaan terkait pelecehan dan kekerasan seksual dengan asumsi perempuan sebagai provokator, sehingga ketika menulis terjadinya pemerkosaan, pelecehan, dan kekerasan seksual selalu menyalahkan perempuan.
Sementara pelaku hanya diasumsikan hilang akal, khilaf, ataupun terprovokasi baik dari cara berpakaian maupun tingkah laku perempuan. Kemudian, kasus tersebut diasumsikan kembali sebagai “hubungan yang sama-sama ingin.”
Lihat saja beberapa diksi dalam judul berikut:
“Berontak saat Hendak Digagahi, Mahasiswa Asing Gigit Lidah Driver Hingga Nyaris Putus”
“Mahasiswi Digilir 3 Pria di Kamar Kos”
“Cerita Mahasiswa Berprestasi Dipaksa Melayani Hawa Nafsu Dosen”
Penggunaan diksi seperti “digagahi”, “digilir”, dan “melayani hawa nafsu” telah melemahkan perempuan serta mendistorsi realitas yang terjadi. Tumpulnya empati dalam maskulinitas jurnalisme mengakibatkan dipandang remehnya isu-isu yang melibatkan kekerasan pada perempuan. Diksi bias dilayangkan untuk “memperhalus” perbuatan pelaku, tanpa menyelam jauh pada perspektif penyintas kekerasan. Media seharusnya tidak menjauhkan realitas dengan penggunaan diksi yang cenderung menormalisasikan perbuatan pelaku.
Pergeseran Perspektif Pemberitaan di Media
Saat ini saya selanjutnya mencatat, pergeseran fokus pemberitaan di media daring secara perlahan memperlihatkan adanya upaya untuk melakukan opresi pada pelaku dan memberikan ruang pada penyintas kekerasan seksual.
Liputan pemberitaan mengenai pelecehan seksual memantik media untuk mengkonstruksi cara pengemasan berita itu sendiri. Tercatat telah terjadi perubahan narasi serta pengimplentasian perspektif episodik dari tahun ke tahun. Penggunaan diksi media kemudian mulai menunjukkan adanya positioning pada perspektif penyintas kekerasan.
Walaupun masih ditemukan pula beberapa media pengejar clickbait yaitu tetap menyalahkan perempuan sebagai penyintas dengan menyematkan diksi bias dan menjatuhkan, namun media juga memiliki peranan yang besar dalam mengawasi kasus serta melindungi penyintas dari stigma.
Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi resmi disahkan, memunculkan keberanian penyintas dari beberapa nama universitas untuk mengambil hak dan keadilan pasca traumatik dilecehkan. Penegakan hukum terhadap pelecehan seksual kian disuarakan dan mampu menjerat pelaku dengan pasal terkait. Namun meskipun demikian, peraturan yang ada belum cukup memoderasi praktik-praktik pelecehan seksual dalam lingkup institusi pendidikan.
Media kemudian membantu pembentukan realitas ini, yaitu membantu korban untuk berani bicara.
Realitas memperlihatkan ruang pendidikan dalam praktiknya telah dinodai sederet kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang melibatkan pendidik sebagai pelaku. Komnas Perempuan melampirkan data yang menunjukkan bahwa perempuan tidak lepas dari marginalisasi dan subordinasi gender di tempat yang seharusnya ia terayomi. Data tersebut menyebutkan sejak tahun 2017 sampai 2021, setidaknya terdapat 66 laporan kekerasan seksual yang terjadi di berbagai jenjang pendidikan.
Dalam kurun lima tahun, perguruan tinggi menempati posisi tertinggi terjadinya pelecehan seksual, yakni sebanyak 35 kasus. Dibuntuti rentetan kasus lainnya, seperti di pesantren sebanyak 16 kasus dan di lingkup SMA 15 kasus. Data tersebut tidak menyatakan jumlah kasus pada realitas secara keseluruhan akibat minimnya pelaporan kepada Komnas Perempuan ataupun pihak yang berwenang.
Laporan Rentan Dikriminalisasi
Seksisme serta diskriminasi berbasis gender menyelusup bebas dalam parsial institusi pendidikan. Pembungkaman tindak asusila yang dilakukan pendidik sering kali membuat penyintas enggan untuk melaporkan. Masih menjamurnya budaya victim blaming mulai dari cara berpakaian hingga tindakan pada saat dilecehkan, mengopresif penyintas untuk tidak menjemput suara keadilan di meja hijau. Rentannya pengakuan penyintas untuk dikriminalisasi kepolisian, secara implisit mendukung pelecehan seksual berfluktuatif dari tahun ke tahun tanpa dipayungi hukum yang sesuai. Karetnya Pasal UU ITE, melonggarkan viktimisasi sekunder (secondary victimization) atau viktimisasi berlipat (multiple victimization) untuk terus bergulir dalam kasus pelecehan di ranah kampus.
Kesadaran sivitas akademika terhadap isu pelecehan seksual yang terjadi dalam kampus serta peranan media massa berperan penting untuk membangun birokrasi ramah gender.
Maraknya persoalan pelecehan seksual serta lemahnya substansi perlindungan hukum perlu dikaji guna menciptakan kampus bebas kekerasan seksual. Media massa sebagai pemberi pengaruh paling besar opini publik sudah seharusnya bersinergi dengan institusi pendidikan pada saat memuat pemberitaan pelecehan seksual. Terlebih lagi di era digitalisasi ini, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia/ APJII menyebutkan Indonesia sudah mengalami peningkatan melek internet sejak pandemi.
Hal itu menandakan media mengambil andil besar untuk menaungi kesaksian korban dan mengawal kasus hingga akhir.