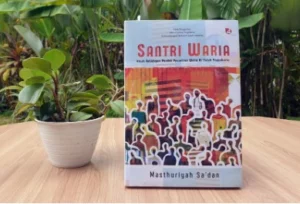Hampir setahun lalu, tonggak untuk mewujudkan dunia tanpa kekerasan seksual telah ditandai dengan lahirnya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) pada 12 April 2022. Undang-undang tersebut tentu bukanlah akhir perjuangan. Sebaliknya, barulah awal.
Masyarakat sipil dan media massa tentunya mesti mengawal implementasi undang-undang tersebut, meminta komitmen berbagai pihak, terutama pemerintah dan penegak hukum untuk menangani kekerasan seksual yang lebih berorientasi pada korban.
Dalam kondisi ideal, media dipercaya memainkan peran utama mendukung perjuangan masyarakat dalam melawan kekerasan terhadap perempuan, termasuk dari kekerasan seksual. Media dapat meningkatkan kesadaran publik dalam isu tersebut, sekaligus mengontrol berbagai pihak untuk memastikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual.
Namun media masih memiliki kompleksitas masalah untuk menjalankan perannya itu, bahkan turut berkontribusi dalam melanggengkan kekerasan pada perempuan. Ada dua dimensi untuk melihat masalah itu di dunia media: segi pemberitaan dan kultur organisasi media.
Pertama, pemberitaan media tentang kekerasan seksual selama ini telah lama dikritik. Penelitian Komnas Perempuan (2015) terhadap sembilan media massa di Indonesia, menemukan pemberitaan media yang masih mengungkap identitas korban kekerasan seksual, penggunaan diksi yang bias, dan stigmatisasi terhadap korban sebagai pemicu kekerasan seksual.
Meskipun sejak 2019, liputan-liputan berkualitas dan mendobrak soal kekerasan seksual makin sering dilakukan seperti Nama Baik Kampus, Tiga Anak Saya Diperkosa, Saya Lapor ke Polisi. Polisi Menghentikan Penyelidikan, Kekerasan Seksual Pegawai Kementerian: Korban Diperkosa dan Dipaksa Menikahi Pelaku, namun tak sedikit laporan media yang masih bermasalah.
Pada 2022, AJI Indonesia pernah mengkritik salah satu media yang menampilkan foto profil penyintas kekerasan seksual, serta menuliskan secara detail kronologi kekerasan tanpa konfirmasi dan persetujuan dari penyintas. Bahkan pemakaian diksi yang bias seperti “menggagahi” masih jamak ditemukan pada judul media online seperti dimuat oleh Viva, Tribunnews, dan JPNN. Atau diksi “digilir yang digunakan oleh Okezone, Liputan6, dan Kompas.com.
Penggunaan diksi yang bias tersebut tak hanya mengaburkan tindak kekerasan seksual, melainkan makin memperkuat budaya patriarki yang mengobjektifikasi korban, menormalisasi kekerasan seksual di masyarakat, dan menjadikan korban seksual sebagai korban berikutnya karena ketidakadilan media.
Selain bias-bias tersebut, media kerap memberitakan kekerasan seksual hanya permukaan atau sebatas “peristiwa”, utamanya saat korban atau pendampingnya melapor ke polisi. Selebihnya, bagaimana korban berjuang mencari keadilan, menghadapi dampak psikis, sosial, dan ekonominya, kerap lewat dari jepretan media.
Berbagai masalah itu adalah saling berkaitan karena faktor model bisnis media dengan mendulang klik, rendahnya pengetahuan soal jurnalisme berperspektif gender, dan kuatnya budaya patriarki yang mendominasi media massa. Pemberitaan media yang bias soal kekerasan seksual sejatinya adalah representasi dari budaya patriarki, yang telah melalui proses seleksi dalam kerja-kerja jurnalistik dan berkelindan mengejar kepentingan ekonomi.
Kedua, lingkungan media belum menjadi tempat yang aman bagi jurnalis perempuan dari kekerasan seksual. Hasil survei terbaru AJI Indonesia bersama Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media) terhadap 852 jurnalis perempuan, mengungkap sebagian besar yakni 704 responden (82,6 persen) menerima kekerasan seksual di sepanjang karir jurnalistik mereka. Jenis kekerasan yang dialami terjadi dalam berbagai bentuk, di ranah online maupun offline.
Pelaku kekerasan tersebut datang dari atasan di tempat kerja (3,4 persen), rekan kerja (15,7 persen), narasumber berita (12,8 persen) dan anonim (24,7 persen). Hal mengejutkan lainnya dari temuan survei itu, mayoritas atau 60,9 persen jurnalis perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, tidak menerima bantuan atau dukungan dari media tempatnya bekerja.
Tidak adanya sistem dukungan dari organisasi media tersebut, membuat sebagian besar para penyintas hanya menceritakan masalahnya itu pada teman atau rekan kerjanya (29,9 persen) atau memilih diam saja (16,1 persen). Kebanyakan para penyintas akhirnya menghadapi kasus dan dampaknya sendirian yang dapat berakibat pada keberlanjutan ekonomi dan gangguan kesehatan mental dalam jangka panjang.
Tak hanya itu, kekerasan seksual juga menjadi hambatan serius bagi perempuan jurnalis untuk berkarir di dunia jurnalisme, di samping masih banyaknya diskriminasi soal remunerasi, asuransi kesehatan, cuti haid, dan cuti melahirkan, sebagaimana hasil riset AJI Indonesia dan PR2Media soal “Diskriminasi Gender di Organisasi Media” pada 2022.
Dengan demikian kita menemukan keterhubungan bagaimana kuatnya budaya patriarki di dalam organisasi media telah menormalisasi kekerasan seksual di internal dan pada akhirnya mempengaruhi bias pada pemberitaan.
Media dan UU TPKS
Media semestinya bisa menjadikan lahirnya UU TPKS sebagai momen untuk meningkatkan komitmennya dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual. Bukan hanya karena kekerasan seksual berada dalam situasi darurat di Indonesia, tapi lebih jauh untuk mewujudkan masyarakat yang lebih setara, terutama bagi perempuan dan minoritas gender lainnya.
Di situasi saat ini, setidaknya media memiliki dua tanggung jawab sekaligus setelah UU TPKS disahkan.
Pertama, media harus menggunakan UU TPKS sebagai momen untuk memproduksi liputan berkualitas mengenai isu kekerasan seksual. Melalui pengaturan di UU TPKS, media setidaknya memiliki pedoman bagaimana meliput isu kekerasan seksual secara holistik dan berperspektif korban.
Secara substansi, UU TPKS memuat tentang aspek pencegahan, tindak pidana kekerasan seksual, hak korban atas perlindungan, penanganan dan pemulihan. Pengaturan di dalamnya menjadi landasan bagi media untuk memastikan bagaimana tanggung jawab dari negara, aparat penegak hukum, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk mencegah, menangani, melindungi, memulihkan dan memastikan kekerasan seksual tak berulang.
Dengan kompleksitas isu tersebut, pengelola media harus memberikan peningkatan kapasitas kepada jurnalis dan redaksinya bagaimana memproduksi liputan tentang kekerasan seksual. Peningkatan kapasitas bisa melibatkan berbagai jaringan organisasi masyarakat sipil dan jurnalis senior lainnya sebagai pemateri. Dengan cara ini, munculnya pemberitaan yang diskriminatif bisa dihindari.
Dewan Pers dan Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dapat membantu media dengan membuat pedoman liputan, menyelenggarakan training, dan diskusi berkala tentang isu kekerasan seksual. Layanan seperti ini perlu disediakan oleh lembaga negara, mengingat tidak seluruh organisasi media memiliki sumber daya yang memadai untuk menyelenggarakan peningkatan kapasitas bagi internalnya.
Memang ada tantangan baru bagi media untuk memberitakan isu kekerasan seksual. Serangan balik terhadap media dan jurnalis setelah mempublikasikan laporan soal kekerasan seksual makin marak. Penyerangnya datang dari pelaku maupun pihak-pihak otoritas yang terkait dengan kasus kekerasan seksual tersebut.
Ambil contoh apa yang dialami oleh Project Multatuli setelah menerbitkan karya berjudul Tiga Anak Saya Diperkosa, Saya Lapor ke Polisi. Polisi Menghentikan Penyelidikan pada 2021. Polisi melabeli karya tersebut sebagai hoaks dan situs Project Multatuli mendapat serangan distributed denial of service (DDoS) hingga karya tersebut sulit diakses publik. Serangan kembali datang ke Project Multatuli, setelah menulis kasus kekerasan seksual oleh Muhammad Subchi Azal Tsani, anak pemimpin pesantren Shiddiqiyyah di Jombang pada November 2022. Pendiri Project Multatuli Evi Mariani di-doxing dan mendapat komentar bernada melecehkan.
Konde.co juga mendapat serangan DDoS setelah menurunkan liputan berjudul Kekerasan Seksual Pegawai Kementerian: Korban Diperkosa dan Dipaksa Menikahi Pelaku pada 24 Oktober 2022.
Di sisi lain, Pers mahasiswa juga jauh lebih rentan mendapatkan serangan, seperti yang dialami oleh LPM Lintas IAIN Ambon setelah menerbitkan laporan khusus berjudul IAIN Ambon Rawan Pelecehan pada 2022. Serangan yang berlapis dari rektorat dan terduga pelaku mereka dapatkan, mulai dari persekusi, pembredelan, dan upaya pemidanaan.
Melihat tren serangan ke media tersebut setelah mengungkap kasus kekerasan seksual, membutuhkan keseriusan negara untuk melindungi kerja-kerja jurnalistik sebagaimana mandat UU Pers. Keseriusan itu harus ditunjukkan dengan penegakan hukum untuk mengungkap pelaku-pelaku serangan digital kepada media dan jurnalis.
Dewan Pers perlu membangun mekanisme perlindungan yang lebih holistik agar dapat merespon berbagai tren serangan baru itu. Termasuk untuk pers mahasiswa dengan membuat surat edaran kepada seluruh perguruan tinggi agar melindungi aktivitas pers mahasiswa sebagai bagian kebebasan berekspresi yang dilindungi Konstitusi.
Kedua, organisasi media juga memiliki tanggung jawab yang sama dengan seluruh pihak lainnya untuk mengimplementasikan UU TPKS, utamanya tindakan untuk mencegah, melindungi, menangani dan memulihkan jika ada jurnalisnya yang menjadi korban kekerasan seksual. Tindakan itu bisa dimulai dengan membuat standar operasional procedure (SOP) di dalam organisasi media berisi mekanisme rinci untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual.
SOP itu tidak boleh berhenti di atas kertas, tapi harus dilatihkan kepada seluruh pekerja media di dalam organisasi media. Diikuti dengan menyediakan layanan pengaduan yang menjamin kerahasiaan korban, tim khusus untuk menangani laporan, prosedur yang transparan untuk memproses kasus, layanan pemulihan psikis, hingga pendampingan ke proses hukum.
Untuk membantu organisasi media, AJI Indonesia dan PR2Media telah membuat panduan SOP bagi perusahaan pers untuk mengatasi kekerasan seksual di dunia kerja. Pembuatan dan implementasi SOP tersebut dapat meminta dukungan dari berbagai organisasi masyarakat sipil yang saat ini telah memiliki layanan untuk menangani kekerasan seksual.
Selain soal tanggung jawab normatif, pada akhirnya perusahaan media sendiri yang akan memetik benefit dari berbagai mekanisme perlindungan yang dibuat bagi jurnalisnya dari kekerasan seksual.
Dengan meningkatnya rasa aman, maka seluruh pekerja media, termasuk jurnalis perempuan akan makin produktif bekerja, secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini akan mendorong seluruh tim akan mendukung produksi liputan yang berkualitas dan berperspektif gender. Dengan sendirinya kepercayaan publik pada media tersebut akan meningkat.