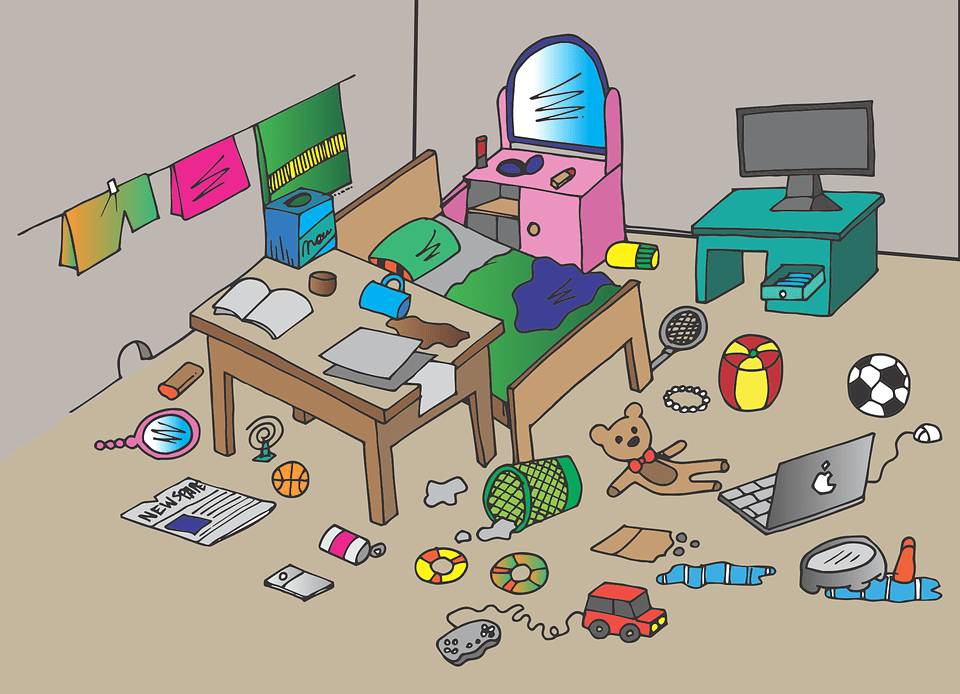Stereotipe terhadap pemimpin perempuan adalah salah satu yang menghambat kepemimpinan perempuan. Lihat saja beberapa komentar yang sering ditujukan pada pekerja perempuan:
“Perempuan tidak bisa lembur”
“Perempuan rentan emosinya sehingga tidak bisa mengemban beban kerja tinggi”
“Ah, kamu perempuan ngapain daftar di sini. Gak pulang sebulan. Nanti suamimu selingkuh.”
Pandangan-pandangan inilah yang menjadi penghambat bagi perempuan untuk bisa meraih posisi pimpinan.
Indonesia mengalami krisis kepemimpinan perempuan yang begitu kentara. Para perempuan di berbagai sektor, termasuk tenaga kerja masih minim menempati posisi strategis. Stereotype adalah salah satu hal yang harus dipecahkan, dibuang dan disingkarkan karena mitos-mitos ini sering menghambat perempuan untuk jadi pemimpin
Dari data yang dikumpulkan, Indonesia hingga kini, bisa dikatakan masih jauh dikatakan berhasil dalam mencapai keadilan dan kesetaraan gender. Setidaknya ada dua indikator yang mendasari, yaitu akibat rendahnya keberhasilan dalam pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan masih tingginya kesenjangan terhadap perempuan yang terjadi.
Data United Nations Development Programme (UNDP) tahun 2020, Indonesia menempati peringkat 121 dari 189 negara terkait Gender Inequality Index. Selain itu, Data World Economic Forum tahun 2021 pun memperlihatkan bahwa Indonesia berada di peringkat 101 dari 156 negara dalam Global Gender Gap Index.
Krisis Kepemimpinan Perempuan yang Sangat Kentara
Satu hal yang jadi catatan, negara ini mengalami krisis kepemimpinan perempuan yang begitu kentara. Para perempuan di berbagai sektor termasuk tenaga kerja masih minim yang menempati posisi strategis.
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 menunjukkan, hanya ada 30,63% perempuan yang berhasil menduduki posisi primer dalam bidang tenaga kerja, sedangkan 69,37% lainnya didominasi laki-laki.
Hasil penelitian Cakra Wikara Indonesia (CWI) yang berjudul ‘Menyoal Data Representasi Perempuan di Lima Ranah’ juga menguatkan, hanya sebanyak 20,05% perempuan yang menjabat eselon I dan eselon 2 (kategori Jabatan Pimpinan Tinggi atau JPT) dari total 2.554 aparatur sipil.
Minimnya perempuan yang menempati jabatan tinggi ini pun, tentu bisa jadi berdampak besar lahirnya kebijakan yang adil gender. Sebab jabatan struktural bisa mencerminkan kewenangan dalam merancang program, menyusun anggaran, hingga mengimplementasikan kebijakan (CWI, 2022).
Di bidang pendidikan, ketimpangan perempuan sebagai pemimpin jabatan juga terjadi. Data menunjukkan, kepala sekolah perempuan di Sekolah Dasar (SD) Indonesia hanya sepertiganya yang perempuan dan madrasah bahkan kurang dari 20% (Dewi, 2021). Padahal, dari sekitar 1,4 juta guru SD, hampir 1 jutanya adalah perempuan atau hampir 70% (Kemendikbud Ristek, 2020).
Bicara soal sedikitnya perempuan yang ada di posisi pemimpin di ranah pendidikan, apakah perempuan memang kurang berkualitas? Tidak juga! Sebuah hasil riset INOVASI (2018) menunjukkan, kepala sekolah perempuan justru lebih baik dalam beberapa aspek manajemen sekolah (Arsendy, Sukoco dan Purba, 2020).
Tak hanya di ranah tenaga kerja dan pendidikan, di ranah politik perempuan juga masih terpinggirkan. Walaupun sudah ada kebijakan afirmasi yang mendorong terpenuhinya kuota 30% perempuan di DPR RI, tapi kenyataannya sampai saat ini perempuan di DPR hanya sekitar 20,25%. Di tingkat lokal baik DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota pun serupa. Dari 34 provinsi, hanya ada 1 provinsi yang anggota DPRD nya melebihi 30% kuota perempuan yaitu Kalimantan Tengah.
Serupa mirisnya, pada tingkat DPRD Kabupaten/kota dari 458 daerah di Indonesia, hanya ada sebanyak 8 kabupaten/kota yang telah memenuhi kuota 30% perempuan, yaitu Kabupaten Gowa (42%), Kota Tomohon (40%), Kota Depok (34%), Kota Madiun (33%), Kota Kendari (33%), Kota Batu (32%), Kota Surabaya (30%), dan Kota Probolinggo (30%).
Hambatan Tak Kasat Mata
Di tengah masyarakat yang masih begitu kental dengan nilai patriarki, perempuan mengalami banyak hambatan. Termasuk hambatan yang tak kasat mata atau efek langit-langit (glass ceiling effect) yang menjadi penghalang mereka untuk berkarir lebih tinggi.
Aparatur Sipil Negara/ ASN perempuan misalnya, mengalami hambatan tak kasat mata pada beban ganda. ASN perempuan masih banyak yang dituntut berkarier sekaligus menanggung beban rumah tangga. Tentu saja ini begitu sangat menyulitkan, dibandingkan laki-laki yang banyak diuntungkan karena bisa fokus mengejar karir setinggi-tingginya (CWI, 2022).
Perempuan aparatur sipil tadi, juga masih harus mengalami hambatan struktural dalam pola kenaikan jabatan. Hasil penelitian dari CWI (2022) menunjukan, ada pola yang khas jika ingin naik ke posisi yang lebih tinggi, yaitu jalur promosi harus dilakukan dengan mutasi ke daerah pinggiran Indonesia, baru kemudian akan dilanjutkan dengan mutasi ke kota-kota besar, dan diakhiri dengan kembali ke Jakarta dengan jabatan yang lebih tinggi.
Pola promosi jabatan seperti ini sulit diikuti oleh perempuan yang menanggung beban ganda karena mereka mesti juga memikirkan untuk turut memindahkan keluarga, termasuk di antaranya mencari tempat tinggal dan sekolah untuk anak-anaknya. Terlebih lagi, jika mereka tidak mendapat izin dari pasangan mereka, akan sulit bagi ASN perempuan untuk mengikuti pola promosi dengan mutasi ke daerah. Karenanya, tidak heran jika ASN perempuan enggan dipromosikan ke jabatan lebih tinggi.
Selanjutnya, hambatan mengikuti pendidikan lanjut untuk kenaikan jabatan. Menempuh pendidikan lanjutan merupakan hal strategis untuk menaikkan pangkat, sehingga ASN tersebut memiliki kualifikasi lebih tinggi untuk bersaing meraih jabatan. Hasil penelitian dari CWI (2022) menemukan salah satu informan yang bercerita bahwa ia tidak jadi sekolah S2 ke luar negeri karena tidak mendapat izin dari suami.
Berbagai hambatan tak kasat mata ini, tentu saja tidak hanya dialami oleh ASN perempuan. Tapi, seluruh pekerja perempuan di Indonesia. Dalam bidang politik pun, partai politik yang setengah hati dalam memasukan perempuan pada daftar kandidat juga menjadi persoalan utama. Hal ini, tak lepas dari akar permasalahan terletak pada adanya budaya patriarki, yaitu perilaku yang mengutamakan laki-laki daripada perempuan dalam masyarakat atau kelompok sosial.
Lalu, apa yang bisa dilakukan? Guna menghapus budaya patriarki sehingga terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ini, memang perlu rasanya mendorong DPR RI sebagai pembuat kebijakan untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG) walaupun perjuangan ini masih sangat jauh.
RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender, sempat menjadi pembahasan di tingkat pemerintah dan DPR pada tahun 2015 – 2016, namun kembali terhenti. RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender sangat strategis untuk menghapuskan berbagai bentuk diskriminasi, stigmatisasi, labelisasi maupun kekerasan terhadap perempuan karena pembedaan perannya di dalam keluarga dan masyarakat. RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender juga merupakan komitmen pemerintah dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dimana target 5.1, Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan, dapat dicapai jika terjadi peningkatan kebijakan yang responsif gender dan mendukung pemberdayaan perempuan
Pelan tapi pasti, secara sistemik budaya patriarki diharapkan bisa memudar dengan sendirinya. Di masyarakat, kemudian terbentuk pemahaman dimana perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki, termasuk dalam pengisian jabatan pimpinan.
Melalui Undang-Undang ini, diharapkan pula mendorong adanya payung hukum yang lebih tinggi dari Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, sehingga PUG dapat berjalan lebih optimal.