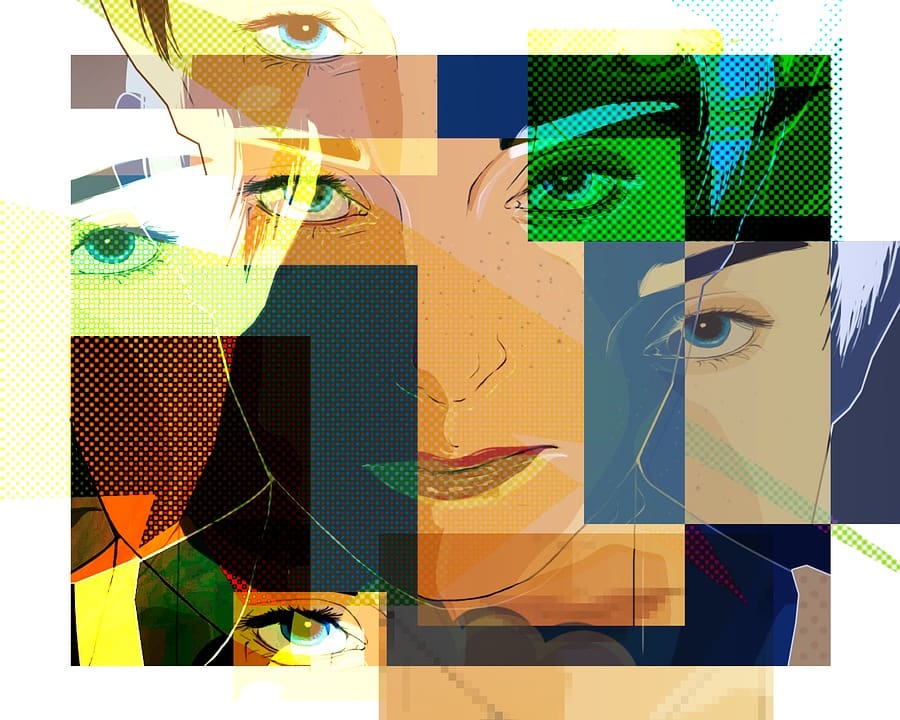Ini adalah cerita tentang perempuan bernama Yati dengan 13 belas
anaknya. Tak bisa menyekolahkan anaknya adalah kepedihan mendalam yang
dialami Yati. Tapi apa mau dikata. Menjadi miskin bukan pilihan
hidupnya.
*Kustiah- www.Konde.co
Ketika terdiam, ada sebuah pertanyaan yang sering membuat saya gelisah setelah memikirkannya: apa yang sudah saya lakukan untuk orang lain yang membutuhkan sesuatu?
Pertanyaan sederhana, tetapi saya begitu sulit menjawabnya.
Kali ini adalah soal keinginan anak-anak yang ingin sekolah. Sebut saja namanya Dandi (bukan nama sebenarnya). Usianya 6 tahun. Dandi setiap hari mengemis di sekitar jalan perumahan tak jauh dari Stasiun Cilebut, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Wajah Dandi tak asing.
Bagi para penikmat kuliner di sekitar jalan stasiun menuju jalan perumahan atau para pejalan kaki yang kerap melewati jalan menuju stasiun, akan selalu menemukan Dandi bersama keenam saudaranya yang sama-sama mengemis atau meminta-minta.
Wajah mereka hampir mirip, masing-masing usianya hanya terpaut sekitar setahun hingga tiga tahunan.
Adik Dandi yang paling kecil E (3 tahun), B (4), S (5), lalu Dandi, kemudian kakaknya Al (8), As (14). Enam saudara sekandung ini kadang mengemis dengan memecah menjadi tiga kelompok.
Dandi biasanya mengemis bersama adiknya, B. Al akan menggandeng adiknya yang paling kecil, E. Sementara S dan As berpencar mengemis seorang diri.
Dandi masih punya lima kakak yang setiap harinya mengamen dan memulung. Dan dua kakak tinggal di Bandung bersama neneknya. Jadi, Dandi punya 13 bersaudara. 11bersaudara tinggal bersama kedua orang tuanya, sementara dua saudaranya terpisah tinggal bersama nenek, ibu dari bapaknya.
Kata Dandi, kakak-kakaknya yang besar pun dulu ketika kecil mengemis. Karena sudah besar mereka malu dan sekarang memilih mengamen dan memulung.
Awalnya saya sempat meragukan cerita Dandi saat mengatakan memiliki 13 saudara kandung yang mengemis, mengamen, dan memulung.
Lalu, awal Mei lalu saya menawarkan diri mengantar pulang Dandi dari mengemis untuk tahu rumah dan keluarganya. Bersama anak sulung saya yang berusia 5 tahun, pukul delapan malam saya membonceng Dandi dan anak saya menuju rumah Dandi. Dan saya merasa sangat bersalah saat Dandi meminta saya menghentikan motor tepat di seberang perumahan Griya Asri, Batugede, Cilebut, Bogor.
Dia menunjuk “rumahnya” yang berada di tengah kebun. Jarak jalan beraspal yang sudah banyak lubang dengan rumah Dandi sekitar 70 meter. Tak ada penerangan, kecuali di rumah Dandi yang terlihat terang. Beruntung malam itu Dandi membawa alat penerangan senter. Dengan sigap ia mengeluarkan senter kecil dari sakunya.
“Saya bawa ini (menunjukkan senter) supaya ibu bisa jalan,” ujarnya kepada saya.
Dan Dandi membimbing saya bersama anak saya yang tampak kesusahan mencari pijakan karena jalan setapak kanan kirinya dipenuhi rumput tebal dan licin.
Malam itu usai gerimis. Dandi berkali-kali memperingatkan saya supaya hati-hati. Mendekati rumah Dandi berteriak memanggil ibu dan bapaknya, memberitahu kalau ia membawa tamu.
Sampai di rumah, tepatnya gubuk yang beralas plastik, kertas kardus, berdinding kain, plastik, dan beratap plastik dan terpal, ibu dan saudara-saudaranya keluar dari gubuk. Satu persatu mereka menyalami kami.
Seorang perempuan memperkenalkan diri sebagai ibu Dandi bernama Yati, 40 tahun. Duduk di atas gelaran kardus Yati menunggui cucunya yang berumur 8 bulan dan anak bungsunya, E (3).
Ayah Dandi, Dadang (62) duduk di sudut gubuk sedang memakan rebusan mi setengah matang sambil memegangi pipi karena sakit gigi. Ia tampak memeriksa televisi. Dadang punya keahlian memperbaiki televisi yang rusak. Tak jarang ia mendapat pesanan untuk memperbaiki televisi rusak milik tetangganya.
Di luar gubuk dua kakak Dandi, As (14) dan Yadi (19) terlihat sibuk memperbaiki ‘betor’, becak motor yang biasa dipakai untuk mengantar beserta kakak dan adiknya mengemis di Cilebut.
Jarak rumah Dandi yang ada di Batu Gede dengan Jalan Stasiun Cilebut sekitar 7 kilometer. Dua bulan ini mereka senang karena memiliki motor yang dimodifikasi dengan kotak yang mirip keranjang di sebelah kiri motor untuk mengangkut Dandi bersama saudara-saudaranya.
Meski hanya memiliki motor rombeng yang mereka sebut betor, mereka senang karena tak lagi mengeluarkan ongkos banyak untuk naik angkot. Sebelum ada betor mereka harus jalan kaki sekitar 200 meter dari gubuknya ke Jalan Raya Batugede untuk naik angkot menuju Cilebut.
Dari mengemis jika sedang ramai biasanya Dandi dan adik-adiknya masing-masing membawa pulang Rp 20 ribu setiap malam. Namun, jika sepi satu orang mendapat tak sampai Rp 10 ribu.
Malam itu kakaknya meninggalkan Dandi dan kedua saudaranya mengemis di Cilebut karena harus mengambil rongsokan di Bojong Gede, Bogor. Jika kakaknya tak menjemput Dandi dan sudara-saudaranya naik angkot.
Akhir Mei, di tengah terik matahari saya kembali ke rumah Dandi. Siang itu Yati tampak sibuk membersihkan gelas air minum bekas untuk dijual ke pengepul. Mengenakan kaos singlet, duduk di depan gubuk Yati membeset tutup plastik yang menempel di gelas. Karena di gubuknya penuh dengan anak-anaknya yang besar dia mempersilakan saya untuk berteduh di rumah petak yang ia sewa tepat di belakang gubuknya. Tampak anak-anak Yati berbaring tertidur di lantai tanpa alas karpet atau tikar. Saya masuk ke rumah kos dengan mengendap kuatir mengganggu tidur siang anak-anak. Tetapi tak berhasil. Karena, Dandi bersama saudara-saudaranya terbangun kecuali si bungsu, E (3) yang tidurnya terlihat gelisah sambil sesekali menggaruk mukanya yang penuh luka gatal kemerahan di sekitar hidung, dagu, dan pipinya.
“Mereka (anak-anak Yati yang besar) puasa. Lemas semalam mencari rongsok dan baru pulang tadi pagi,” ujar Yati.
Yati menyewa rumah petak supaya bisa menggunakan fasilitas air dan kakus. Juga karena ia punya anak-anak kecil yang perlu tinggal di tempat yang lebih baik dibanding di gubuk atau dia menyebutnya bedeng. Ia menyewa Rp 400 ribu setiap bulan. Kondisi di dalam rumah petaknya sebenarnya tak layak untuk disebut sebagai tempat tinggal. Ruangannya pengap, sempit, dan sangat kumuh. Bedeng dengan rumah petak dipisahkan sebuah got yang bau airnya menyengat dan pembuangan sampah tempat warga sekitar membuang sampah.
Bedeng yang ditempati Yati bersama suami dan anak-anaknya berada di kebun kosong milik warga. Ia mengaku sudah meminta ijin kepada si empunya dan bersedia angkat kaki jika ladang dibangun.
Yati mengatakan, penghasilannya bersama suami dan anak-anaknya dari mengemis, mengamen, dan memulung hanya cukup untuk makan sehari-hari, membayar sewa rumah petak, dan membiayai pesantren dua anaknya yang tinggal di pesantren tak jauh dari rumah neneknya di Bandung.
Anaknya yang sekolah dan tinggal di pesantren selalu meminta Rp 500 ribu setiap bulan untuk biaya hidup dan biaya sekolah. Sehingga dia dan suaminya mengaku kesulitan jika menyekolahkan anak-anaknya yang lain.
Dari ketiga belas anaknya, hanya dua anaknya yang mencecap bangku sekolahan. Lainnya paling tinggi ikut sekolah di sekolah masjid terminal atau yang tenar dengan nama sekolah Master Depok, itu pun hanya sampai kelas 3 sekolah dasar. Sisanya mengemis, mengamen, dan memulung.
Perempuan kelahiran Bogor yang mengaku tak pernah mencecap bangku sekolahan ini menikah di usia 17 tahun. Sementara usia suaminya saat menikah sekitar 40 an tahun.
Pertama menikah hingga saat ini Yati maupun suaminya tak menggunakan alat kontrasepsi untuk membatasi jarak kelahiran anaknya. Juga tak pernah berniat menggunakan kontrasepsi sesuai pesan almarhum ibunya ketika masih hidup. Tak ayal jika ketiga belas anaknya jarak kelahirannya hanya berjarak sekitar satu hingga tiga tahun.
Melihat kesulitan hidup yang cukup pelik saya bertanya kepada Yati, apakah dia atau suaminya pernah didatangi pengurus rukun tetangga (RT) atau rukun warga (RW) atau pegawai kelurahan?
Yati menggeleng. Ia, suami, dan anak-anaknya yang berusia di atas 18 tahun tak memiliki kartu identitas kependudukan apalagi surat akta kelahiran anak. Yati atau suaminya juga tak pernah berusaha mencoba membuat atau mengurus kartu tanda penduduk. Alasannya macam-macam mulai karena ia bukan warga Bojonggede hingga karena Yati maupun suaminya tak sempat.
Ia mengatakan, dalam hidup ia hanya berprinsip tak mau menyusahkan orang lain. Itu pula yang ia ajarkan kepada anak-anaknya. Ia dan suaminya tak bisa menyekolahkan anak-anaknya karena keterbatasan biaya juga tidak memiliki akses informasi.
“Jujur saja, saya tak bisa menyekoahkan anak-anak. Karena mereka banyak. Kalau satu sekolah semuanya pasti akan ribut (minta sekolah). Saya tak sanggup,” ujarnya kepada saya.
Saya terdiam. Melihat kehidupan Yati bersama keluarganya membuat saya berpikir, bahwa seseorang menjadi miskin bukan karena mereka tak bekerja keras. Bukan karena mereka malas. Kurang keras apa mereka bekerja?
Lantas, pertanyaan “Kapan kami bisa sekolah bu?” membuyarkan lamunan. Wajah Dandi beserta kakak dan adik-adiknya berkelindan di pelupuk mata.
(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)
*Kustiah, mantan jurnalis Detik.com, kini menjadi penulis di www.Konde.co