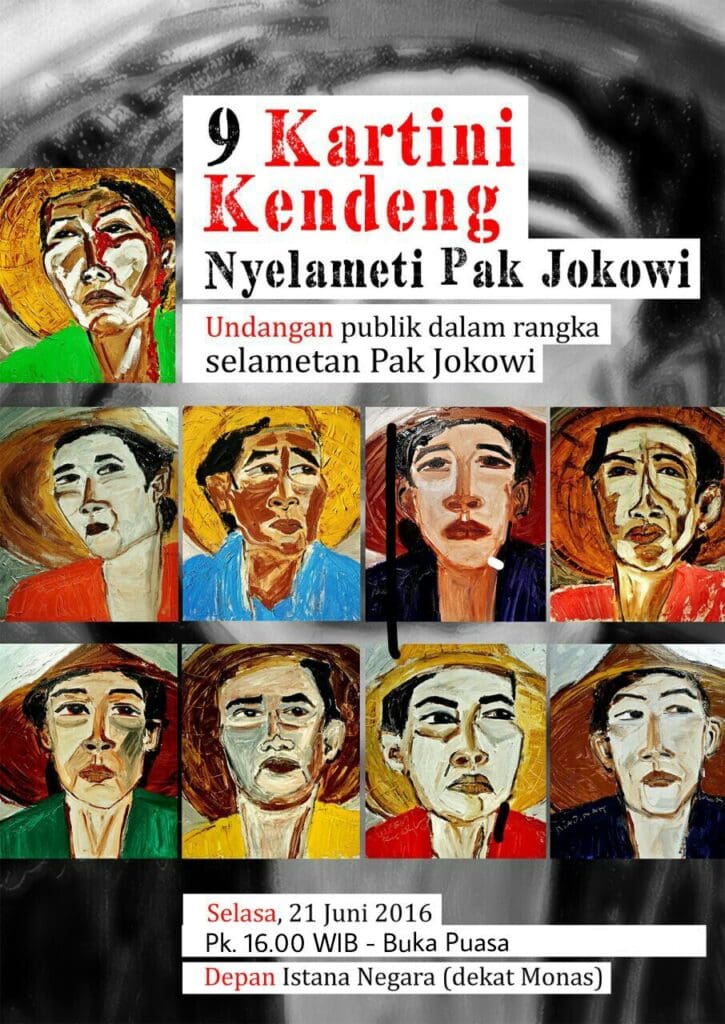*Aprelia Amanda- www.Konde.co
Jakarta, Konde.co- Muhammad Muchlisin bercerita tentang masa kecilnya. Masa kecil yang dihabiskan di Pati, sebuah kota kecil yang terletak di Jawa Tengah. Ia senang bermain volly sampai sore.
Namun ketika pulang ke rumah, ia dimarahi kakeknya. Kakeknya tiba-tiba mengatakan bahwa penampilan Muchlisin seperti orang Cina hanya karena ia sedang memakai celana pendek. Dalam bayangannya waktu itu ia hanya menangkap bahwa kebiasaan orang Cina memakai celana pendek.
Suatu ketika Muchlisin pergi ke masjid untuk solat magrib. Karena warga di daerahnya semuanya orang islam dan mayoritas orang Nahdatul Ulama (NU) maka mereka punya tradisi menggunakan sarung ketika datang ke masjid. Muchlisin waktu itu datang ke masjid menggunakan celana lalu ditegur oleh ustad. Ustad itu bilang Muchlisin seperti orang Muhamadiyah karena menggunakan celana ke masjid, bukannya sarung. Muchlisin kecil tidak mengerti itu semua, dia hanya mengganggap kalau yang baik itu berarti yang menanggunakan celana panjang dan menggunakan sarung ke masjid.
Teguran itu terus diingatnya sampai ia dewasa. Ketika Muclisin datang ke Jakarta ia mengalami culture shock. Ia bertemu etnis Tionghoa dan Muhammadiyah yang kesemuanya membuatnya takut. Ia takut melakukan kesalahan karena teguran yang dulu. Ia juga merasa takut untuk menyapa.
Kemudian untuk menghilangkan ketakutannya, ia mengikuti program pemuda lintas agama, di sana akhirnya ia sadar bahwa pemahamannya selama ini ternyata salah.
Berbekal pengalaman masa kecilnya itu, Muchlisin kemudian berinisiatif mendirikan yayasan Cahaya Guru. Yayasan ini didirikan untuk sekolah para guru tentang kebhinekaan. Sekolah ini ia dirikan agar para guru mengetahui soal kebhinekaan karena ini penting dalam mengajari, mendidik para siswanya. Guru-guru ini kemudian dilatih untuk memberi pemahaman tentang keragaman kepada siswa-siswanya, sehingga anak-anak akan memahami perbedaan dengan pandangan yang luas bukan dengan stigma.
Muchlisin mengatakan hal ini pada peringatan hari Pemuda Internasioal, Youth Advisory Panel UNFPA & UNFPA Indonesia di Jakarta pada 18 Agustus 2019. Tahun ini acara ini mengabil tema tranformasi pendidikan yang berfokus pada kesetaraan, keadilan, dan pendidikan inklusif bagi semua orang. Transformasi pendidikan harus dilakukan agar tercipta pembangunan yang berkelanjutan.
Acara ini menghadirkan empat narasumber yaitu Kanzha Vina dari Sanggar Swara, Muhammad Muchlisin dari Yayasan Cahaya Guru, Chintia Octenta seorang aktifis disabilitas, dan Robin Siinurat pendiri MimpiBesar.id. Mereka membagi cerita tentang perjuangan untuk membangun pendidikan yang layak bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain.
Pendidikan dan informasi ternyata merupakan hal penting yang sering dilupakan orang. Jika mendapatkan pendidikan yang baik, maka ini bisa mengubah ekonomi seseorang. Tak hanya itu, pendidikan juga akan mengubah cara pandang orang, mengubah perilaku orang lain dan memberikan perspektif baru soal informasi.
Khanza Vina seorang transgender perempuan memberikan fakta kehidupan para transgender yang ada di Indonesia. Transgender khususnya transgender perempuan sulit sekali mendapat pekerjaan. Sejumlah hal yang menyebabkan ini karena banyak transgender yang tidak bisa meraih pendidikan tinggi. Penyebabnya? Ketika mereka sekolah, mereka sangat sering dibully, ini yang menyebabkan transgender harus keluar dari sekolah. Padahal pendidikan merupakan hak semua orang untuk mendapatkannya. Namun karena tidak mendapatkan ruang yang layak untuk belajar, maka para transgender seperti terbuang nasibnya dari sekolah.
Pekerjaan yang bisa dilakukan transgender adalah menjadi pekerja salon, pengamen dan menjadi pekerja seks. Kehidupan mereka selalu dalam kondisi tidak aman karena sering mengalami bullying dan persekusi. Maka pendidikan merupakan salah satu cara agar orang bisa menghormati orang lain.
Menurut Khanza Vina, persoalan pendidikan adalah persoalan genting di Indonesia. Karena sejauh ini pendidikan di Indonesia belum memberi pemahaman tentang keragaman gender sehingga orang-orang yang dianggap berbeda menjadi sasaran empuk kekerasan. Kelompok Lesbian, Gay Biseksual dan Transgender atau LGBT dianggap penyakit dan menyimpang sehingga selalu terus menerus didorong untuk “kembali ke jalan yang benar”. Padahal kondisi seksual seperti ini bukanlah penyakit sehingga tidak perlu disembuhkan.
“Pendidikan yang diajarkan sekolah saat ini pun hanya mencakup soal kesehatan alat konprehensif di dalam kurikulum, pemerintah menolaknya. Mereka terlalu takut dengan hal-hal yang ada kata seks didalamnya.”
Robinson Sunurat berasal Dusun Tiga Sindoro, Sumatra Barat. Sebagai anak desa ia punya mimpi untuk sekolah di tempat yang bagus namun impinnya itu tidak terwujud karena orang tuanya tidak punya biaya.
Ketika ia diterima di Universitas Sriwijaya, Palembang namun orang tuanya tidak mampu untuk membiayai. Namun tekad besarnya itu akhirnya mampu membawanya tetap bisa sekolah disana. Di Palembang ia harus berhemat, akhirnya ia memutuskan untuk makan sehari satu kali dan ketika lapat di tengah malam ia hanya makan biskuit sambil menangis.
Robinson merupakan anak yang berprestasi, banyak penghargaan yang ia peroleh selama kuliah. Setelah lulus ia ke Jakarta untuk bekerja. Selama bekerja di Jakarta ia punya mimpi untuk sekolah di luar negeri. Ia akhirnya mendapat beasiswa di Columbia University. Seorang anak desa yang berasal dari keluarga sederhana akhirnya mampu mewujudkan mempinya untuk sekolah setinggi mungkin.
Setelah kembali ke Indonesia ia membangun sebuah platform MimpiBesar.id. Platform ini didedikasikan untuk semua orang yang memiliki mimpi besar seperti dirinya. Hal ini karena sekolah menjadi tak mudah bagi orang miskin, tak punya akses layak untuk melanjutkan jenjang yang lebih tinggi.
Anak-anak muda yang hadir disini menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia harus melakukan transformasi, sebab pendidikan yang ada saat ini belum menjangkau pemahaman tentang keadilan, kesetaraan, dan inklusifitas. Peran pemuda sangat diperlukan untuk mengubah wajah pendidikan yang ada saat ini.
“Pemuda harus menyuarakan kebutuhannya akan pendidikan yang lebih melek dengan realitas sosial yang ada sehingga agent of change tidak hanya sebuah jargon
*Aprelia Amanda, biasa dipanggil Manda. Menyelesaikan studi Ilmu Politik di IISIP Jakarta tahun 2019. Pernah aktif menjadi penulis di Majalah Anak (Malfora) dan kabarburuh.com. Suka membaca dan minum kopi, Manda kini menjadi penulis dan pengelola www.Konde.co