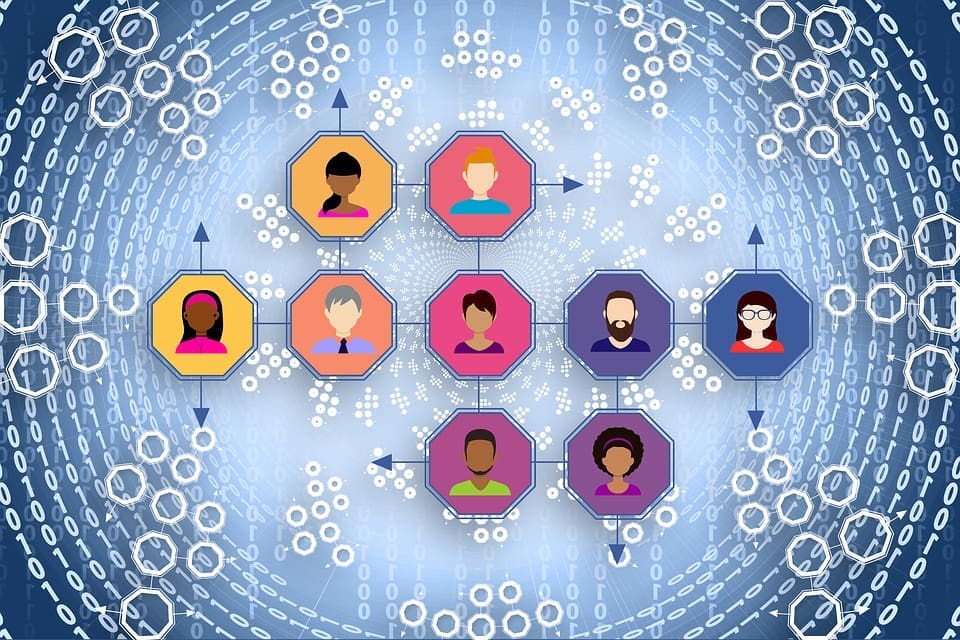Kehamilan yang tidak diinginkan akibat perkosaan atau inses merupakan jenis kehamilan yang diperbolehkan oleh hukum untuk diaborsi. Pengaturan aborsi bagi korban perkosaan pun sudah cukup lengkap mulai dari Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi hingga Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi.
SPEKHAM, lembaga pengada layanan bagi korban kekerasan yang berbasis di Kota Surakarta (Solo) mencatat sepanjang 2021 menerima aduan sebanyak 78 kasus, 12 diantaranya merupakan kasus kekerasan seksual, dengan 3 korban mengalami kehamilan.
Sementara PPT Provinsi Jawa Tengah sepanjang Januari hingga Agustus 2022 menerima aduan perkosaan sebanyak 13 kasus, 10 diantaranya terjadi pada anak dengan 1 anak mengalami kehamilan dan 3 kasus terjadi pada orang dewasa dengan 2 orang mengalami kehamilan. Pada periode yang sama P2TP2A/PTPAS Kota Surakarta menerima 3 aduan perkosaan dan semua korban mengalami kehamilan.
Di Jakarta LBH APIK Jakarta, lembaga bantuan hukum yang berbasis di Jabodetabek mencatat sepanjang 2021 menerima aduan kasus sebanyak 1.321 kasus. Dari jumlah tersebut sebanyak 48 kasus merupakan kekerasan seksual terhadap anak dan 66 kasus kekerasan seksual dewasa, termasuk di dalamnya perkosaan. Beberapa diantaranya korban mengalami kehamilan.
Direktur SPEKHAM, Rahayu Purwa menuturkan situasi ini tentu saja bukan tanpa masalah. Karena minimnya informasi, korban yang melaporkan kasus kekerasannya dan mengalami kehamilan tidak ada satupun yang mengetahui adanya akses aborsi aman buat mereka. Sementara pendamping juga sangat berhati-hati dalam memberikan pilihan untuk terminasi kehamilan karena adanya pengalaman kriminalisasi terhadap pendamping. Selain itu aborsi juga masih dianggap sebagai isu yang sangat sensitif.
Korban Perkosaan Menghadapi Hambatan Struktural dan Kultural
Meskipun UU Kesehatan sudah lebih dari satu dekade disahkan, tetapi kebijakan tentang aborsi tidak dipahami oleh masyarakat umum bahkan oleh aparat penegak hukum. Rahayu menuturkan banyak orang tidak tahu dan tidak cukup terinformasi oleh kebijakan ini. Ia melihat kondisi ini berbeda dengan yang terjadi pada UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).
“Tidak seperti UU PKDRT (yang setelah disahkan–red) kemudian disosialisasikan secara luas kepada masyarakat umum sehingga kemudian orang sudah sangat paham bahwa pada saat mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga ya mereka tahu ada UU PKDRT. Tetapi tidak dengan kebijakan ini. Saya rasa masyarakat masih sangat minim mendapatkan informasi tentang ini,” tutur Rahayu.
Di kalangan pendamping korban situasinya tidak jauh berbeda. Penyedia layanan kesehatan baik pemerintah (P2TP2A) maupun NGO tidak semuanya memahami soal ini.
“Sebagian besar kawan-kawan di Solo Raya yang bersinergi erat dalam penanganan kasus kekerasan bersama SPEKHAM tidak cukup mengetahui kebijakan ini. Mereka bilang, oh iya mbak ada kebijakan itu ternyata, kami nggak tahu. Begitu juga dengan kawan-kawan NGO, ternyata di kawan-kawan kita sendiri juga tidak banyak yang mendapatkan informasi tentang kebijakan ini,” ungkap Rahayu.
Situasi penanganan terhadap perempuan korban kekerasan ini semakin berat dengan adanya fakta bahwa layanan kesehatan bagi korban masih parsial. Tidak ada pemeriksaan komprehensif untuk korban sebagaimana dipaparkan Rahayu.
“Misalkan polisi merekomendasikan untuk melakukan visum et repertum, ya layanan kesehatan hanya melakukan visum aja, tetapi kemudian tidak ada layanan yang secara komprehensif diberikan. Misalkan sekaligus tes IMS, atau tes kehamilan kalau memang kejadiannya sudah beberapa waktu yang lalu, atau profilaksi HIV,” kata Rahayu.
Di sisi lain langkah preventif pencegahan kehamilan bagi korban perkosaan belum menjadi wacana di kalangan penyedia layanan kesehatan di kabupaten dan kota di Jawa Tengah kecuali di Kota Semarang. Prosedur yang harus dilewati juga sangat panjang bahkan tidak ada aturan bakunya sehingga layanan kesehatan kadang-kadang memberikannya secara diam-diam.
Rahayu menjelaskan, “Pemberian kontrasepsi darurat kadang-kadang konyol, harus atas resep dokter, harus konfirmasi keluarga. Biasanya kami SPEKHAM manakala ada korban perkosaan yang kejadiannya masih dalam satu dua hari yang lalu, kami melihat kondisi korban sangat terpukul, sangat berat, maka kemudian kami memberikan informasi tentang alat kontrasepsi darurat. Kami juga pasti akan menginformasikan kepada pendamping korban dari pihak keluarga.”
Hambatan juga dihadapi korban karena kehamilan dianggap sebagai alat bukti kekerasan. Situasi ini membuat pendamping kesulitan memberikan saran kepada korban untuk mengakses aborsi aman. Sementara pilihan tersebut mungkin adalah yang terbaik bagi korban mengingat secara psikologis korban dalam kondisi tidak baik demikian juga secara ekonomi. Menurut Rahayu hal ini tidak terlepas dari posisi aparat penegak hukum terhadap alat bukti.
“Bahwa visum tidak dipandang sebagai alat bukti yang cukup. Bahwa alat-alat bukti yang lain dirasa kurang maka aparat penegak hukum masih melihat ya kehamilan ini sebagai alat bukti kekerasan,” ujar Rahayu.
Sementara ketika korban menghendaki penghentian kehamilan, pendamping dihadapkan pada situasi yang sangat rumit. Ini dikarenakan undang-undang memperbolehkan aborsi dan seharusnya pemerintah menyelenggarakan layanan tersebut tetapi pada kenyataannya tidak ada layanan rujukan yang bisa diakses dengan mudah dan aman. Bila korban ingin mengakhiri kehamilan pendamping akan merujuk secara diam diam.
Rahayu mengungkapkan, “Terpaksa kami harus merujuk secara diam-diam lagi karena memang ada kriminalisasi kepada pendamping dan lain sebagainya.”
Direktur LBH APIK Jakarta, Siti Mazuma menambahkan kriminalisasi juga dialami oleh tenaga medis dan ahli. Ia mengungkapkan, “Ini kasusnya sudah agak lama tetapi bisa jadi ini terjadi lagi gitu ya, seorang tenaga medis yang membantu melakukan aborsi kepada korban kekerasan seksual justru ditangkap oleh polisi.”
Situasi yang sama juga terjadi pada ahli yang disediakan LBH APIK Jakarta dalam penanganan beberapa kasus. Mereka mengalami hal serupa.
Hambatan lain adalah terkait dengan aturan aborsi yang memberi batasan berdasarkan usia kehamilan tertentu untuk dapat mengakses aborsi aman. Rahayu mengutarakan pendamping tak jarang dihadapkan pada situasi yang sulit terkait pembatasan tersebut.
“Pada saat (korban–red) datang dalam kondisi kehamilan 6 sampai dengan 7 bulan, maka kami sebagai kuasa hukum korban, tidak cukup mampu memiliki ruang-ruang untuk mendorong korban mengakses layanan aborsi aman,” tutur Rahayu.
Pembatasan ini menjadi tantangan yang sangat besar mengingat masyarakat cenderung banyak pertimbangan sehingga kadang-kadang terlambat melapor. Siti Mazuma menambahkan hal ini biasanya juga terjadi pada kasus kekerasan seksual terhadap perempuan disabilitas.
“Korban tidak tahu kalau hamil dan baru diketahui ketika (usia kehamilan–red) sudah di atas 3 bulan. Apalagi ketika ini adalah perempuan disabilitas, biasanya kasus-kasus perempuan disabilitas itu mereka tidak mengetahui bahwa mereka menjadi korban kekerasan seksual. Tahu-tahu ketika ibunya melihat kok sudah tiga bulan anakku tidak mengambil pembalut. Nah itu ternyata sudah sangat lama gitu ya,” ujar Mazuma.
Selain itu perspektif dan pengetahuan yang minim serta dogma yang masih kuat di masyarakat membuat pendamping korban tidak berani menyarankan untuk pilihan terminasi. Anggapan bahwa aborsi adalah dosa dan tidak manusiawi masih kuat.
“Jadi ini masih sangat kuat sekali apalagi dari hasil pemetaan pada beberapa kawan P2TP2A ya mereka perspektifnya belum selesai, sangat normatif. Jadi ini akan semakin membuat berat kerja-kerja untuk mendorong korban mendapatkan akses layanan aborsi yang lebih baik,” tegas Rahayu.
Isu Hak Aborsi Bagi Korban Perkosaan Belum Jadi Prioritas Media
Dalam situasi ketika perempuan korban perkosaan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan belum terpenuhi hak-haknya, media sesungguhnya merupakan bagian penting untuk mendukung advokasi dengan cara memberitakan. Kampanye melalui media dinilai juga efektif untuk menggalang dukungan masyarakat secara lebih cepat.
Namun riset Konde.co memperlihatkan media masih minim dalam mengangkat pemberitaan soal hak aborsi bagi korban perkosaan. “Tim peneliti Konde.co menemukan masih jarang media mengangkat isu aborsi bagi korban perkosaan, fenomena kekerasan seksual justru mengambil polisi atau institusi yang kadang tak terkait langsung dengan korban kekerasan seksual sebagai narasumber. Itulah mengapa terkadang pemberitaan yang muncul hanya seputar motif kekerasan seksual sedang korban tak punya hak bicara,” papar Luviana, Pemimpin Redaksi Konde.co dalam peluncuran Riset, Rabu (10/8/2022).
Tim riset Konde.co juga menemukan sejumlah media menuliskan secara normatif soal aborsi yang dipertentangkan, seperti soal boleh atau tidak boleh melakukan aborsi, masih mempertentangkan antara pro-choice dan pro-life, padahal aturan hukum di Indonesia sudah berubah untuk soal ini.
“Sementara aturan UU Kesehatan 36/2009 yang menyebutkan bahwa aborsi boleh dilakukan dalam kondisi tertentu tak terosialisasi dengan baik akibat jurnalis yang dikejar kuota pemberitaan harian,” ungkap Nurul Nur Azizah, Tim Peneliti Konde.co.
Lebih lanjut Nurul menjelaskan masih minimnya pemberitaan soal hak aborsi bagi korban perkosaan dilatarbelakangi oleh beberapa alasan. Pertama, kurangnya pemahaman awak media akan isu ini. Kedua, tidak banyak media yang mengangkat soal hak aborsi bagi korban perkosaan karena takut menyinggung norma sosial dan agama, padahal sebetulnya hal ini sudah memiliki justifikasi dari sisi hukum dan agama. Hal lain, para jurnalis juga tidak pernah mengikuti pelatihan khusus terkait isu hak aborsi bagi korban perkosaan serta kurangnya pemahaman lantas membuat kentalnya stigma terhadap aborsi.
Menanggapi riset Konde.co Managing Editor Koran Tempo Sunu Dyantoro mengatakan penelitian tersebut mencerminkan jurnalisme kita saat ini sekaligus bisa menjadi cambuk bagi media agar bekerja lebih profesional.
“Ini sebuah realitas yang terjadi dalam jurnalisme kita, bahwa jurnalis penting menambah pengetahuan soal kekerasan seksual,” jelasnya.
Realitasnya, Sunu mengungkap bentuk kekerasan terhadap perempuan yang tinggi pembacanya seperti kasus perkosaan, intimidasi atau percobaan perkosaan, pelecehan seksual, prostitusi paksa yang kini banyak menggunakan cara daring, aborsi, dan aturan diskriminatif terhadap perempuan. Sejauh ini, menurut Sunu meja redaksi Tempo sudah melakukan tugas dengan bertanggung jawab. “Contohnya, sebelum kami menerima reporter baru kami menanyakan perspektifnya soal kekerasan seksual hingga mengedukasi reporter agar memperhatikan etika penulisan berita soal kekerasan seksual,” ujarnya.