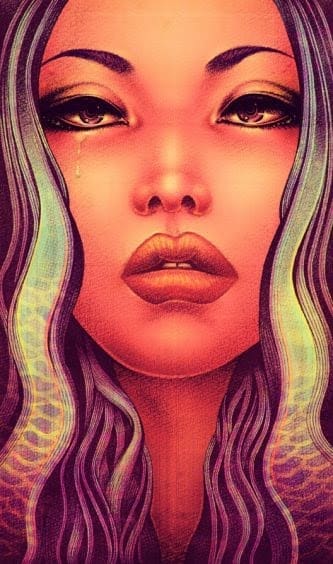Mulai dari labilnya kebijakan Elon Musk sebagai pemilik baru Twitter, keputusan Meta untuk memberhentikan lebih dari 11.000 pegawainya, hingga anjloknya saham-saham teknologi, industri media sosial lagi-lagi dilanda kekacauan. Namun, di saat gelombang kejutan ini menarik banyak sekali perhatian publik, tak banyak yang membicarakan dampaknya pada perempuan.
Perusahaan-perusahaan besar gagal melindungi perempuan di kedua sisi layar: para pekerja mereka dan para pengguna layanan. Ini mengapa langkah-langkah yang diambil untuk mengatur perusahaan media sosial harus mengikutsertakan perlindungan khusus bagi perempuan.
Pelecehan daring, seperti yang telah berulangkali dikonfirmasi oleh penelitian akademik dan kelompok sipil, kerap menyasar pengguna perempuan.
Salah satu kebijakan Musk setelah membeli Twitter adalah untuk memperkenalkan verifikasi demi memangkas jumlah akun palsu. Akun-akun tersebut kerap dikutip sebagai sumber utama kekerasan dalam media sosial. Namun, proses otentifikasi yang diperkenalkan Musk hanyalah sekadar meminta akun-akun “centang biru” untuk membayar tarif bulanan – dan kebijakan ini telah dicabut menyusul protes warga Twitter.
Langkah ini lebih terlihat seperti cara untuk meningkatkan pemasukan alih-alih strategi keamanan daring yang efektif. Parahnya lagi, di saat bersamaan, Musk juga mengambil tindakan kontroversial dengan mengembalikan akun beberapa figur terkenal yang sebelumnya diblokir karena wacana misogini. Ini termasuk Andrew Tate, yang mendefinisikan dirinya sendiri sebagai influencer “seksis”.
Terlepas kacaunya pendekatan kepemimpinan Musk, keputusan-keputusan ini mengindikasikan adanya tren yang merebak dalam industri sosial media, dengan konsekuensi yang luas bagi perempuan.
Faktanya, selama beberapa tahun terakhir, platform seperti Twitter, Facebook, YouTube, dan TikTok telah merespons derasnya tuntutan publik dengan mangadopsi pedoman yang lebih ketat terhadap ujaran kebencian berbasis gender. Namun, perubahan ini kebanyakan diterapkan lewat regulasi mandiri dan kemitraan sukarela dengan sektor publik. Pendekatan ini membuat perusahaan bebas untuk menarik kembali keputusannya, seperti apa yang dilakukan oleh Musk.
Di samping itu, menyensor figur di internet atau mempromosikan verifikasi akun tidak betul-betul mengatasi penyebab utama kekerasan dalam media sosial. Desain aktual platform dan model bisnis perusahaan memainkan peran yang lebih sentral.
Platform media sosial berusaha untuk menjaga kita terus berada di dunia maya demi menghasilkan data yang membawa profit dan menjaga audiens untuk bisnis iklan mereka. Mereka melakukan ini melalui algoritma yang menciptakan ruang gema. Artinya, kita akan terus melihat konten yang sama dengan apapun yang membuat kita pertama kali tertarik untuk mengkliknya.
Namun riset menunjukkan bahwa hal ini turut memfasilitasi peredaran pesan-pesan yang “memecah belah”. Sistem tersebut juga mendukung penyebaran seksisme di dunia maya, dan mendorong pengguna yang pernah menonton suatu konten problematis masuk ke dalam “lubang hitam” unggahan yang seragam.
Sementara platform-platform ini menjadi problematis bagi para pengguna perempuan, banyak dari perusahaan di baliknya juga gagal melindungi pekerja perempuan yang turut membangun dan mengelola jaringan media sosial.
Redundansi Perusahaan Teknologi
Bagaimana perusahaan media sosial memperlakukan karyawannya perlu dilihat dari lensa gender, apalagi mengingat bagaimana perusahaan-perusahaan ini melakukan PHK massal dan strategi pemangkasan beban lainnya sebagai reaksi terhadap lesunya pasar.
Salah satu kelompok yang paling terimbas (menurut hasil pengamatan yang saya tuliskan di buku saya yang baru saja diterbitkan) adalah moderator media sosial.
Para moderator ini bertugas membersihkan platform dari konten-konten yang melanggar standar komunitas. Mereka terus menerus terpapar ujaran kebencian yang bersifat misoginis, foto-foto kekerasan seksual dan pornografi non-konsensual. Staf perempuan – utamanya – kerap terpicu oleh konten-konten ini. Banyak dari mereka yang kemudian kena masalah kesehatan mental, termasuk depresi, kecemasan, dan sindrom stres pascatrauma.
Perusahaan media sosial dan subkontraktor internasional mereka (yang banyak menyuplai tenaga alihdaya) menerapkan kebijakan-kebijakan lain yang juga melanggar hak karyawan, khususnya moderator perempuan. Salah satu yang terbaru adalah menempatkan kamera dengan kecerdasan buatan di rumah moderator yang bekerja dari jarak jauh. Langkah ini merupakan intrusi yang sangat brutal bagi perempuan, apalagi mereka sudah sering menghadapi pelecehan atau masalah keamanan di ruang publik.
Pelecehan daring dan perlakuan terhadap pekerja berimbas pada semua gender. Namun, ada dampak khusus yang harus ditanggung perempuan dari kekerasan di media sosial. Sebuah studi dari The Economist menunjukkan bahwa ketakutan terhadap adanya agresi baru mendorong sembilan dari 10 korban yang disurvei mengubah habit dunia maya mereka – 7% bahkan keluar dari pekerjaannya.
Solusi Spesifik Untuk Kebencian di Dunia Maya
Seperti layaknya pekerja perempuan dan pengguna yang menghadapi isu-isu spesifik akibat kebijakan – atau tidak adanya kebijakan – media sosial, intervensi untuk meningkatkan keamanan dan kesejahteraan mereka pun juga harus spesifik.
Buku saya membahas bagaimana kapitalis digital – termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan media sosial – mengecewakan pengguna dan pekerja perempuan, dan bagaimana cara mengatasinya. Di antara perubahan yang saya sarankan adalah intervensi untuk membuat platform lebih bertanggung jawab.
Rancangan Undang-Undang Keamanan Daring di Inggris, misalnya, dirancang untuk memberi regulator otoritas untuk mendenda atau menuntut perusahaan yang lalai menghapus konten-konten berbahaya (harmful). Namun, penting bagi perubahan kebijakan di area ini untuk mengidentifikasi perempuan sebagai kategori pengguna yang dilindungi, dan rancangan undang-undang ini masih belum mempertimbangkan hal tersebut. Komitmen transparansi terkait algoritma dan regulasi platform seputar bisnis penambangan data juga dapat membantu, tetapi sejauh ini belum – atau belum sepenuhnya – terintegrasi ke sebagian besar undang-undang nasional dan internasional.
Dan karena pekerja juga harus mendapatkan perlindungan yang sama besarnya dengan pengguna, penting untuk memastikan bahwa mereka bisa berserikat dan harus ada dorongan bagi para pemberi kerja untuk menghormati kewajiban mereka memerhatikan tenaga kerjanya. Ini misalnya termasuk melarang pengawasan yang invasif di tempat kerja.
Satu solusi terkait pengguna dan pekerja perempuan: sudah waktunya bagi raksasa media sosial untuk menerapkan strategi-strategi spesifik untuk melindungi perempuan di kedua sisi layar.
Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.