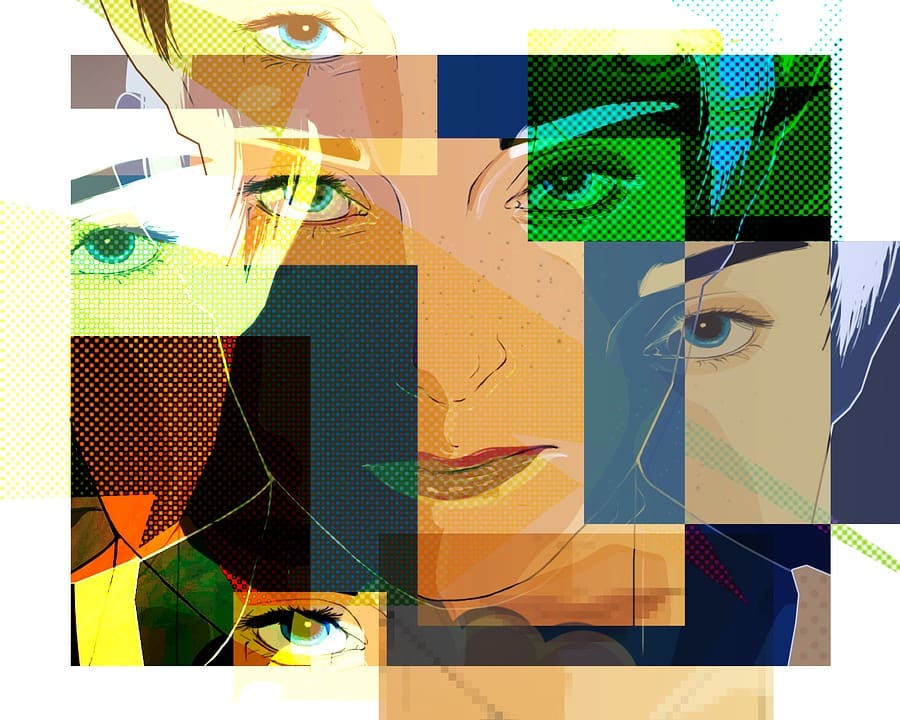*Jony Eko Yulianto – www.Konde.co
“Perempuan itu diibaratkan seperti burung phoenix. Dia harus cantik, tetapi juga kuat di saat yang bersamaan. Selamat menjalani hari ini, perempuan-perempuan hebat. Di tangan kita masa depan bangsa ini berada”.
Kutipan di atas saya ambil dari catatan gambar (caption) salah satu foto di Instagram Veronica Tan (@veronicabtp), istri Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Melalui foto yang diunggah pada 29 Maret 2017 ini, Veronica menggambarkan dua tipologi kepribadian yang seharusnya dimiliki oleh seorang perempuan, yakni cantik dan kuat, melalui metafora burung phoenix.
Pemilihan Burung Phoenix sebagai metafora untuk memotret kepribadian perempuan ini tergolong unik, mengingat perempuan kerap digambarkan dengan jenis burung lain. Merak misalnya, pernah digunakan oleh Peter Popham dalam karyanya, The Lady and The Peacock: The Life of Aung San Suu Kyi sebagai metafora dalam menegaskan karakter penerima Nobel Perdamaian asal Burma tersebut.
Merpati, melalui istilah “jinak-jinak merpati”, lazim dipakai dalam Sastra Indonesia untuk menggambarkan fluktuasi afeksi perempuan dalam menjalin relasi. Simak pula bagaimana Cary Anderson, melalui bukunya The Eagle Lady, menunjukkan ketangguhan Jean Keene yang ia gambarkan bagai burung elang liar.
Maka menggunakan Phoenix sebagai objek metafora untuk menjelaskan eksistensi perempuan adalah hal yang menarik untuk dibahas. Namun demikian sebelum berdiskusi lebih lanjut, sebenarnya ada dua pertanyaan mendasar terkait isu metafora Burung Phoenix ini: Sejauhmana kita dapat mengeksplorasi makna perempuan cantik dan kuat dalam kacamata Burung Phoenix? Apakah cantik dan kuat yang diulas dalam hal ini adalah sesuai dengan makna universal yang biasa kita pahami atau ada makna khusus di dalamnya?
Pertanyaan di atas penting untuk kita ulas karena memahami metafora memerlukan sebuah pemahaman yang kontekstual. Karin Moser, melalui karyanya Metaphor Analysis in Psychology, menjelaskan sebuah prinsip dalam memahami simbol-simbol metafora: Penciptaan metafora adalah hasil imaji kognitif yang sangat dipengaruhi budaya (culturally constructed). Maka, cara memahami metafor yang paling ideal sebenarnya adalah dengan memahami konteks dan latar belakang budaya yang membentuknya.
Phoenix dalam Pandangan Tionghoa
Phoenix sebenarnya merupakan karakter mitologi Yunani yang secara alegoris melambangkan kelahiran baru. Konon setelah hidup selama 500-1.500 tahun, Phoenix akan mati dengan cara membakar dirinya sendiri. Melalui abu sisa pembakaran tersebut, lahirlah Phoenix muda. Inilah yang menjadikan burung ini kerap pula digunakan sebagai lambang keabadian dan pengorbanan.
Dalam kebudayaan populer, penyair legendaris William Shakespeare membuat puisi berjudul The Phoenix and The Turtle untuk menggambarkan kematian cinta sejati. Sementara itu, Edith Nesbit, mengarang The Phoenix and The Carpet untuk menjelaskan nilai-nilai persahabatan Phoenix dengan seorang anak. Dalam novel Harry Potter, J.K. Rowling menciptakan karakter Phoenix bernama Fawkes yang digambarkan sebagai burung kuat dan loyal.
Dalam kebudayaan Cina, Burung Phoenix memiliki penekanan makna alegoris lain. Burung yang di kalangan pengamat budaya negeri Tirai Bambu disebut sebagai Feng Huang ini merupakan satu dari empat makhluk supranatural bersama dengan naga (liong), kilin (qilin), dan kura-kura (gui). Burung Phoenix memiliki kedudukan tinggi karena dipakai sebagai motif kain yang hanya boleh dipakai oleh para permaisuri Cina.
Wujud Burung Phoenix dalam kebudayaan Cina digambarkan memiliki kepala burung pelikan, berleher seperti ular, berekor bagai sisik ikan, bermahkotakan burung merak, dan memiliki lima warna bulu yang melambangkan lima nilai luhur. Kepalanya adalah lambang kebajikan, sayapnya adalah tanggung jawab, punggungnya adalah perbuatan baik, dadanya adalah kemanusiaan, dan perutnya adalah sifat yang terpercaya. Karenanya, ia adalah jenis burung paling terhormat diantara segala makhluk. Ia adalah simbol perempuan yang sempurna.
Bagaimana kita kemudian menjelaskan keterkaitan alegori-alegori Burung Phoenix di atas dengan eksistensi kiprah perempuan dalam berbagai bidang kehidupan sebagaimana menjadi kegelisahan Veronica Tan? Sejauhmana pemilihan metafora tersebut relevan memotret situasi perempuan saat ini?
Mendobrak Langit-langit Kaca
Jika kita menggunakan kacamata kesetaraan hak-hak perempuan dalam berkiprah di level kepemimpinan sebagai kacamata analisis, niscaya kita akan lebih dapat memahaminya (Baca pula artikel “Perempuan Masih Tertinggal”, Kompas 31 Maret 2017). Indeks Melakukan Bisnis 2017 (Doing Business Index 2017) dari Bank Dunia misalnya, menemukan adanya kecenderungan bahwa kebijakan-kebijakan dalam wirausaha yang berlaku di 155 negara cenderung merepresentasikan kesenjangan keadilan yang dialami oleh perempuan dalam berwirausaha.
Selain itu, ditemukan pula bahwa perempuan cenderung menghadapi tantangan yang lebih besar dalam memulai sebuah usaha dibandingkan dengan laki-laki. Contohnya dalam hal registrasi korporasi. DBI 2017 menemukan adanya perbedaan persyaratan registrasi yang harus dipenuhi jika sebuah korporasi dimiliki oleh seorang wirausahawan perempuan. Di beberapa negara, seorang wirausahawan perempuan diminta untuk menambahkan surat persetujuan dari suami.
Contoh lainnya yang menarik untuk diangkat adalah tentang perbedaan perlakuan terhadap wirausahawan perempuan dalam hal akses terhadap kredit. Pihak pemberi kredit kerap over-fokus apakah perusahaan dimiliki oleh sang perempuan atau milik suaminya. Beberapa fakta menunjukkan bahwa rasio persetujuan kredit lebih tinggi diberikan kepada wirausahawan laki-laki dibandingkan dengan wirausahawan perempuan.
Michelle Ryan dan Alexander Haslam, dua ilmuwan psikologi sosial dunia, memperkenalkan sebuah terma menarik untuk menjelaskan fakta di atas: fenomena langit-langit kaca (glass ceiling phenomenon). Mereka berpendapat bahwa perempuan memiliki kecenderungan tidak dapat memiliki kiprah sampai ke puncak karena kerap kali tertahan oleh langit-langit kaca.
Penahan ini dimetaforakan sebagai kaca karena tidak nampak, tetapi dapat dirasakan secara nyata. Wujudnya dapat berupa ketidakpercayaan dari pimpinan atau bawahan atau adanya pandangan konvensional bahwa peran perempuan sebaiknya hanya di balik layar mengerjakan tugas-tugas domestik.
Maka jika kita menggunakan Burung Phoenix sebagai pisau analisis metafor, interpretasi cantik dan kuat dalam konteks perempuan sebagai pemimpin setidaknya memunculkan dua poin refleksi. Pertama, perempuan yang cantik sekaligus kuat adalah ketika ia mampu bertahan dalam kesulitan-kesulitan, menghadapi dan bahkan mendobrak setiap penahan kasat mata, untuk tetap memberikan karya terbaik dalam bidangnya masing-masing seperti Phoenix yang hidup ribuan tahun.
Kedua, seorang perempuan dapat disebut cantik dan kuat ketika dengan segenap tanggung jawab dan pengorbanannya ia berupaya menghasilkan pemimpin-pemimpin baru, sebagaimana Burung Phoenix yang bersedia mengorbankan dirinya sendiri untuk melahirkan Phoenix-Phoenix muda.
Jadi, penggunaan Burung Phoenix sebagai metafor ini relevan untuk semua perempuan, terlepas dari apakah ia memilih berkarir atau menjadi ibu rumah tangga. Ketika ia melakukan berbagai kebajikan, menunjukkan tanggung jawab, memberikan manfaat luhur bagi orang-orang di sekitarnya, ia adalah Phoenix yang cantik sekaligus kuat.
Damai di bumi.
*Jony Eko Yulianto, Dosen psikologi sosial, kolumnis surat kabar, penikmat durian dan terang bulan keju, suporter Barcelona, dan mengidolakan Xavi Hernandez.