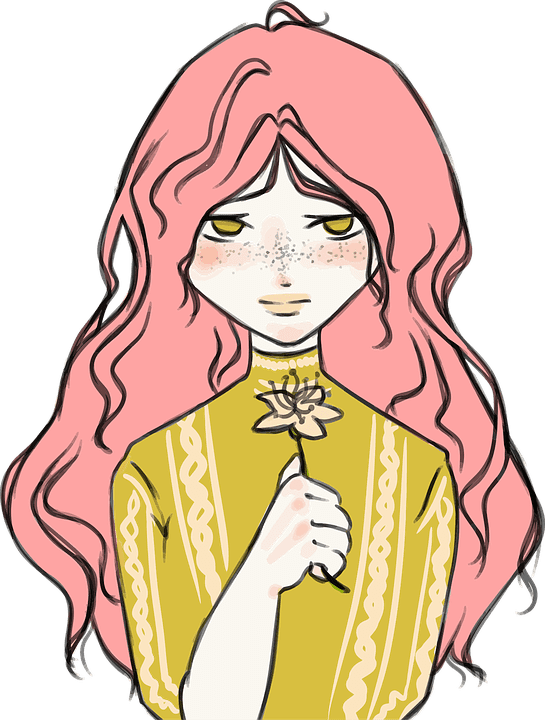*Aprelia Amanda- www.Konde.co
Jakarta, Konde.co- Nonoy Espani datang untuk menggantikan Maria Ressa. Maria Ressa tidak mendapatkan izin dari Pemerintah Filipina untuk datang ke Indonesia karena kasus yang sedang dihadapinya.
Maria Ressa adalah perempuan yang menjadi pemimpin redaksi situs media Rappler, Filipina yang ditangkap setelah menulis secara kritis terhadap pemerintah Filipina.
Maria Ressa menjadi representasi bagaimana kebebasan pers di Filipina masih bermasalah. Nonoy Espani yang menggantikan Maria Ressa mengungkapkan, bahwa saat ini Filipina masih menghadapi masalah upah dan lingkungan kerja yang tidak layak. Banyak jurnalis yang dibunuh beberapa tahun belakangan. Media sosial dijadikan senjata oleh negara untuk menuntut pencemaran nama baik .
“Facebook adalah senjata yang dimiliki negara. Begitu yang biasa dikatakan Maria Ressa”, ungkap Nonoy.
Pemerintah menyebarkan berita bohong lewat facebook dengan membuat judul-judul yang bombastis tanpa isi yang jelas. Masyarakat Filipina hanya membaca judul dan komentar lalu dengan mudah terprovokasi. Kondisi ini membuat kesenjangan antara masyarakat dan jurnalis.
“Negara menjadikan sosial media (facebook) untuk membunuh media”.
Yang dihadapi Maria Ressa adalah problem yang dialami pekerja pers di dunia yaitu pembungkaman.
Saya juga mengamati hal yang lain yang masih menjadi problem media kita, yaitu tentang isi sejumlah media online, sejumlah media online di Indonesia misalnya masih menuliskan artikel yang sensasional terhadap tubuh-tubuh perempuan. Hal ini bisa dilihat dari judul, isi dan gambar. Buat saya, sensasionalisme tubuh perempuan harus dikategorikan dalam penilaian pers bagaimana media kita memandang perempuan.
Namun sayang, sensasionalisme tubuh perempuan di media ini belum dimasukkan dalam banyak indeks penilaian kebebasan pers, walaupun masalah kebebasan pers selalu menjadi diskusi yang sangat serius di banyak negara. Dalam sebuah forum media, hal ini pernah diusulkan karena penting untuk melihat bagaimana media memandang publik marjinal salah satunya perempuan.
Reporters Without Bourders (RSF), mempunyai laporan tentang indeks kebebasan pers di dunia. Indeks kebebasan pers Indonesia dalam satu dekade terakhir menduduki peringkat tertinggi mencapai 101 di tahun 2009. Namun setelah itu peringkat Indonesia sesalu berada di bawah 110. Artinya kondisi kebebasan pers kita tidak cukup baik secara internasional.
Kondisi ini disebabkan karena konstitusi kita tidak memberi perlindungan yang cukup kuat bagi kebebasan pers. Undang-undang pers belum mampu melindungi wartawan karena pengaturannya masih sangat umum terutama soal perlindungan hukum bagi wartawan. Hal ini didiskusikan dalam pertemuan ini betajuk Regional Conference: The Challenge of Journalism in Digital Era yang diadakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pada 6 Agustus 2019.
Sejumlah pembicara dihadirkan seperti Steven Gan Editor in Chief Malaysiakini.com, Jane Worthington Direktur IFJ Asia Pasific, Adam Portelli Victorian Branch of Media Entertaining and Art Alliance (MEAA), Nonoy Espani Ketua Nation Union of Journalists of the Philippines (NUJP), dan Asep Setiawan Anggota Dewan Pers.
Memasui era digital para jurnalis menghadapi tantangan-tantangan baru. Fenomena citizen jurnalisme menjadi hal yang baru. Warga yang bukan jurnalis kini bisa membuat berita dan menyebarkannya lewat sosial media. Kini jurnalis bukan satu-satunya orang yang bisa membuat berita, tapi ini bukan berarti kematian bagi para jurnalis. Jurnalis akan tetap hidup karena ada mutu berita yang terus dijaga.
“Jurnalis akan berubuah menjadi verifikator tapi juga harus tetap memproduksi berita”, ungkap Asep Setiawan.
Masalah kebebasan pers menjadi sorotan beberapa panelis. Menurut Asep Setiawan, kawasan Asia Tenggara masih menghadapi masalah kebebasan pers seperti yang terjadi di Kamboja, Myanmar, Filipina, Thailand, dan tentunya juga Indonesia.
Meskipun berdasarkan Press Freedom Index 2019, Indonesia menerima nilai 69 yang termasuk dalam kategori agak bebas, ini masih menandakan bahwa kebebasan pers di Indonesia belum sepenuhnya bebas.
Steven Gan juga menyoroti dampak dari masalah kebebasan pers yang lebih luas. Ia mengambil sebuah contoh film dokumenter yang berjudul Active Measures yang isinya tentang keterlibatan Rusia di Ukraina. Rusia tidak mengirim tank ke Ukraina, tapi mereka menciptakan ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Kedua kelompok mereka biayai dan mereka menyebarkan berita kebohongan. Dengan cara ini demokrasi dapat terbunuh.
“Mereka membunuh demokrasi dengan cara membunuh jurnalis,” ungkapnya Steven Gan.
Adam Portelli menyoroti masalah ketidakadilan bagi para jurnalis media digital. Bersama dengan serikatnya Media Entertaining and Art Alliance (MEAA) ia meluncurkan kampanye Good Job in Digital Media. Para pekerja media harus siap berdiri bersama untuk memperjuangkan upah yang adil dan kondisi kerja yang layak. Kampanye ini dilakukan untuk memperjuangkan upah dan kondisi kerja yang layak bagi pekerja media.
Ia juga menyoroti soal pekerja freelance di media, menurutnya harus ada perjanjian yang jelas antara media dan pekerja freelance agar tercipta situasi kerja yang layak, karena media-media menyerap banyak frellancer sehingga masalah ini juga harus diperhatikan.
Untuk menghadapi segala tantangan bagi para jurnalis di era digital ini, jurnalis tidak dapar bergerak sendiri. Jurnalis harus berserikat untuk menuntut kebebasan pers, upah dan lingkungan kerja yang layak.
“Bagaimana jurnalis bisa bertahan hidup di era digital ini, salah satunya dengan bekerja bersama”, Jane Worthington.
Jika tidak bekerjasama, salah satu yang bisa dilakukan adalah dibungkam suaranya.
(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)
*Aprelia Amanda, biasa dipanggil Manda. Menyelesaikan studi Ilmu Politik di IISIP Jakarta tahun 2019. Pernah aktif menjadi penulis di Majalah Anak (Malfora) dan kabarburuh.com. Suka membaca dan minum kopi, Manda kini menjadi penulis dan pengelola www.Konde.co