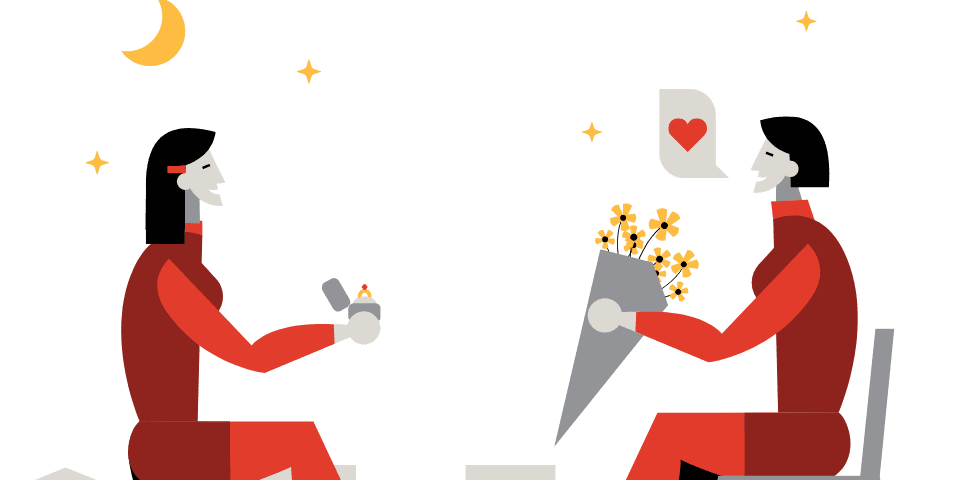Adit, kawan saya; bukan nama sebenarnya, adalah seorang laki-laki gay yang mengalami kekerasan seksual oleh pacarnya sendiri sesama lelaki gay.
Sang pacar kerap melakukan kekerasan fisik (abusif) dengan memaksanya melakukan penetrasi. Padahal, Adit telah mengatakan bahwa tindakan tanpa konsensus itu membuatnya merasa tidak nyaman.
Tidak hanya terluka secara fisik, praktik kekerasan itu juga membuat Adit tersiksa secara psikis dan emosional—ia menjadi trauma dan ketakutan
Selain tindak kekerasan fisik, masih ada lusinan praktik manipulasi, pengekangan, dan kebohongan yang dilakukan sang pacar selama lebih dari dua tahun mereka menjalin hubungan. Hal itu membuat Adit merasa terikat dan tidak memiliki kebebasan untuk mengaktualisasikan diri di luar hubungan percintaan mereka.
Ditambah lagi, sang pacar juga kerap memainkan emosinya dengan rutin menjejalkan perkataan, “Hanya aku yang menyayangimu. Semua orang, termasuk keluargamu, membencimu karena kamu adalah seorang pendosa.”
Sebagai seorang individu gay, ucapan manipulatif semacam itu membuat perasaan rendah diri atau low self-esteem di dalam dirinya semakin membuncah. Hal itu mengingat ia pernah ditolak oleh keluarganya akibat pengakuannya sebagai seorang lelaki gay. Situasi itu menjadi pintu masuk bagi sang pacar untuk membangun kuasa atas kehidupan Adit, termasuk untuk melancarkan sikap posesif secara berlebihan.
Relasi Sakit Tapi Menjebak Seperti ‘Candu’
Situasi yang dihadapi Adit dapat dikategorikan sebagai bentuk hubungan beracun atau toksik alias toxic relationship. Individu yang terjebak dalam hubungan beracun akan mengalami berbagai dampak destruktif, baik secara fisik maupun psikis. Hal itu mungkin terjadi sebab hubungan percintaan (termasuk pacaran) cenderung melekat sifat saling ketergantungan (dependen).
Menurut Mia Olivia, seorang peneliti hak-hak perempuan di Komnas Perempuan, sifat ketergantungan tersebut dapat dimanipulasi oleh salah satu pihak untuk mendominasi dan mendulang kuasa atas pasangannya. Pada saat itulah, hubungan beracun sangat dimungkinkan terjadi.
Perlakuan toksik semacam itu muncul karena salah satu pihak merasa memiliki posisi tawar (power) lebih tinggi dibandingkan pasangannya. Hal itu menjadi pondasi bagi terbangunnya sebuah hubungan tidak setara dalam berpacaran yang tidak jarang dapat berujung pada berbagai praktik kekerasan, mulai dari kekerasan fisik, psikis (emosional), ekonomi, bahkan juga kekerasan budaya.
Apabila ditarik ke belakang, nalar untuk mendominasi di dalam hubungan beracun merupakan warisan budaya patriarki yang meletakkan maskulinitas (biasanya melekat pada laki-laki) pada posisi yang lebih superior dibandingkan feminitas (biasanya dilekatkan pada perempuan).
Dikotomi antara superioritas (maskulin) dan inferioritas (feminin) itu menjadi awal mula lahirnya dominasi yang satu atas yang lainnya. Maka dari itu, meskipun hubungan beracun dapat menjebak siapa saja (terlepas dari identitas gender dan seksualitasnya), perempuan (atau ekspresi gender yang cenderung feminin) biasanya lebih sering dijadikan korban.
Walaupun hubungan beracun ada yang diterapkan secara terang-terangan (semisal kekerasan fisik), banyak pula yang dipraktikan secara halus dan samar-samar melalui berbagai praktik manipulasi yang sarat akan kebohongan. Hal itu membuat korban merasa tidak sadar jika sedang didominasi dan dikuasai oleh pasangannya. Dalam artian, korban merasa ‘semuanya baik-baik saja.’
Adit semisal, merasa bahwa perilaku posesif dan sikap mengekang yang dilakukan pacarnya dilandasi oleh perasaan cinta. Hal itu membuat dia sulit sekali untuk melepaskan diri, meskipun ia sebenarnya merasa tersiksa. Tidak berlebihan untuk saya mengatakan bahwa sekalipun hubungan beracun itu menyakitkan, praktik manipulasi yang ada juga membuat korban sulit lepas dari hubungan itu
Mengintip Relasi Toksik
Hubungan beracun dapat menimpa siapa saja, baik cis-heteronormatif (biasanya hubungan antara laki-laki dan perempuan heteroseksual) maupun non-cis-heteronormatif (biasanya identitas gender non-biner).
Diskusi mengenai perempuan sebagai korban hubungan beracun telah banyak dibicarakan di berbagai ruang, baik di ruang kelas akademik maupun di ruang publik sehari-hari. Akan tetapi, saya melihat bahwa diskusi yang membahas hubungan beracun dalam kerangka non-cis-heteronormatif—terutama yang dialami oleh kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT)—masih belum banyak diperbincangkan. Padahal, kerentanan dan dampak-dampak yang ditanggung oleh mereka tidak kalah destruktif apabila membandingkannya dengan kekerasan yang terjadi dalam hubungan cis-heteronormatif.
Terjebaknya kelompok LGBT pada hubungan beracun disebabkan oleh diadopsinya relasi hubungan cis-heteronormatif ke dalam hubungan LGBT. Seorang Antropolog asal Amerika Serikat, Evelyn Blackwood, pernah menulis penelitian bertajuk “Tombois and Femmes”. Di dalam penelitian tersebut, Blackwood merekam kehidupan kelompok perempuan yang mengidentifikasi dirinya sebagai lesbian di Padang, Sumatera Barat. Blackwood menunjukkan bahwa subjektivitas lesbian di Padang dalam membangun hubungan dengan pasangannya menduplikasi relasi laki-laki (tombois) dan perempuan (femmes) sebagaimana yang terjadi di dalam masyarakat patriarkal.
Selain itu, Karakter tombois yang mengadopsi karakter maskulin dan femmes yang menduplikasi karakter feminin membuat praktik dominasi di dalam sebuah relasi percintaan memungkinkan individu-individu di dalamnya terjebak pada sebuah hubungan beracun. Sekali lagi, relasi semacam itu dapat menimpa seluruh identitas gender dan seksualitas, baik perempuan, laki-laki, maupun non-binary.
Sekalipun hubungan beracun dapat kita sebut sebagai salah satu bentuk kekerasan berbasis gender, rupanya tidak mudah bagi kelompok LGBT untuk menyatakan hak-haknya atas keadilan dan rasa aman. Hal itu disebabkan oleh karakter masyarakat kita yang umumnya masih belum terbuka terhadap identitas gender dan seksualitas non-cis-heteronormatif. Semisal, ketika mengalami praktik pemerkosaan berkali-kali, Adit merasa enggan untuk meminta perlindungan kepada negara melalui institusi kepolisian. Hampir bisa dipastikan, dia akan menghadapi beban dua kali lebih berat, yaitu tragedi kekerasan berbasis gender yang masih menghantuinya dan ketakutannya akan berbagai penghakiman.
Ketakutan tersebut memang cukup masuk akal, mengingat kuatnya sentimen homofobia yang mandarah daging di dalam tubuh institusi kepolisian—sebagaimana komentar mereka yang pernah menyebut LGBT sebagai penyakit yang harus disembuhkan.
Tanpa perlu beranjak jauh pada kasus kekerasan yang dialami oleh kelompok LGBT, kita tentu juga kerap mendengar kabar mengenai banyaknya kasus kekerasan berbasis gender yang dialami oleh perempuan, tetapi tidak diusut secara serius oleh kepolisian. Padahal, kasus tersebut masih terjadi dalam kerangka heteroseksual. Apabila jika itu terjadi pada kelompok LGBT yang dinilai tidak fit dengan norma heternormatif, tentu saja, persoalannya akan menjadi dua kali lebih berat.
Melalui lensa saya terhadap pengalaman Adit, saya menunjukkan bahwa hubungan beracun tidak hanya dialami oleh kelompok cis-heteronormatif (terutama perempuan), sebagaimana yang selama ini telah banyak dibicarakan. Hubungan beracun juga dapat menimpa siapa saja, terlepas dari identitas gender dan seksualitasnya.
Adit dan LGBT lain yang menjadi korban hubungan beracun bahkan mengalami beban ganda akibat diadopsinya budaya patriarki yang menganggap maskulinitas serba-superior. Karakter masyarakat kita yang cenderung sulit menerima keberadaan LGBT juga membuat mereka sulit untuk mencari perlindungan.
Pengalaman mereka perlu untuk disuarakan agar diskusi mengenai topik ini menjadi beragam.