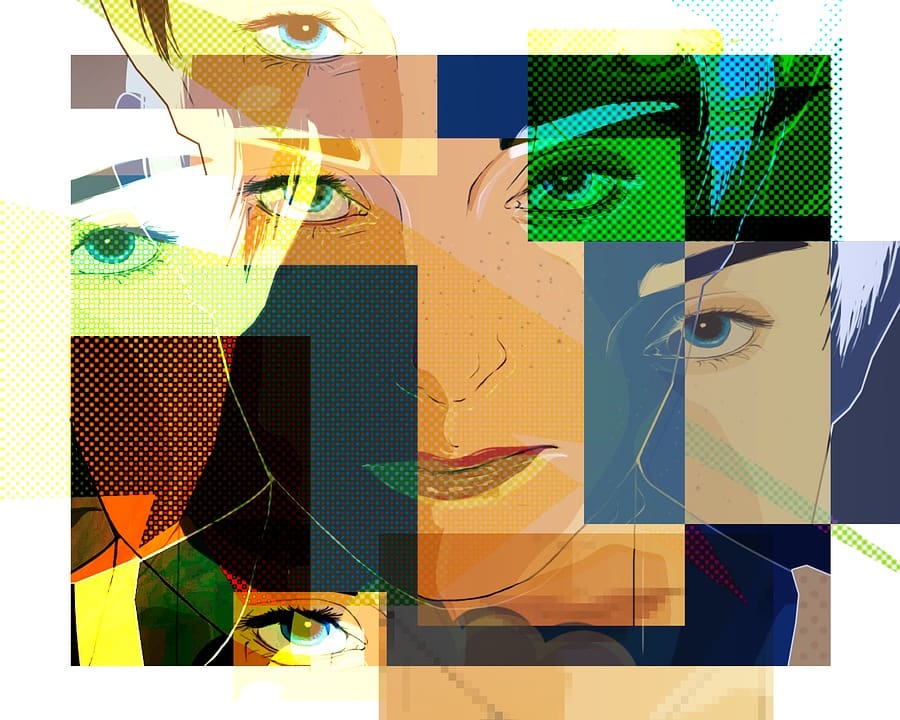Ribuan kilometer dari Pariaman, di pertengahan malam, awal tahun 2018, rumah Maria (bukan nama sebenarnya) seorang transpuan di Gowa, Sulsel, diseruduk puluhan warga. Di tengah gerombolan itu Maria melihat, ada tetangganya, ketua RT dan kepala Dusun.
Polisi bersenjata mengawal kelompok warga dan menggeledah rumahnya. Warga dan Polisi menghujani Maria dengan pertanyaan dan umpatan kasar. Maria terdesak, tak kuasa membela. Dia terpojokkan di rumahnya sendiri.
Di rumah itu, Maria tinggal bersama pasangannya dari Australia. Mereka telah menikah secara sipil di negara asal pasangannya. Saat kejadian, tubuh pasangan Maria terkulai lemas, nyaris pingsan.
“Kenapa kalian datang membongkar-bongkar? Memangnya kita bikin apa? Kita bisa bicara baik-baik,” kata pasangan Maria di hadapan warga, dengan bahasa Indonesia.
Tapi warga menutup telinga. Tetangganya kekeh mengusir mereka. Warga menganggap jika pasangan itu tinggal seatap, maka kesialan segera melumat warga. Padahal mereka sudah menikah secara sipil, Maria berkali-kali meyakinkan, tapi apa daya.
Maria menceritakan persekusi yang menimpa dirinya ke saya, pada penghujung November lalu. Kejadian itu membuat hati Maria hancur. Tubuhnya bergidik bila menceritakannya kembali.
Setelah kejadian itu, Maria terpaksa berdamai dan menuruti kemauan tetangganya. Maria dan pasangannya kini tinggal berpisah. Jarak yang terentang di pasangan itu, tak bikin mata warga tercabut dari rumah Maria.
“Warga bilang kalau tinggal berdua lagi, kami angkut ke kantor [polisi],” kata Maria.
Di Sulsel, Maria tidak sendiri. Sepanjang tahun 2007-2019, 21 transpuan telah menjadi korban kekerasan. Menurut studi Komunitas Sehati Makassar/ KSM melalui ketuanya,Eman Memay Harundja menyatakan, kebanyakan kasusnya menguap begitu saja.
Ironisnya, parade kekerasan ini, berguling di era reformasi. Seharusnya, demokrasi membuat Indonesia merengkuh keragaman, termasuk gender dan seksual. Namun ternyata tidak.
Kejadian seperti ini tak hanya terjadi di masyarakat, namun juga terjadi di media. Komunitas Sehati Makassar juga menemukan bahwa konstruksi di masyarakat, apa yang dikatakan pemerintah, kemudian mempengaruhi tulisan tentang kelompok minoritas gender dan seksual: Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender—kini Interseks dan Queer ditambahkan, LGBTIQ di media
Dina Listiorini, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) yang menyelesaikan studi Doktor, pada 4 Desember 2020, di Universitas Indonesia menemukan ini.
Mengangkat disertasi berjudul; Rezim Kebenaran Media dalam Kepanikan Moral. Disertasi Dina mengurutkan bagaimana media siber macam Kompas.com, Tempo.co, Republika.co.id, Viva.co.id dan media televisi, dari tahun 2016-2018 menebar narasi fobia LGBTI melalui praktik kuasa dan kebenaran secara sistematik.
“Ada semacam paradoks ya,” kata Dina.
Indonesia dikenal negara heteronormatif paling ekstrim. Sejak kecil, melalui institusi pendidikan, manusia Indonesia, ditanamkan doktrin tersebut, melalui konsep keluarga ‘ideal’. Ada ibu dan ayah: laki-laki sejatinya menikahi perempuan, lalu beranak-pinak. Konsep ini dikenal dengan heteroseksual. Maka konsep sebaliknya dianggap asing dan menerabas kenormalan.
Kepanikan moral, menurut Dina Listiorini, tumbuh melalui relasi kuasa dan pengetahuan, yang ingin mengabadikan doktrin heteronormatif—dengan membutuhkan pendisiplinan. Kepanikan moral yang homofobia, yang menebar rasa takut akan LGBTI, katanya adalah cara kuasa heteronormatif menundukkan seksualitas manusia: “tubuh yang patuh.”
Dan, bagi Dina, media walaupun tentu tidak semua—adalah satu diantara agen negara, yang menjaga moral sekaligus mendisiplinkan seksualitas warga negara.
“Saya temukan dengan wawancara jurnalis, bahwa, rezim heteronormatif itu, salah satu yang membentuk karakter pengetahuan jurnalis,” katanya.
Dina punya pengalaman mentoring wartawan di Indonesia. Kerap kali dia temukan, kekeliruan wartawan saat menulis tentang transpuan misalnya.
“Masih beranggapan, itu orang perlu tahu bahwa dulunya dia laki-laki. Itukan sebetulnya, ketika teman transgender perempuan pingin dikatakan sebagai perempuan, ya sudah. Kita harus menghormati bahwa dia ingin disebut perempuan. Gak perlu melihat asal-usulnya.”
“Saya kadang berpikir, memberikan pengetahuan SOGIESC [ke Jurnalis] itu tidak cukup. Menurut saya, yang lebih krusial lagi adalah, menghancurkan paham heteronormatif yang melekat di kepala jurnalis. Dan itu tidak mudah.”
SOGIESC adalah konsep pemahaman tentang keragaman seksualitas dan gender: orientasi seks, identitas dan ekspresi gender, dan karakteristik seksual.
Media meminggirkan LGBT
“Ada tiga peminggiran [terhadap LGBTI] yang dilakukan oleh media, yang kemudian media menjadi homophobic,” kata Dina.
Peminggiran bersifat ekonomi. Dina bercerita, wartawan kadang cemas bila memberitakan LGBTI dari ‘sisi yang berbeda’. Pengiklan dan pembaca tidak bakal merapat. Bahkan khawatir bakal dipecat atau diserang kelompok penentang.
“Salah satunya juga: Karena pesta seks gay itu kalau dalam algoritma Google tinggi. Kalau kita nggak nampilin itu, kita nggak dibaca,” Dina cerita ungkapan seorang wartawan.
“Itu persoalan teknologi, yang juga dipakai oleh media, yang jadi peminggiran.”
Dalam bisnis media siber, banyak ‘klik’ dan pembaca berarti keuntungan.
Media siber di Indonesia, umumnya mengandalkan iklan: dari pengiklan dan monetisasi situs lewat Google Adsense. Biasanya, pengiklan enggan membakar uangnya di media yang sepi pembaca. Tapi Google Adsense hal lain.
Google Adsense adalah tambang uang bagi media siber. Tak butuh bersusah payah, selama situs kebanjiran klik pengunjung.
“Jujur, kalau online dilihat dari nilai kliknya, jumlah pengunjung. Tidak bisa dipungkiri,” kata Edy Arsyad, Koordinator Sulsel Fajar Online.
“Kalau Fajar Online memberitakan LGBT, apakah banyak pembaca?” saya bertanya.
“Jujur bahwa judul-judul—yang tanda kutip—LGBT, banyak. Apalagi pemberitaan yang menyebutkan perkawinan LGBT. Karena istilahnya di luar konsep mainstream, pasti orang penasaran [membacanya].”
“Itu berpengaruh ke bisnisnya?”
“Kita bicara redaksional saja, bahwa ada peningkatan pembaca.”
Bagaimana dengan Tribun Timur?
“Tidak ada data spesifik, apakah banyak penghasilan dari kata kunci LGBT,” kata Mansur.
“Tapi rata-rata [berita LGBTI] yang banyak pembacanya. Yang viral baru-baru ini, soal oknum Polri dan TNI itu. Saya lihat memang banyak pembacanya. Belum ada saya temukan, LGBT tidak ramah bagi pengiklan.”
Menjelang pemilihan umum, isu LGBTI kerap kali menguat. Para calon, kerap berdandan diri anti-LGBTI demi mengikat suara pemilih–yang mayoritas menolak LGBTI. Peran media, menyiarkannya. Tanpa sadar–mungkin juga sadar–media telah melakukan peminggiran, yang bagi Dina, bersifat politik. Di Sulsel, cara itu bergulir ketika debat ketiga Pemilihan Gubernur soal minoritas, pada tahun 2018.
Kala itu, gagasan Andi Sudirman Sulaiman (ASS), sekarang Wakil dari Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (NA), tentang pemberdayaan kelompok LGBTI dipelintir oleh lawan politik. Bahwa pasangan Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman (NA-ASS) dukung LGBTI.
Di Indonesia, menyatakan dukungan kepada LGBTI mengundang masalah. Dan, bisa ditebak, arah memberitaan media di Sulsel seperti apa ketika itu.
Fajar menayangkan berita berjudul: ‘Mengaku Dukung LGBT, NA-ASS Ibarat Pelihara Bom Waktu’. GoSulsel.com, berjudul: ‘Waduh, Nurdin Abdullah-Sudirman Sulaiman Dukung LGBT’. Tribun Timur: ‘NA-ASS Dukung LGBT, Jubir NH-Aziz: Ini Bahaya Bagi Masyarakat Sulsel’.
Judul boleh berbeda, tapi semua berasal dari pers rilis. Isi berita cenderung memojokkan LGBTI, bukan NA-ASS.
Dari serangkaian pemberitaan soal itu, kelompok LGBTI absen sebagai narasumber utama. Saya tidak menemukannya. Satupun. Ketidakhadiran kelompok LGBTI sebagai narasumber berita adalah peminggiran secara sosial budaya.
“[Kelompok LGBTI] dianggap tidak ada keberadaannya. Kemudian, sejarahnya ditiadakan. Orang tidak lagi, mencari sejarah atau riwayat-riwayat keragaman gender dan seksualitas di Indonesia,” kata Dina.
Namun, Dina Listiorini bilang, Kompas hingga 2016 masih kerap menghadirkan keragaman gender dan seksualitas di Indonesia melalui pemberitaannya. Kompas relatif memposisikan kelompok LGBTI sebagai manusia yang kehilangan haknya.
Namun, riset media inklusif berdasarkan keragaman gender dan seksualitas dari Remotivi–lembaga studi dan pemantauan media, mendapuk Tirto.id di urutan pertama.
Peminggiran oleh media bukan hal sepele, begitu pula dengan berita-berita yang negatif menyangkut LGBTI. Dampaknya bahkan, menggoyahkan psikis individu LGBTI.
“Kepercayaan diri [individu LGBTI] bisa berkurang,” kata Eman.
Terlebih, katanya, bagi individu yang sama sekali belum mengenyam konsep SOGIESC.
“Itu biasanya lebih tidak percaya kepada dirinya. Merasa bahwa ini [menjadi LGBTI] sebuah kesalahan, sebuah hal yang tidak baik.”
Selama ini, KSM mengkampanyekan keragaman gender dan seksual ke masyarakat, selain memberi penguatan diri bagi individu LGBTI yang terpinggirkan.
“Kami melihat [berita-berita negatif] sebenarnya, bisa melemahkan apa yang sudah kami kerjakan, termasuk bagaimana membangun kepercayaan teman-teman komunitas.”
Di mata Eman, kebencian yang menyasar komunitas LGBTI selama ini, semacam sistem agar orang-orang membenci LGBTI, hingga melakukan persekusi dan kriminalisasi.
“Kayak upaya menghilangkan LGBTI. Kayak mau ki dibasmi. Kayak komando bersama untuk membenci LGBT.”
Bagaimana selanjutnya?
Tribun Timur dan Fajar, berkata tengah berubah dan kelak akan menjadi media yang inklusif, serta menekankan empati kepada komunitas LGBTI di tiap pemberitaan. Saban tahun, Tribun Timur mengirim awaknya buat belajar lebih tentang peliputan minoritas ke Kompas. Sedang Fajar belum pernah melatih wartawannya soal keragaman gender dan seksual.
Selama ini, pedoman bagaimana menulis kelompok minoritas gender dan seksual belum ada. Sisi lain, wartawan, belum banyak memiliki perspektif yang baik tentang minoritas gender dan seksual. Belum lagi, bias si wartawan–dengan latar belakang beragam hingga redaksi medianya. Satu-satunya pedoman—meski kerap dipalingkan, adalah kode etik jurnalistik (KEJ) dari Dewan Pers.
Tapi, Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (Sejuk), beranggapan lain.
“Kode etik 11 pasal itu tidak cukup untuk memberikan panduan, terkait pemberitaan-pemberitaan keragaman seksual dan gender. Karena nggak detail,” kata Ahmad Alex Junaidi, Direktur Sejuk.
“Cuma pasal 8 ada sedikit itu: tidak berdasarkan prasangka [atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan] jenis kelamin. Tapi, apa? Lebih detailnya apa sih? Itu tidak dijelaskan.”
Sejuk bersama organisasi wartawan, katanya telah menyusun pedoman peliputan kelompok minoritas—termasuk minoritas gender dan seksual.
“Itu sudah diserahkan ke Dewan Pers. Ini semacam panduan pelengkap dari kode etik.”
Bila Kode Etik Jurnalistik/ KEJ belum cukup, sementara pedoman belum ada, maka bagaimana dengan uji kompetensi wartawan?
Saya lantas mengecek nama-nama awak redaksi Fajar Online dan Tribun Timur, melalui data Sertifikasi Wartawan Dewan Pers.
Di jajaran Fajar Online, Edy Arsyad, Direktur, Arsyad Hakim, dan Pemimpin Redaksi, Rasid Alfarizi telah sertifikasi. Sedang Tribun Timur, Wakil Pemimpin Redaksi, Nur Thamzil Thahir dan beberapa awaknya dominan telah sertifikasi.
Tapi, apakah sertifikasi menjamin?
“Aku setuju, bahwa sertifikasi itu tidak menjamin. Memang benar,” kata Alex.
“Di daerah—saya tidak mau sebut nama organisasi yang suka bikin sertifikasi, [hanya] ngejar setoran sertifikasi.”
Dewan Pers, sejak 2010, melakukan sertifikasi wartawan, lewat uji kompetensi. Penyelenggara adalah organisasi profesi, macam Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Juga lembaga pendidikan pers, perguruan tinggi, dan badan usaha pers. Di Sulsel, Fajar adalah satu penyelenggara uji kompetensi.
Ada tiga jenjang uji kompetensi: dari wartawan muda, wartawan madya, hingga wartawan utama. Satu diantara tujuan uji kompetensi adalah meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan.
Dalam uji kompetensi, kata Alex, umumnya hanya mempelajari hal dasar, menembus narasumber, dan mendalami KEJ.
“Cover both side, ditanya. Itukan biasa aja. Itu nggak menjamin, tulisan-tulisan tidak bias terhadap kelompok minoritas—agama, gender dan seksual. Malah kalau waktu wawancara, kalau misalnya, nggak punya perspektif, nanti wartawannya justru–bisa saja, menyudutkan kelompok-kelompok minoritas. Memang, dia dapat beritanya. Tapi karena tidak punya perspektif gender, sehingga timbul bias.”
“Saya melihat dari teman-teman yang ikut, [uji kompetensi] tidak memasukkan soal perspektif, soal toleransi pada keragaman seksualitas. Tapi bukan berarti jelek, Ya. Saya nggak menentang, tapi [memang] tidak menjamin.”
Melihat media bagai mimbar para pengujar kebencian kepada kelompok LGBTI, membuat saya mengingat istilah jurnalisme semu, yang dipakai Bill Kovach, pengajar jurnalisme. Ketika media tidak menengahi debat publik dengan fakta memadai. Reportase berubah sekadar ‘meminjam mulut’ penentang dan kecanduan isu yang terpolarisasi. Jurnalisme semu hanya menebar provokasi dan memupuk kebencian.
Tapi, pemberitaan negatif tentang LGBTI mulai berkurang, menurut pantauan KSM. Harapan bahwa media kelak lebih baik, belum pupus.
“Sangat besar sih harapannya. Dan saya yakin, masih banyak jurnalis-jurnalis yang menghargai keragaman. Dan beberapa media mulai baik,” kata Eman.
(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)